Kajian Film Zombie
Gambar: dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan
Kajian budaya terhadap film zombie menawarkan wawasan mendalam tentang berbagai aspek politik, sosial, dan ideologis. Genre ini telah berkembang dari sekadar hiburan horor menjadi sebuah medium yang sering mencerminkan ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat terhadap dinamika politik tertentu. Berikut adalah beberapa tema kunci dalam kajian budaya film zombie dan relevansinya dalam politik:
1. Zombie Sebagai Alegori Politik dan Ketakutan Kolektif
Film zombie sering kali digunakan sebagai alegori politik untuk menggambarkan ketakutan kolektif terhadap krisis sosial, ekonomi, atau politik. Misalnya, film “Night of the Living Dead” (1968) karya George A. Romero, dianggap mencerminkan ketegangan rasial dan ketidakadilan sosial di Amerika Serikat pada era hak-hak sipil. Zombie dalam film ini melambangkan massa tak berwajah yang mengancam tatanan sosial yang mapan, sementara para protagonis manusia mencoba bertahan di tengah ancaman tersebut.
Dalam konteks politik, zombie sering diasosiasikan dengan kondisi krisis atau disintegrasi. Kehadiran zombie dapat menggambarkan ketakutan terhadap kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, atau ketakutan terhadap “yang lain” (the other), yaitu kelompok yang dianggap mengancam tatanan sosial. Dalam film seperti “28 Days Later” (2002) dan “World War Z” (2013), ketakutan terhadap pandemi global dan ancaman terorisme pasca 9/11 menjadi cermin dari kecemasan terhadap keamanan nasional.
2. Zombie dan Kapitalisme
Kajian budaya sering mengaitkan zombie dengan kritik terhadap kapitalisme dan konsumsi berlebihan. Dalam film “Dawn of the Dead” (1978), Romero menggambarkan para zombie yang berkeliaran di mal sebagai representasi masyarakat konsumtif yang terjebak dalam siklus belanja tanpa henti. Zombie menjadi simbol dari pekerja yang tidak berpikir, terjebak dalam rutinitas kapitalisme yang mengeksploitasi, dan manusia modern yang telah kehilangan otonomi dan kreativitasnya.
Film zombie modern juga kerap menyoroti isu globalisasi dan ketidaksetaraan ekonomi. Dalam film “Train to Busan” (2016), ada kritik tersirat terhadap perbedaan kelas sosial di Korea Selatan. Para tokoh yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses ke sumber daya dan perlindungan, sementara mereka yang berasal dari kelas bawah harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup.
3. Zombie dan Kekuasaan Pemerintah
Film zombie sering menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani krisis, menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam banyak narasi, pemerintah digambarkan sebagai tidak kompeten, terlalu lamban, atau bahkan korup dalam menghadapi wabah zombie. Misalnya, dalam “Resident Evil” series, pemerintah dan perusahaan multinasional besar seperti Umbrella Corporation digambarkan sebagai kekuatan jahat yang mengeksploitasi situasi krisis demi keuntungan mereka sendiri.
Ketidakpercayaan terhadap otoritas ini juga muncul dalam film “The Walking Dead”, di mana tidak ada lagi struktur pemerintah yang berfungsi, dan masyarakat terpaksa mengandalkan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang dianggap gagal dalam menangani krisis besar seperti bencana alam, resesi ekonomi, atau pandemi.
4. Zombie dan Identitas Kolektif
Dalam banyak film zombie, batas antara “manusia” dan “zombie” menjadi kabur, menggambarkan krisis identitas kolektif. Zombie sering dilihat sebagai representasi dari hilangnya identitas individu dan munculnya identitas massa yang homogen. Hal ini mencerminkan ketakutan terhadap hilangnya otonomi pribadi di bawah rezim politik otoriter atau dalam masyarakat yang sangat terstruktur dan terkontrol.
Dalam “I Am Legend” (2007), misalnya, karakter utama harus berhadapan dengan perubahan drastis dalam demografi manusia yang membuatnya mempertanyakan apa arti menjadi manusia. Dalam konteks politik, ini dapat diartikan sebagai ketakutan terhadap perubahan sosial yang terlalu cepat, seperti migrasi massal atau perubahan politik radikal.
5. Zombie dalam Politik Kontemporer
Film zombie sering kali digunakan untuk menggambarkan kondisi politik kontemporer, termasuk ketakutan terhadap perubahan iklim, pandemi, atau bahkan gerakan politik populis. Misalnya, pandemi COVID-19 memicu kembali ketertarikan pada film dan serial zombie karena tema-tema tentang wabah global dan ketidakpastian sosial menjadi semakin relevan.
Di beberapa karya modern, seperti serial “Kingdom” dari Korea Selatan, wabah zombie yang terjadi dalam konteks sejarah Joseon juga menawarkan komentar politik mengenai kekuasaan, korupsi, dan ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat. Ini menunjukkan bahwa narasi zombie tidak terbatas pada latar modern, tetapi bisa digunakan dalam berbagai latar waktu untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan, krisis, dan masyarakat.
6. Zombie dan Narasi Perbatasan: Isu Imigrasi dan Xenofobia
Salah satu tema penting dalam kajian film zombie adalah bagaimana genre ini sering mencerminkan ketakutan terhadap “yang lain” (the other), khususnya dalam konteks perbatasan nasional dan migrasi. Zombie sering kali digambarkan sebagai kekuatan asing yang tak terbendung, menyerbu wilayah yang aman dan melanggar batas-batas yang sebelumnya dianggap tak bisa ditembus. Hal ini memiliki relevansi politik yang jelas terhadap isu-isu seperti imigrasi dan xenofobia.
Film zombie seperti “World War Z” menggambarkan zombie sebagai ancaman global yang melintasi batas-batas nasional. Negara-negara dengan perbatasan kuat, seperti Israel dalam film tersebut, digambarkan sebagai yang paling siap menghadapi wabah zombie. Namun, ketika batas tersebut akhirnya dilanggar, narasi ini mencerminkan ketakutan terhadap ancaman eksternal, seperti imigran atau kelompok asing yang dianggap membawa ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial.
Ketakutan ini semakin relevan dalam konteks politik global saat ini, di mana wacana populis di beberapa negara Barat sering kali mengkonstruksikan imigran sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan identitas budaya. Dalam kajian budaya, film zombie dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari ketakutan terhadap percampuran budaya dan keruntuhan identitas nasional akibat imigrasi.
7. Zombie dan Pandemi: Kritik terhadap Respons Kesehatan Publik
Film zombie kerap digunakan sebagai analogi untuk pandemi atau krisis kesehatan global. Hal ini menjadi semakin relevan selama pandemi COVID-19, di mana banyak film dan serial zombie mulai menarik perhatian baru. “Contagion” (2011), meski bukan film zombie, telah kembali populer karena kemiripannya dengan pandemi COVID-19, dan film zombie pada umumnya sering kali mengandung kritik terhadap respons pemerintah dan institusi kesehatan dalam menghadapi krisis.
Film “Train to Busan” tidak hanya menggambarkan ketakutan terhadap penyebaran wabah, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana tanggapan pemerintah yang lambat dan kurang efektif memperburuk keadaan. Wabah zombie dalam film ini menyoroti bagaimana masyarakat terpecah akibat ketidakmampuan otoritas dalam menangani krisis secara cepat dan efektif. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan kesehatan dan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana besar.
8. Perlawanan terhadap Hegemoni: Zombie sebagai Simbol Revolusi
Dalam beberapa kajian, zombie juga dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni politik atau sosial. Zombie yang bangkit dan menyerbu peradaban manusia bisa dilihat sebagai lambang dari pemberontakan massa melawan sistem yang represif. Mereka adalah simbol dari kekuatan bawah tanah yang menentang otoritas dan kekuasaan yang mapan.
Salah satu contoh adalah “Land of the Dead” (2005), di mana zombie mulai menunjukkan kemampuan untuk berpikir dan berorganisasi, yang mencerminkan semangat revolusi dan perlawanan terhadap penindasan. Mereka tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial. Ini dapat dikaitkan dengan gerakan protes atau revolusi sosial dalam dunia nyata, di mana kelompok yang sebelumnya tertindas bangkit untuk menantang ketidakadilan.
9. Zombie dalam Konteks Politik Populis
Film zombie juga dapat dikaitkan dengan munculnya politik populis di berbagai belahan dunia. Populisme sering kali memanfaatkan ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap ancaman eksternal atau perubahan besar, seperti migrasi atau krisis ekonomi. Dalam konteks ini, zombie melambangkan massa yang “tidak rasional” yang dikendalikan oleh ketakutan dan kecemasan, serta siap menyerang institusi yang mapan.
Narasi semacam ini dapat ditemukan dalam film seperti “The Purge” series, di mana zombie atau massa yang menyerang sering kali digambarkan sebagai kelompok yang termarjinalkan dan siap untuk menghancurkan tatanan yang ada. Di dunia nyata, wacana populis sering kali memanfaatkan ketakutan yang sama terhadap “yang lain” dan menawarkan solusi yang simplistik untuk masalah kompleks.
10. Zombie dan Ketidakpastian Masa Depan
Akhirnya, salah satu relevansi politik paling umum dari film zombie adalah refleksi ketidakpastian masa depan. Di dunia yang semakin kompleks, dengan tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan ekonomi, zombie mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap apa yang akan datang. Wabah zombie menjadi simbol dari kehancuran sistematis, yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu tetapi juga seluruh struktur sosial.
Dalam film “The Girl with All the Gifts” (2016), kita melihat bagaimana zombie baru yang lebih kuat dan cerdas muncul, menantang status quo dan memaksa manusia untuk menghadapi perubahan yang tak terhindarkan. Ini mencerminkan ketakutan terhadap masa depan di mana manusia mungkin kehilangan kontrol atas lingkungan mereka, baik secara sosial, politik, maupun ekologis.
11. Zombie dan Keseimbangan Ekologis: Krisis Lingkungan dan Politik Hijau
Film zombie juga dapat dilihat sebagai refleksi dari krisis lingkungan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Dalam beberapa film, wabah zombie terjadi karena eksperimen manusia yang mengganggu keseimbangan alam atau karena bencana ekologis yang tidak dapat dihentikan. Misalnya, dalam film “The Crazies” (2010), krisis dimulai akibat kontaminasi air yang terinfeksi oleh senjata biologis, dan dalam “Resident Evil” series, wabah zombie dimulai dari eksperimen genetika yang gagal.
Narasi ini sering kali dikaitkan dengan perdebatan tentang perusakan lingkungan dan bagaimana kapitalisme memprioritaskan keuntungan ekonomi daripada menjaga keseimbangan ekologis. Wabah zombie menjadi simbol dari konsekuensi bencana yang diakibatkan oleh manusia sendiri. Dalam kajian budaya, zombie sering dilihat sebagai representasi dari kehancuran lingkungan yang akhirnya memaksa manusia untuk menghadapi realitas krisis ekologi yang tidak dapat dihindari.
Politik hijau dan isu-isu terkait dengan perubahan iklim juga sering ditemukan dalam film-film zombie modern. Zombie dapat dipahami sebagai cerminan dari ancaman yang semakin nyata akibat perubahan iklim, seperti bencana alam, kerusakan lingkungan, dan kekurangan sumber daya. Dalam konteks ini, zombie bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman ekologis yang lebih besar, yang memperingatkan kita tentang perlunya tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
12. Zombie dan Teknologi: Ketakutan terhadap Kemajuan Teknologi
Di era teknologi tinggi, film zombie juga sering mengeksplorasi ketakutan terhadap perkembangan teknologi yang tidak terkendali. Wabah zombie yang disebabkan oleh eksperimen ilmiah yang gagal atau kecelakaan teknologi menggambarkan ketakutan manusia terhadap efek samping dari inovasi teknologi. Film seperti “Resident Evil” dan “I Am Legend” menggambarkan dunia di mana upaya manusia untuk mencapai keabadian atau kekuatan super malah berakhir dengan menciptakan kekacauan dan kehancuran.
Zombie dalam film ini menjadi simbol dari kegagalan manusia dalam mengendalikan teknologi yang mereka ciptakan. Ketakutan ini sangat relevan dalam diskusi tentang kecerdasan buatan (AI), bioteknologi, dan robotika, di mana banyak orang khawatir bahwa kemajuan teknologi yang tidak terkendali dapat berakhir dengan malapetaka global. Wabah zombie menjadi peringatan tentang batas-batas etika dalam inovasi teknologi, serta potensi bahaya yang muncul ketika manusia kehilangan kontrol atas ciptaannya sendiri.
13. Zombie dan Fobia Sosial: Ketakutan terhadap Kolektivisme
Selain ketakutan terhadap perpecahan masyarakat, zombie juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketakutan terhadap kolektivisme dan homogenitas. Dalam banyak film zombie, identitas individu terhapus dan digantikan oleh massa yang homogen, tanpa pikiran atau keinginan sendiri. Ini bisa dianggap sebagai metafora untuk ketakutan terhadap ideologi-ideologi totaliter atau rezim politik yang menghapuskan perbedaan individu dan memaksakan keseragaman.
Dalam konteks politik, zombie dapat merepresentasikan ketakutan terhadap gerakan sosial besar yang dianggap mengancam kebebasan individu. Misalnya, dalam beberapa kajian, zombie sering dikaitkan dengan ketakutan terhadap komunisme atau fasisme, di mana massa yang tidak berpikir digambarkan sebagai ancaman terhadap masyarakat demokratis yang beragam. Ketakutan ini juga bisa ditemukan dalam film “Invasion of the Body Snatchers” (1956), yang walaupun bukan film zombie, berbagi tema yang sama tentang hilangnya individualitas di bawah ancaman kolektif yang kuat.
14. Zombie dan Ruang Urban: Kritik terhadap Kota Modern
Kota-kota besar sering kali menjadi latar utama dalam film zombie, di mana wabah berkembang pesat di lingkungan urban yang padat penduduk. Ini mencerminkan kecemasan terhadap kehidupan di kota modern, yang sering digambarkan sebagai tempat yang penuh tekanan, alienasi, dan ketidakpastian. Dalam kajian budaya, kota dalam film zombie sering diinterpretasikan sebagai simbol dari kerusakan sosial dan ketidakmampuan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam ruang perkotaan yang padat dan tidak ramah.
Film “Dawn of the Dead” menggambarkan mall sebagai simbol dari konsumsi yang berlebihan, sementara film “28 Days Later” menampilkan kota London yang sepi dan hancur sebagai lambang dari kehancuran peradaban modern. Kota dalam film zombie sering kali digambarkan sebagai tempat di mana tatanan sosial runtuh dengan cepat, menunjukkan bahwa infrastruktur perkotaan yang padat dan terorganisir sebenarnya rapuh dan rentan terhadap krisis.
15. Zombie dan Isu Keamanan Global
Dalam banyak film zombie, wabah ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas menjadi ancaman global. Ini mencerminkan ketakutan terhadap ancaman global seperti terorisme, perang nuklir, atau pandemi yang tidak mengenal batas negara. Film seperti “World War Z” dan “Train to Busan” menunjukkan bagaimana negara-negara bereaksi terhadap krisis global, serta bagaimana wabah zombie dapat memperburuk ketegangan politik dan sosial di tingkat internasional.
Ketakutan terhadap keamanan global ini juga terkait dengan kebijakan luar negeri dan militerisme. Zombie sering kali melambangkan ancaman yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan militer tradisional, yang menantang konsep keamanan nasional dan internasional. Dalam “World War Z”, misalnya, militer global berjuang untuk mengatasi wabah zombie, menunjukkan bahwa ancaman global yang baru membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif daripada sekadar kekuatan militer.
16. Zombie dan Trauma Kolektif: Refleksi atas Perang dan Genosida
Film zombie sering kali berfungsi sebagai metafora untuk trauma kolektif yang dihasilkan oleh perang, genosida, dan kekerasan massal. Dalam konteks ini, zombie mewakili kenangan kelam yang terus menghantui masyarakat, seperti halnya korban perang atau kekejaman pemerintah otoriter yang tak bisa dilupakan. Dalam “Land of the Dead” (2005), George A. Romero menggambarkan zombie sebagai kaum tertindas yang akhirnya bangkit melawan elit yang mapan, sebuah refleksi dari ketidakadilan sosial yang muncul pasca konflik besar atau perang.
Film zombie pasca-Perang Dunia II, seperti “Night of the Living Dead” (1968), sering dipahami sebagai alegori trauma pasca-perang dan ketidakmampuan masyarakat untuk memulihkan diri dari kekerasan dan kematian massal. Zombie menjadi lambang dari ketakutan bahwa sejarah kelam bisa terulang kembali dan bahwa luka kolektif dari perang atau kekerasan tidak bisa dengan mudah dihapus dari ingatan.
Dalam konteks genosida, zombie dapat diartikan sebagai representasi korban yang tidak bisa dikuburkan dengan layak, yang terus menghantui pelaku dan masyarakat yang gagal mengakui atau menebus dosa-dosa masa lalu. Narasi ini memiliki relevansi dalam politik kontemporer yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan transisional.
17. Zombie dan Kegagalan Neoliberalisme
Zombie juga bisa dilihat sebagai simbol dari kegagalan neoliberalisme dan sistem kapitalis global yang menghadapi krisis ekonomi dan sosial. Pandangan ini muncul terutama dalam film-film yang menampilkan masyarakat yang kacau akibat wabah, di mana ketidaksetaraan sosial semakin memburuk. Dalam “Snowpiercer” (2013), meskipun bukan film zombie, perpecahan kelas yang ekstrem akibat kapitalisme menjadi tema utama, dan dalam banyak film zombie, krisis ini diperburuk oleh ketidakmampuan negara untuk melindungi warganya.
Dalam “The Walking Dead”, kita melihat bagaimana sistem ekonomi kapitalis runtuh dan digantikan oleh tatanan baru di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan. Sumber daya yang terbatas menciptakan persaingan ekstrem di antara manusia yang tersisa, mencerminkan ketidakadilan ekonomi dalam sistem neoliberalisme, di mana kelompok elit memiliki akses ke sumber daya sementara yang lainnya berjuang untuk bertahan hidup.
18. Zombie dan Feminisme: Peran Gender dalam Narasi Zombie
Kajian feminis terhadap film zombie mengeksplorasi bagaimana genre ini sering kali mereproduksi atau menantang peran gender tradisional. Dalam banyak film zombie klasik, perempuan sering digambarkan sebagai korban yang pasif atau objek penyelamatan oleh laki-laki. Namun, seiring berkembangnya genre ini, banyak film zombie mulai menampilkan karakter perempuan yang kuat dan mandiri.
Film seperti “Resident Evil” menampilkan protagonis perempuan, Alice, yang menjadi pemimpin dalam perjuangan melawan zombie. Ini mencerminkan pergeseran dalam representasi gender di mana perempuan bukan lagi korban, tetapi agen aktif dalam mengatasi krisis. Dalam “28 Days Later”, karakter perempuan memainkan peran penting dalam menyelamatkan kelompok dari ancaman zombie, menantang stereotip gender tradisional.
Kajian feminis juga menyoroti bagaimana film zombie sering kali mengeksplorasi ketakutan terhadap tubuh perempuan, khususnya dalam konteks kehamilan dan kelahiran. Dalam “Dawn of the Dead” (2004), misalnya, ada adegan ikonik tentang seorang perempuan hamil yang menjadi zombie, yang mencerminkan kecemasan tentang kontrol atas tubuh perempuan dan reproduksi.
19. Zombie dan Posthumanisme: Pengaburan Batas antara Manusia dan Non-Manusia
Kajian posthumanisme dalam film zombie mengeksplorasi pengaburan batas antara manusia dan non-manusia. Zombie, sebagai makhluk setengah mati yang tetap bergerak dan hidup, menantang konsep tradisional tentang apa artinya menjadi manusia. Dalam beberapa film, seperti “Warm Bodies” (2013), zombie mulai mengembangkan emosi dan hubungan dengan manusia, menunjukkan potensi rekonsiliasi antara yang hidup dan yang mati.
Hal ini mencerminkan wacana posthumanisme yang menantang keunikan manusia sebagai entitas biologis yang berbeda dari hewan atau mesin. Dengan kemajuan teknologi dan bioteknologi, film zombie sering kali mengeksplorasi batas antara kehidupan organik dan buatan, serta bagaimana kemajuan tersebut dapat mengubah pandangan kita tentang kemanusiaan. Zombie dalam hal ini menjadi simbol dari masa depan di mana batas-batas antara manusia dan makhluk non-manusia semakin kabur.
20. Zombie dan Dinamika Identitas: Ras, Etnis, dan Kebangsaan
Film zombie juga menawarkan ruang untuk mengeksplorasi isu-isu identitas rasial, etnis, dan kebangsaan. Dalam “Night of the Living Dead” (1968), karakter utama adalah seorang pria kulit hitam, yang di akhir film secara tragis ditembak oleh regu penyelamat kulit putih, meskipun dia bukan zombie. Ini memberikan komentar tajam tentang rasisme di Amerika Serikat, terutama di era gerakan hak-hak sipil.
Zombie sering kali digambarkan sebagai massa homogen tanpa identitas individu, yang mencerminkan ketakutan terhadap hilangnya identitas budaya dan etnis di tengah globalisasi. Dalam kajian budaya, ini sering dikaitkan dengan ketakutan terhadap migrasi dan homogenisasi budaya akibat kapitalisme global. Zombie mewakili ancaman terhadap perbedaan budaya, di mana identitas yang berbeda dihapus dan digantikan oleh satu kelompok homogen yang menyerang semua yang ada di jalurnya.
Penutup
Film zombie tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium yang kuat untuk mengeksplorasi kecemasan dan ketakutan masyarakat terhadap isu-isu politik dan sosial. Dalam kajian budaya, zombie sering kali menjadi simbol ketakutan kolektif yang mencerminkan keresahan sosial yang muncul di berbagai konteks politik. Mulai dari ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kritik terhadap kapitalisme, hingga respons terhadap migrasi dan pandemi, genre ini terus relevan dalam menggambarkan dinamika politik kontemporer.
Sebagai cermin sosial, film zombie mengangkat berbagai isu penting seperti ketakutan terhadap imigrasi, krisis lingkungan, serta perkembangan teknologi yang tidak terkendali. Zombie juga berfungsi sebagai alegori untuk menggambarkan ketidakadilan, kekuasaan, dan identitas kolektif. Dengan terus berkembangnya genre ini, film zombie menghadirkan kesempatan bagi analisis kritis tentang kekuasaan dan ketidakpastian masa depan masyarakat.
Zombie bukan hanya simbol kehancuran, tetapi juga alat naratif yang kuat untuk mengkritik tatanan sosial, baik dalam konteks ekonomi global maupun ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis. Zombie mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, mulai dari ketakutan terhadap homogenitas sosial hingga ketegangan politik yang berakar pada ketidaksetaraan. Film-film zombie terus menjadi medium efektif dalam mengangkat permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat modern.
Film zombie menawarkan ruang yang kaya untuk mengkaji berbagai persoalan politik dan sosial. Sebagai metafora politik yang terus berkembang, zombie mencerminkan pergolakan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di dunia nyata, dan genre ini akan terus relevan seiring dengan perubahan sosial dan politik di masa depan.
Film zombie mengajak penonton untuk merenungkan krisis identitas, ketidakadilan sosial, dan ancaman terhadap masa depan umat manusia. Melalui lensa yang suram dan penuh ketegangan, film ini berperan penting dalam memperluas pemahaman kita tentang dinamika politik dan sosial kontemporer.
Referensi
Bishop, Kyle. American Zombie Gothic: The Rise and Fall (and Rise) of the Walking Dead in Popular Culture. McFarland, 2010.
Boluk, Stephanie, and Wylie Lenz, eds. Generation Zombie: Essays on the Living Dead in Modern Culture. McFarland, 2011.
Conrich, Ian, ed. Horror Zone: The Cultural Experience of Contemporary Horror Cinema. I.B. Tauris, 2009.
Dendle, Peter. The Zombie Movie Encyclopedia, Volume 2: 2000–2010. McFarland, 2012.
Harper, Stephen. “Zombies, Malls, and the Consumerism Debate: George Romero’s Dawn of the Dead.” Americana: The Journal of American Popular Culture (1900-present), Fall 2002, Volume 1, Issue 2.
Hubner, Laura, Marcus Leaning, and Paul Manning, eds. The Zombie Renaissance in Popular Culture. Palgrave Macmillan, 2015.
Lauro, Sarah Juliet, dan Karen Embry. “A Zombie Manifesto: The Nonhuman Condition in the Era of Advanced Capitalism.” boundary 2, vol. 35, no. 1, 2008.
Lauro, Sarah Juliet. The Transatlantic Zombie: Slavery, Rebellion, and Living Death. Rutgers University Press, 2015.
Luckhurst, Roger. Zombies: A Cultural History. Reaktion Books, 2015.
McNally, David. Monsters of the Market: Zombies, Vampires, and Global Capitalism. Brill, 2011.
Moreman, Christopher M., dan Cory James Rushton, eds. Race, Oppression and the Zombie: Essays on Cross-Cultural Appropriations of the Caribbean Tradition. McFarland, 2011.
Paffenroth, Kim. Gospel of the Living Dead: George Romero’s Visions of Hell on Earth. Baylor University Press, 2006.
Phillips, Kendall R., ed. Projected Fears: Horror Films and American Culture. Praeger, 2005.
Shaviro, Steven. The Cinematic Body. University of Minnesota Press, 1993.
Shaviro, Steven. Post-Cinematic Affect. Zero Books, 2010.
Wetmore, Kevin J. Post-9/11 Horror in American Cinema. Continuum, 2012.
AI: ChatGPT

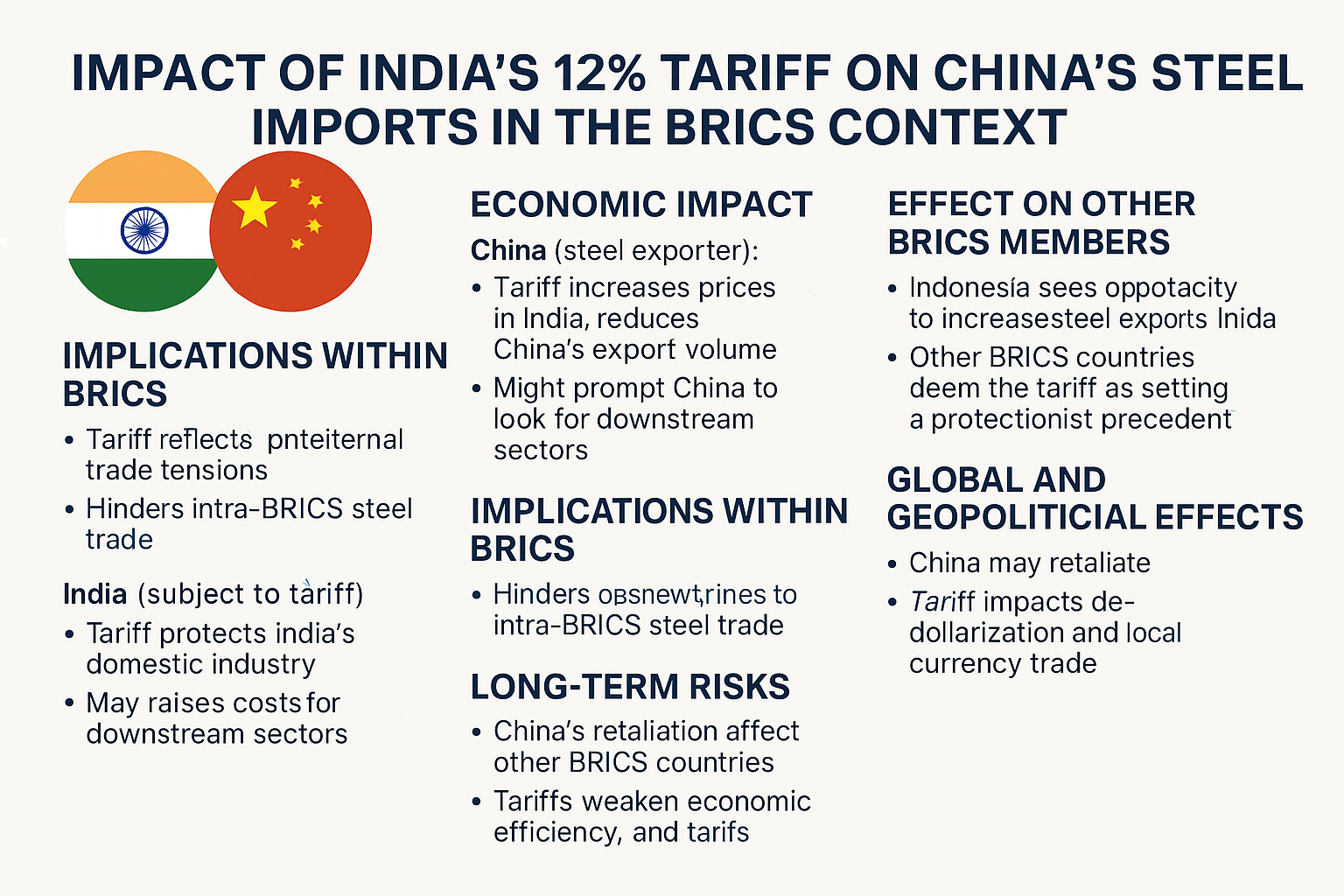

Post Comment