Nobel Ekonomi 2024
Gambar: dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan
Pada 14 Oktober 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson dianugerahi Nobel Ekonomi atas penelitian mendalam mereka yang menghubungkan kegagalan ekonomi negara-negara dengan warisan kolonialisme. Melalui karya mereka yang berpengaruh, terutama dalam buku “Why Nations Fail” dan penelitian akademis lainnya, ketiga ekonom ini membangun sebuah kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana institusi ekonomi dan politik yang diciptakan selama era kolonial terus membentuk nasib ekonomi negara-negara bekas jajahan hingga saat ini (Acemoglu et al., 2000).
Warisan Institusi Eksploitatif
Acemoglu, Johnson, dan Robinson memulai argumen mereka dengan fokus pada salah satu peninggalan paling berbahaya dari kolonialisme: institusi yang eksploitatif. Pada masa kolonial, kekuatan Eropa tidak tertarik untuk menciptakan institusi yang mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah jajahan mereka. Sebaliknya, institusi kolonial didesain untuk mengambil sumber daya sebanyak mungkin dari wilayah tersebut, dan memberikan sedikit perhatian pada kesejahteraan ekonomi atau sosial penduduk lokal. Pengambilalihan tanah, sumber daya alam, dan tenaga kerja terjadi secara masif di bawah kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite kolonial (Maseland, 2017).
Dalam banyak kasus, institusi eksploitatif ini terus berlanjut bahkan setelah negara-negara tersebut memperoleh kemerdekaan. Struktur pemerintahan dan ekonomi yang diwariskan dari kolonialisme tetap tidak inklusif, dirancang untuk mempertahankan status quo, di mana kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang. Akibatnya, negara-negara pascakolonial menghadapi tantangan besar untuk membangun institusi baru yang dapat mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas dan merata (Heldring & Robinson, 2013).
Inklusi vs Eksklusi: Kunci Kegagalan dan Keberhasilan Ekonomi
Salah satu konsep kunci yang dijelaskan oleh ketiga ekonom ini adalah perbedaan antara institusi inklusif dan institusi eksklusif. Institusi inklusif adalah institusi yang memungkinkan partisipasi ekonomi yang luas dan merata, memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui mekanisme pasar yang adil, perlindungan hak-hak properti, dan jaminan kebebasan politik. Di sisi lain, institusi eksklusif cenderung membatasi akses terhadap kekayaan dan kekuasaan hanya kepada sekelompok kecil elite, menghalangi mobilitas sosial dan ekonomi bagi sebagian besar penduduk (Bruhn & Gallego, 2012).
Dalam karya mereka, Acemoglu, Johnson, dan Robinson menjelaskan bagaimana banyak negara di dunia berkembang, terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, mewarisi institusi eksklusif yang dibangun oleh penjajah Eropa. Institusi-institusi ini diciptakan untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, bukan untuk membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Warisan institusi semacam itu menyebabkan negara-negara tersebut terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, bahkan setelah mereka merdeka (Lange et al., 2006).
Geografi, Penyakit, dan Perbedaan Pendekatan Kolonial
Penelitian Acemoglu, Johnson, dan Robinson juga mencakup faktor geografis dan epidemiologis yang memengaruhi jenis institusi kolonial yang didirikan. Mereka berargumen bahwa di wilayah-wilayah yang memiliki iklim dan kondisi yang memungkinkan pemukiman Eropa, seperti Amerika Utara dan Australia, kekuatan kolonial cenderung mendirikan institusi yang lebih inklusif. Institusi ini dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang karena bangsa Eropa melihat wilayah tersebut sebagai tempat yang layak untuk mereka tinggali dan berkembang (Acemoglu et al., 2000).
Sebaliknya, di wilayah-wilayah tropis yang memiliki tingkat penyakit tinggi dan sumber daya alam yang melimpah, seperti Afrika dan sebagian besar Asia, bangsa kolonial cenderung mendirikan institusi yang eksploitatif. Mereka memandang wilayah-wilayah ini sebagai sumber daya yang bisa diambil tanpa perlu membangun masyarakat yang berkembang. Akibatnya, setelah kemerdekaan, banyak negara-negara ini tetap terjebak dalam pola institusi eksklusif yang menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan politik (Heldring & Robinson, 2013).
Dampak Jangka Panjang Kolonialisme: Kesinambungan Institusi dan Ketidaksetaraan
Salah satu sumbangan besar dari karya Acemoglu, Johnson, dan Robinson adalah analisis mereka tentang dampak jangka panjang kolonialisme. Mereka menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan luka sejarah, tetapi juga menciptakan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mendalam dan bertahan lama. Ketimpangan yang diciptakan oleh kolonialisme—baik dalam hal distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, maupun peluang ekonomi—terus memperparah kemiskinan di negara-negara pascakolonial (Maseland, 2017).
Sejarah Lokal dan Tradisi sebagai Faktor Penentu
Salah satu aspek penting dari analisis Acemoglu dan rekan-rekannya adalah pengakuan bahwa tidak semua negara bekas jajahan mengalami kegagalan ekonomi yang sama. Beberapa negara berhasil menciptakan institusi yang lebih inklusif setelah kemerdekaan, meskipun mereka memiliki sejarah kolonial yang brutal. Faktor sejarah dan tradisi lokal memainkan peran penting dalam proses ini. Di beberapa tempat, masyarakat lokal berhasil menolak atau mengadaptasi institusi kolonial yang eksploitatif, sementara di tempat lain, kolonialisme sepenuhnya menggantikan institusi lokal yang lebih inklusif.
Reformasi Institusi sebagai Kunci Pemulihan
Kesimpulan utama dari karya Acemoglu, Johnson, dan Robinson adalah bahwa reformasi institusi menjadi kunci untuk mengatasi kegagalan ekonomi negara-negara yang mewarisi institusi kolonial yang eksploitatif. Mereka menekankan pentingnya menciptakan institusi yang lebih inklusif—yang memungkinkan partisipasi luas dalam ekonomi, melindungi hak-hak properti, dan mendorong inovasi—sebagai syarat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Lange et al., 2006).
Melalui pemikiran ini, Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson telah mengubah cara kita memahami kegagalan ekonomi negara-negara berkembang. Dengan menghubungkan sejarah kolonial dengan ketidakmampuan institusi untuk mendukung pembangunan inklusif, mereka memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami tantangan ekonomi global di masa kini dan masa depan.
Referensi:
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2000). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. MIT Economics Department Working Paper Series. https://doi.org/10.2139/ssrn.244582.
Bruhn, M., & Gallego, F. (2012). Good, Bad, and Ugly Colonial Activities: Do They Matter for Economic Development?. Review of Economics and Statistics, 94, 433-461. https://doi.org/10.1162/REST_a_00218.
Heldring, L., & Robinson, J. (2013). Colonialism and development in Africa. 2012. https://doi.org/10.1093/OXFORDHB/9780199845156.013.10.
Lange, M., Mahoney, J., & Hau, M. (2006). Colonialism and Development: A Comparative Analysis of Spanish and British Colonies1. American Journal of Sociology, 111, 1412 – 1462. https://doi.org/10.1086/499510.
Maseland, R. (2017). Is colonialism history? The declining impact of colonial legacies on African institutional and economic development. Journal of Institutional Economics, 14, 259 – 287. https://doi.org/10.1017/S1744137417000315.
AI: ChatGPT, Consensus



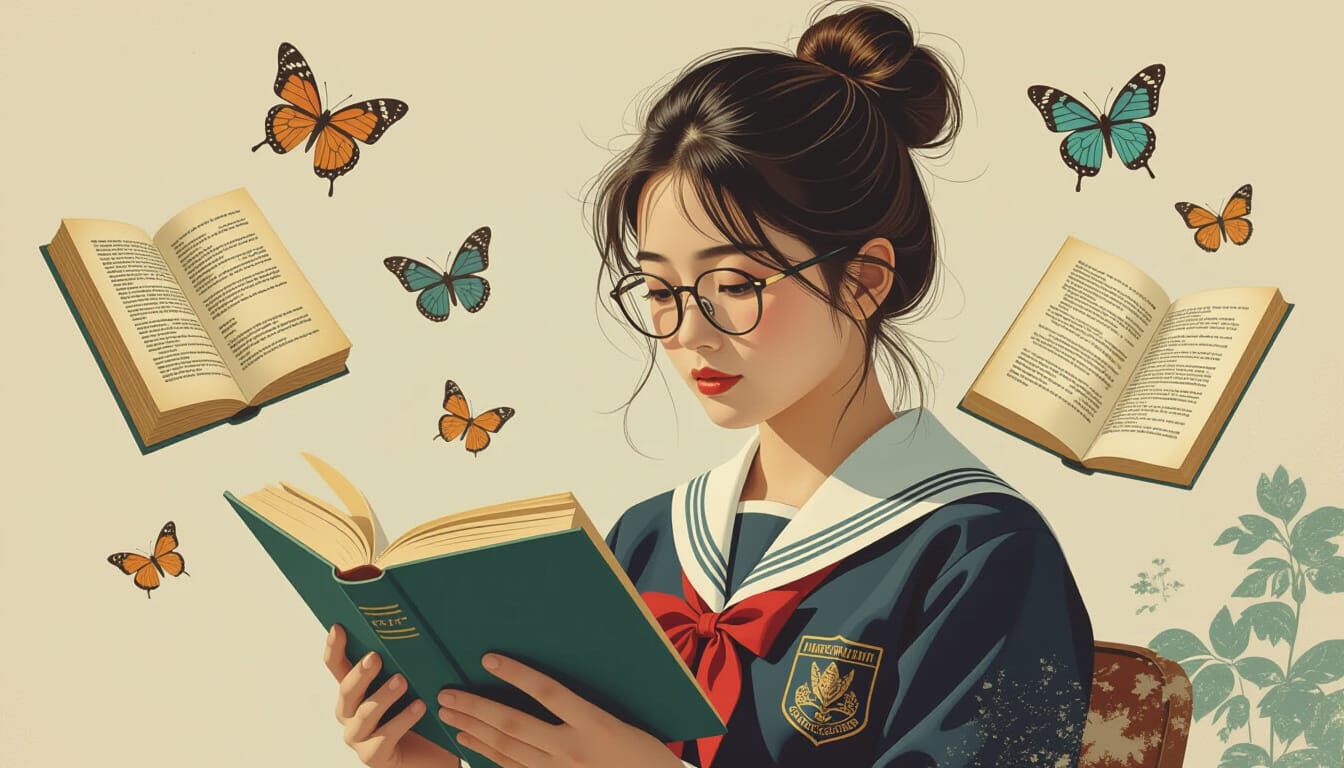
Post Comment