Bisakah Kampus Dituntut Jika Lulusannya Tidak Mendapatkan Pekerjaan?
Gambar: dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan
Bagus Muljadi, seorang akademisi terkemuka, baru-baru melontarkan pertanyaan yang memantik diskusi hangat: “Bisakah kampus dituntut jika lulusannya tidak mendapatkan pekerjaan?” Pertanyaan ini mencuat di tengah realitas meningkatnya biaya pendidikan tinggi dan ekspektasi yang besar dari lulusan terhadap almamater mereka. Dalam lanskap pendidikan modern, terutama di tengah persaingan pasar kerja yang semakin ketat, pertanyaan ini bukan hanya relevan, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai tanggung jawab institusi pendidikan terhadap keberhasilan karier lulusannya.
Tanggung Jawab Kampus: Janji vs. Realitas
Bagi banyak mahasiswa, universitas bukan hanya tempat untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga dianggap sebagai batu loncatan menuju kesuksesan profesional. Iklan-iklan dari berbagai kampus sering kali memamerkan prospek kerja yang menggiurkan, lengkap dengan data statistik lulusan yang diklaim cepat terserap di pasar kerja. Namun, bagaimana jika kenyataan tidak sesuai dengan janji tersebut?
Dalam hubungan antara universitas dan mahasiswa, terdapat kontrak yang sifatnya implisit maupun eksplisit. Mahasiswa membayar biaya kuliah dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan pendidikan berkualitas dan peluang karier yang lebih baik. Namun, sebagian besar universitas tidak pernah secara eksplisit menjamin bahwa lulusannya pasti akan mendapatkan pekerjaan. Mereka umumnya hanya menyediakan layanan tambahan, seperti pelatihan karier, jaringan alumni, dan bursa kerja.
Namun, apakah layanan ini cukup? Bagi sebagian lulusan, kegagalan mendapatkan pekerjaan menjadi beban berat, apalagi ketika mereka sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pendidikan.
Kasus Trina Thompson: Ketika Lulusan Menuntut Kampusnya
Trina Thompson, seorang lulusan Monroe College di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 2009, Trina menggugat almamaternya dengan tuntutan sebesar $72.000, jumlah yang setara dengan biaya pendidikan yang telah ia keluarkan.
Trina berargumen bahwa Monroe College telah gagal memenuhi janji-janjinya. Ia mengklaim bahwa layanan pengembangan karier kampus tersebut tidak memberikan dukungan yang memadai untuk membantunya mendapatkan pekerjaan di bidang Teknologi Informasi, bidang studi yang ia ambil. Selain itu, ia merasa bahwa universitas terlalu melebih-lebihkan prospek kerja dalam materi promosi mereka.
Sebagai lulusan yang baru saja mendapatkan gelar Bachelor of Technology pada April 2009, Trina menghadapi tantangan besar di pasar kerja yang sedang lesu akibat dampak krisis ekonomi global 2008. Namun, baginya, tantangan ini diperparah oleh kurangnya bantuan konkret dari pusat layanan karier universitas yang seharusnya membantunya dalam mencari pekerjaan. Dalam gugatannya, Trina menyatakan bahwa universitas gagal memberikan bimbingan yang efektif, termasuk tidak menawarkan cukup peluang wawancara atau jaringan yang relevan di industri teknologi informasi.
Trina juga menyoroti bahwa Monroe College memasarkan program studinya sebagai pintu masuk menuju karier yang menjanjikan. Klaim ini, menurutnya, tidak sejalan dengan kenyataan yang ia hadapi sebagai lulusan yang masih menganggur berbulan-bulan setelah kelulusan. Dalam wawancaranya dengan media, Trina bahkan menyebutkan bahwa dia merasa “dibiarkan begitu saja” tanpa dukungan yang nyata setelah menyelesaikan studinya.
Namun, kasus ini akhirnya tidak berhasil di pengadilan. Hakim memutuskan bahwa universitas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesulitan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan, terutama jika kampus tersebut telah menyediakan pendidikan sesuai standar. Pengadilan juga menilai bahwa ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, seperti kondisi pasar tenaga kerja, tingkat pengalaman, dan kualifikasi individu.
Meski gugatan ini tidak berhasil, kasus Trina Thompson tetap menarik perhatian publik dan menjadi bahan perdebatan mengenai tanggung jawab universitas terhadap alumninya. Di satu sisi, universitas memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan yang memadai dan membantu mahasiswanya mencapai tujuan karier mereka. Di sisi lain, pengadilan menegaskan bahwa keberhasilan lulusan di pasar kerja tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, melainkan juga bergantung pada upaya individu dan dinamika ekonomi yang lebih luas.
Kasus ini menjadi pengingat bagi para calon mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam memilih institusi pendidikan. Mereka harus memastikan bahwa program studi yang mereka pilih tidak hanya relevan dengan minat mereka, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kasus ini juga mendorong universitas untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada calon mahasiswa dan memperkuat layanan karier mereka agar dapat membantu lulusan menghadapi persaingan di dunia kerja.
Mahasiswa Gugat James Cook University atas Program Studi yang Tidak Terakreditasi
Pada Mei 2023, sekelompok mahasiswa James Cook University (JCU) di Australia meluncurkan gugatan class action terhadap universitas tersebut. Gugatan ini bermula dari program studi utama di bidang Financial Advising (nasihat keuangan) yang ditawarkan oleh JCU, tetapi ternyata tidak memiliki akreditasi yang diperlukan untuk bekerja sebagai penasihat keuangan di Australia. Para mahasiswa mengklaim bahwa mereka telah dirugikan secara finansial dan profesional akibat janji yang mereka anggap menyesatkan dari pihak universitas.
Mahasiswa yang tergabung dalam gugatan ini menyatakan bahwa JCU memasarkan program studi utama Financial Advising sebagai jalan menuju karier profesional di bidang keuangan. Namun, setelah menyelesaikan program tersebut, para lulusan menemukan bahwa gelar mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Financial Adviser Standards and Ethics Authority (FASEA), badan yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akreditasi bagi penasihat keuangan di Australia.
Menurut gugatan, universitas telah gagal memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa mengenai status akreditasi program ini. Mahasiswa merasa telah tertipu, karena mereka telah menginvestasikan waktu, uang, dan tenaga dalam program yang tidak memenuhi standar industri yang diperlukan untuk bekerja di bidang tersebut.
Para mahasiswa yang mengajukan gugatan berpendapat bahwa James Cook University:
- Melakukan Misrepresentasi: Universitas diduga memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap dalam mempromosikan program studi ini sebagai persiapan karier yang sah di bidang nasihat keuangan.
- Melanggar Undang-Undang Konsumen Australia: Gugatan ini juga menyebut bahwa universitas telah melanggar ketentuan di bawah Australian Consumer Law (ACL), yang melarang praktik bisnis yang menyesatkan atau tidak jujur.
- Gagal Memberikan Pendidikan yang Memadai: Program studi ini dianggap tidak memberikan kualifikasi yang relevan atau diperlukan untuk memenuhi persyaratan akreditasi yang berlaku.
JCU, dalam pernyataan resminya, menyatakan bahwa mereka meninjau gugatan tersebut dan berkomitmen untuk mendukung para mahasiswa yang merasa dirugikan. Namun, universitas belum memberikan pengakuan langsung atas kesalahan dalam memasarkan program studi ini.
Pihak universitas juga menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti proses internal untuk mengatasi kekurangan pada program studi Financial Advising, meskipun belum ada pernyataan lebih lanjut tentang langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah akreditasi ini.
Bagi mahasiswa yang terkena dampak, konsekuensi dari program yang tidak terakreditasi sangat signifikan. Mereka tidak hanya kehilangan peluang karier di bidang yang telah mereka persiapkan, tetapi juga mengalami kerugian finansial akibat biaya pendidikan dan waktu yang telah diinvestasikan. Beberapa lulusan harus mengambil kursus tambahan atau program studi baru untuk memenuhi persyaratan akreditasi, yang tentunya menambah beban biaya dan waktu.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama dalam program yang mempersiapkan mahasiswa untuk karier profesional dengan persyaratan akreditasi khusus. Universitas harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan kepada calon mahasiswa benar, akurat, dan mencerminkan realitas yang ada.
Di sisi lain, gugatan ini juga menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk lebih kritis dalam memilih program studi. Melakukan penelitian mendalam mengenai akreditasi dan relevansi program dengan kebutuhan industri sangat penting untuk menghindari kerugian serupa.
Gugatan class action terhadap James Cook University adalah salah satu dari kasus langka yang menyoroti hubungan kompleks antara universitas, mahasiswa, dan ekspektasi karier. Kasus ini berpotensi menciptakan preseden penting bagi institusi pendidikan tinggi di Australia, khususnya terkait tanggung jawab mereka dalam memberikan informasi yang transparan dan pendidikan yang sesuai dengan standar industri.
Seiring dengan perkembangan kasus ini, pertanyaan besar tetap mengemuka: sejauh mana tanggung jawab universitas terhadap keberhasilan karier mahasiswa setelah lulus, dan bagaimana institusi pendidikan dapat memastikan bahwa program yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja?
Bagaimana di Indonesia?
Di Indonesia, kasus lulusan menuntut universitasnya karena gagal mendapatkan pekerjaan masih belum terjadi, tetapi bukan berarti hal tersebut mustahil dilakukan. Dalam konteks hukum, terdapat peluang untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk mahasiswa yang membeli layanan pendidikan, terhadap praktik bisnis yang menyesatkan. Jika universitas terbukti membuat klaim yang tidak realistis atau menyesatkan dalam mempromosikan program studinya, para lulusan memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan.
Misalnya, apabila universitas mengiklankan sebuah program studi sebagai “pintu gerbang menuju karier sukses” atau “menjamin pekerjaan bergaji tinggi setelah lulus,” namun ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka klaim tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk misrepresentasi. Dalam situasi ini, alumni yang merasa dirugikan dapat menuntut universitas atas dasar bahwa janji-janji tersebut tidak terpenuhi, terutama jika mereka telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya pendidikan yang besar.
Namun, menggugat institusi pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi oleh lulusan yang ingin membawa kasus seperti ini ke ranah hukum. Salah satu tantangan utama adalah beban pembuktian. Mahasiswa yang mengajukan gugatan harus mampu menunjukkan bukti bahwa universitas telah melanggar kontrak atau melakukan pelanggaran hukum lainnya, seperti menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan.
Selain itu, faktor eksternal juga menjadi kendala besar dalam kasus seperti ini. Pasar tenaga kerja di Indonesia sangat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan, persaingan antar lulusan, serta relevansi keterampilan individu dengan kebutuhan industri. Jika seorang lulusan gagal mendapatkan pekerjaan, pengadilan akan mempertimbangkan apakah kegagalan tersebut benar-benar disebabkan oleh universitas, ataukah disebabkan oleh faktor lain di luar kendali institusi pendidikan.
Di sisi lain, pengaruh budaya di Indonesia juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kasus gugatan semacam ini. Banyak lulusan yang merasa enggan untuk menggugat universitas mereka karena adanya stigma sosial, rasa segan terhadap almamater, atau ketakutan bahwa tindakan tersebut dapat merusak hubungan mereka dengan institusi yang mungkin masih berperan dalam memberikan dukungan karier.
Meski demikian, kasus gugatan terhadap institusi pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih umum di masa depan seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap institusi pendidikan. Banyak mahasiswa dan orang tua yang mulai mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab universitas dalam membantu lulusan mereka meraih kesuksesan di dunia kerja.
Untuk mencegah potensi sengketa semacam ini, universitas di Indonesia harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai program studinya, termasuk prospek kerja yang realistis dan dukungan karier yang ditawarkan. Selain itu, penguatan layanan bimbingan karier di kampus menjadi sangat penting. Universitas harus lebih proaktif dalam menjembatani lulusan dengan pasar kerja, misalnya melalui program magang, bursa kerja, atau kemitraan dengan perusahaan di berbagai sektor.
Pada akhirnya, kasus seperti ini bukan hanya tentang hak mahasiswa sebagai konsumen, tetapi juga tentang peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, institusi pendidikan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi sengketa hukum di masa depan.
Refleksi: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaan yang diajukan oleh Bagus Muljadi memunculkan diskusi yang mendalam dan fundamental mengenai tanggung jawab institusi pendidikan tinggi terhadap lulusan mereka. Pertanyaan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menggali aspek etika, harapan sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun masa depan generasi muda.
Di satu sisi, universitas memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan ini tidak hanya mencakup transfer pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan praktis, keterampilan kerja, dan wawasan tentang dinamika industri yang relevan. Sebagai institusi yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, universitas juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendukung, seperti bimbingan karier, jaringan alumni, serta koneksi dengan perusahaan dan sektor industri. Janji-janji yang dibuat dalam materi promosi, seperti prospek karier dan keberhasilan lulusan, harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, bukan sekadar strategi pemasaran yang bombastis.
Namun, di sisi lain, keberhasilan karier lulusan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali universitas. Kondisi ekonomi global, tingkat kompetisi di pasar kerja, kebijakan pemerintah terkait lapangan pekerjaan, serta kecocokan individu dengan kebutuhan pasar adalah elemen-elemen yang kompleks dan dinamis. Tidak semua kegagalan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan dapat dibebankan sepenuhnya kepada universitas, terutama jika institusi tersebut telah menyediakan pendidikan dan dukungan yang memadai sesuai standar.
Dari perspektif mahasiswa, kasus-kasus seperti ini juga memberikan pelajaran penting: memilih program studi di perguruan tinggi adalah keputusan besar yang memerlukan pertimbangan matang. Mahasiswa perlu lebih kritis dalam mengevaluasi pilihan mereka, termasuk meneliti akreditasi program studi, prospek kerja, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Ekspektasi yang tidak realistis terhadap pendidikan tinggi dapat memicu kekecewaan yang tidak perlu, terutama jika mereka tidak memahami sepenuhnya tantangan dan dinamika pasar kerja yang akan mereka hadapi setelah lulus.
Bagi universitas, kasus-kasus gugatan lulusan, baik di Indonesia maupun di negara lain, menjadi pengingat kuat bahwa janji-janji mereka harus selaras dengan kenyataan. Promosi yang terlalu ambisius tanpa landasan yang jelas dapat merusak reputasi institusi dan menimbulkan konsekuensi hukum. Universitas harus lebih transparan dan jujur dalam menyampaikan informasi kepada calon mahasiswa. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan layanan bimbingan karier, memperkuat kolaborasi dengan dunia industri, dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Dari sisi dunia industri, kontribusi mereka dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat juga sangat penting. Kolaborasi antara universitas dan industri dapat menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Program magang, kerja sama riset, dan transfer teknologi adalah beberapa bentuk kemitraan yang dapat memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang tanggung jawab dalam kasus ini tidak dapat dijawab secara hitam putih. Tanggung jawab keberhasilan karier lulusan adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan universitas, mahasiswa, pemerintah, dan industri. Solusi terbaik mungkin terletak pada membangun hubungan yang lebih erat dan harmonis antara keempat pihak ini. Universitas dapat berfungsi sebagai jembatan yang kokoh, tetapi jembatan tersebut harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat: pendidikan berkualitas, bimbingan karier yang efektif, keterampilan individu yang relevan, dan peluang dari industri.
Dengan pendekatan yang kolaboratif ini, pendidikan tinggi tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga menjadi landasan untuk masa depan profesional yang cerah dan berkelanjutan. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar menjadi investasi yang berharga bagi mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan.
Referensi:
Collini, Stefan. What Are Universities For? Penguin Books, 2012.
Davidson, Helen. “Students Launch Class Action Against James Cook University Over Unaccredited Financial Advice Major.” The Guardian, 3 Mei 2023.
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/may/03/students-launch-class-action-against-james-cook-university-over-unaccredited-financial-advice-major
“Graduate Sues College Over Lack of Job.” The Guardian, 3 Agustus 2009.
https://www.theguardian.com/world/2009/aug/03/graduate-sues-college
Malaka. 15 Januari 2025. Bahas Riset, Pendidikan, dan Logika Mistika Bersama Bagus Muljadi. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=hvoHdMR1XRI
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
AI: ChatGPT



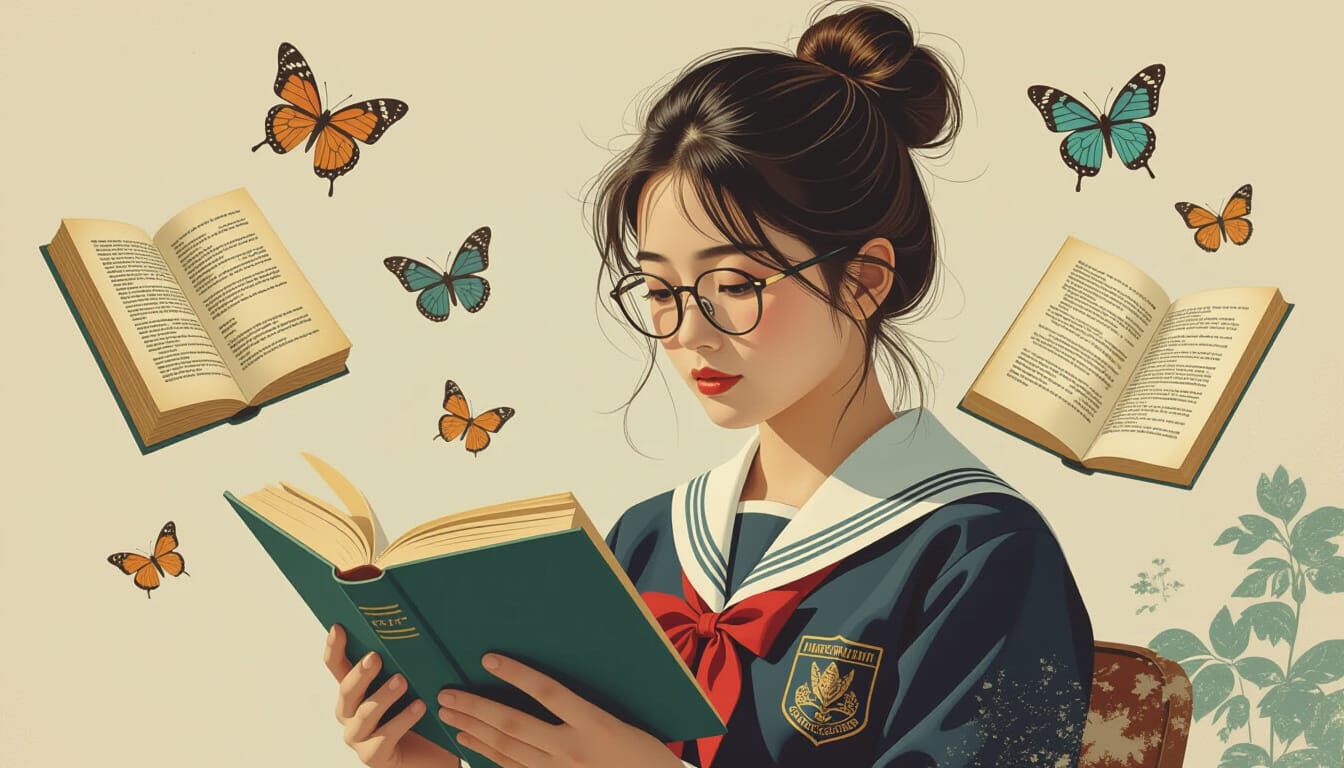
Post Comment