Hari Filsafat Sedunia 2025: Lebih dari Sekadar Peringatan, Sebuah Seruan Mendesak di Tengah Krisis Makna Global
Setiap Kamis ketiga bulan November—tahun ini jatuh tepat pada 20 November 2025—dunia memperingati Hari Filsafat Sedunia (World Philosophy Day) yang ditetapkan UNESCO sejak 2002. Di balik kesan seremonial, peringatan ini sebenarnya adalah alarm keras: filsafat bukan lagi kemewahan intelektual kelas menengah atas yang duduk di kafe Paris sambil membaca Sartre, melainkan kebutuhan mendesak umat manusia yang sedang kehilangan arah di era kecerdasan buatan, polarisasi politik, dan kehancuran iklim.
Mengapa Filsafat Dibutuhkan Lebih Dari Sebelumnya?
Manusia modern sedang mengalami apa yang oleh filsuf Korea-Byung-Chul Han disebut “krisis narasi”. Kita memiliki lebih banyak informasi daripada kapan pun dalam sejarah, tapi semakin sedikit makna. Algoritma media sosial menciptakan gelembung realitas yang membuat kita yakin bahwa “kebenaran” adalah apa yang paling sering muncul di feed. Politik identitas menggantikan perdebatan ide dengan pertarungan tribal. Sains dan teknologi melaju kencang, tapi pertanyaan “untuk apa?” dan “apakah ini baik?” semakin jarang ditanyakan.
Di sinilah filsafat kembali menjadi relevan—bukan sebagai disiplin akademis yang kaku, tapi sebagai latihan berpikir kritis, meragukan, dan membayangkan alternatif. Hari Filsafat Sedunia 2025 mengangkat tema implisit (dan kadang eksplisit di berbagai negara) tentang “Filsafat di Era Antroposin dan Teknologi”: bagaimana kita mendefinisikan ulang kemanusiaan ketika mesin bisa melukis, menulis puisi, bahkan “berpikir” lebih cepat dan akurat daripada kita?
Tema-Tema Besar yang Mengemuka Tahun Ini
- Kemanusiaan Pasca-AI
Dengan munculnya model bahasa besar dan robot humanoid seperti Optimus, pertanyaan klasik “Apa itu manusia?” kembali menggelegar. Apakah kesadaran, kreativitas, atau empati yang membedakan kita—orang-orang mulai curiga bahwa jawaban tradisional itu rapuh. Di berbagai seminar Hari Filsafat Sedunia tahun ini, dari Paris sampai Yogyakarta, muncul diskusi apakah kita sedang menuju era “post-human” atau justru perlu kembali ke akar kemanusiaan yang paling sederhana: kemampuan untuk menderita, mencintai, dan mati. - Etika Iklim dan Tanggung Jawab Antar-Generasi
Di tengah COP30 yang sedang berlangsung di Brasil, filsafat iklim menjadi sorotan. Apakah kita berutang kepada generasi mendatang yang bahkan belum lahir? Apakah konsep “keadilan” masih relevan ketika negara kaya historically bertanggung jawab atas emisi, tapi negara miskin yang paling menderita? Filsuf seperti Roman Krznaric dengan konsep “good ancestor” atau orang Indonesia seperti Rocky Gerung yang kerap mengkritik penguasa, menjadi rujukan penting. - Filsafat di Ruang Publik dan Demokrasi yang Sakit
Banyak negara mengalami kemunduran demokrasi: populisme, hoaks, dan politik berbasis emosi bukan argumen. Hari Filsafat Sedunia menjadi momen untuk mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang terlatih berpikir dialektis (tesis-antitesis-sintesis), bukan sekadar memilih berdasarkan like atau dislike. Di Indonesia sendiri, diskusi filsafat di kampus-kampus sering kali mati suri karena dianggap “tidak praktis” atau bahkan berbahaya bagi rezim yang anti-kritik. - Filsafat Timur dan Dekolonisasi Pemikiran
Tahun ini, ada gelombang kuat untuk mengangkat filsuf-filsuf non-Barat: Ibnu Rusyd, Mulla Sadra, Zhu Xi, Nagarjuna, sampai pemikiran Nusantara seperti Ki Ageng Suryomentaram atau Sutan Takdir Alisjahbana. Ini bukan sekadar political correctness, tapi pengakuan bahwa Barat bukan satu-satunya sumber kebijaksanaan. Di era ketika “pengetahuan” didominasi oleh jurnal berbahasa Inggris dan universitas Ivy League, Hari Filsafat Sedunia menjadi ruang perlawanan intelektual.
Di Indonesia: Filsafat yang Selalu “Terlambat” Datang
Di Indonesia, peringatan Hari Filsafat Sedunia biasanya berlangsung sederhana: seminar di kampus besar, diskusi di komunitas kecil seperti di Yogyakarta, atau cuitan-cuitan di media sosial. Jarang sekali masuk berita utama. Ini ironis, karena bangsa Indonesia sebenarnya sangat filosofis dalam kehidupan sehari-hari: gotong royong, musyawarah, hidup rukun dengan alam—semua itu adalah filsafat praktis yang hidup. Tapi filsafat sebagai disiplin sering dianggap “barang impor” yang tak berguna dibandingkan teknik atau ekonomi.
Padahal, di tengah maraknya politik identitas, korupsi sistemik, dan krisis ekologis, Indonesia justru sangat membutuhkan filsafat untuk bertanya hal-hal dasar: Apa itu bangsa yang adil dan beradab? Apakah pembangunan yang mengorbankan hutan dan masyarakat adat masih bisa disebut “pembangunan”? Siapa yang berhak menentukan “kebenaran” di era pasca-kebenaran?
Filsafat Bukan Jawaban, Tapi Seni Bertanya yang Baik
Hari Filsafat Sedunia bukan pesta intelektual elit. Ia adalah pengingat bahwa setiap orang—petani di sawah, driver ojol di kemacetan Jakarta, ibu rumah tangga di kampung—sebenarnya sudah berfilsafat setiap hari ketika bertanya: “Hidup ini untuk apa?” “Apakah saya sudah cukup baik?” “Apa yang harus saya lakukan besok?”
Di tahun 2025 ini, ketika dunia terasa semakin cepat, semakin bising, dan semakin kehilangan arah, peringatan ini mengajak kita semua untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menemukan jawaban akhir (karena filsafat tahu bahwa jawaban akhir sering kali adalah ilusi), tapi untuk belajar bertanya dengan lebih jujur, lebih dalam, dan lebih berani.
Karena di akhirnya, seperti kata Socrates dua ribu tahun lalu, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Di tengah semua krisis abad ke-21 ini, mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa menyelamatkan kita.
AI: Grok
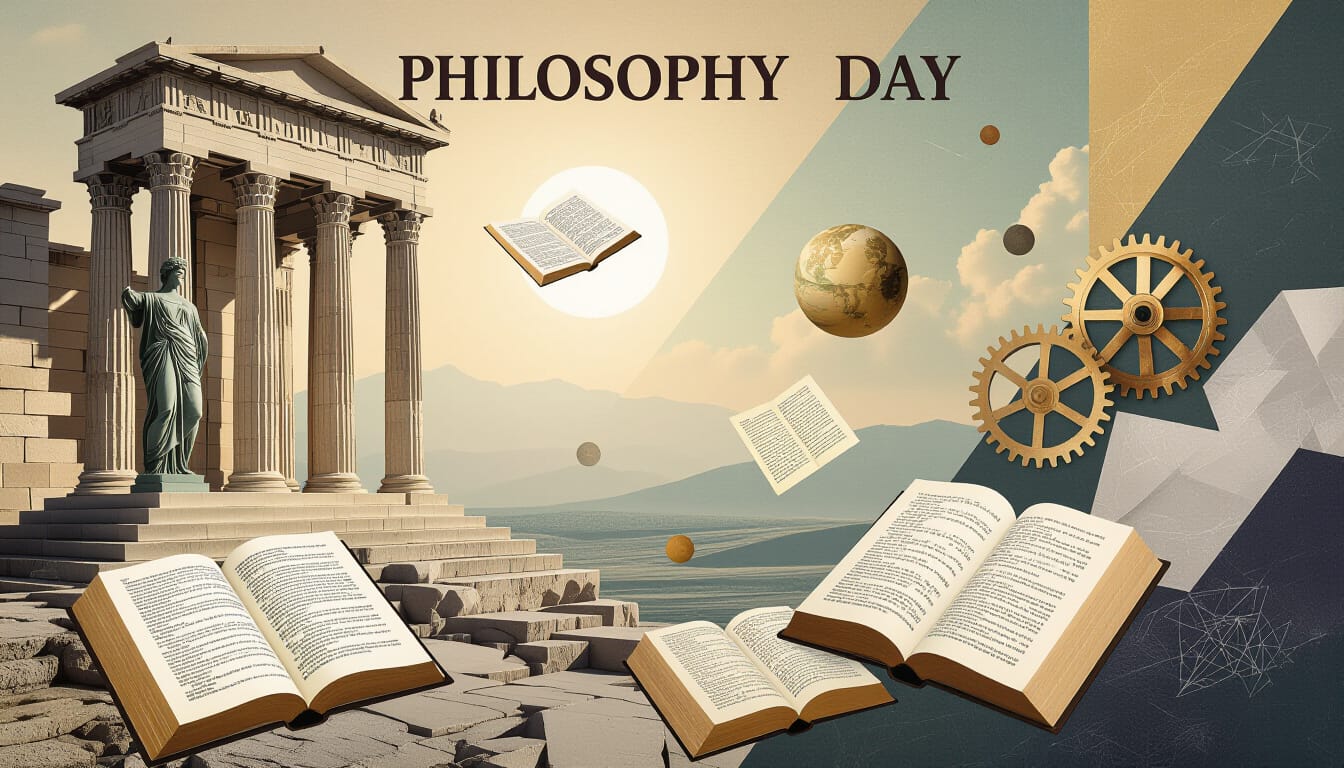
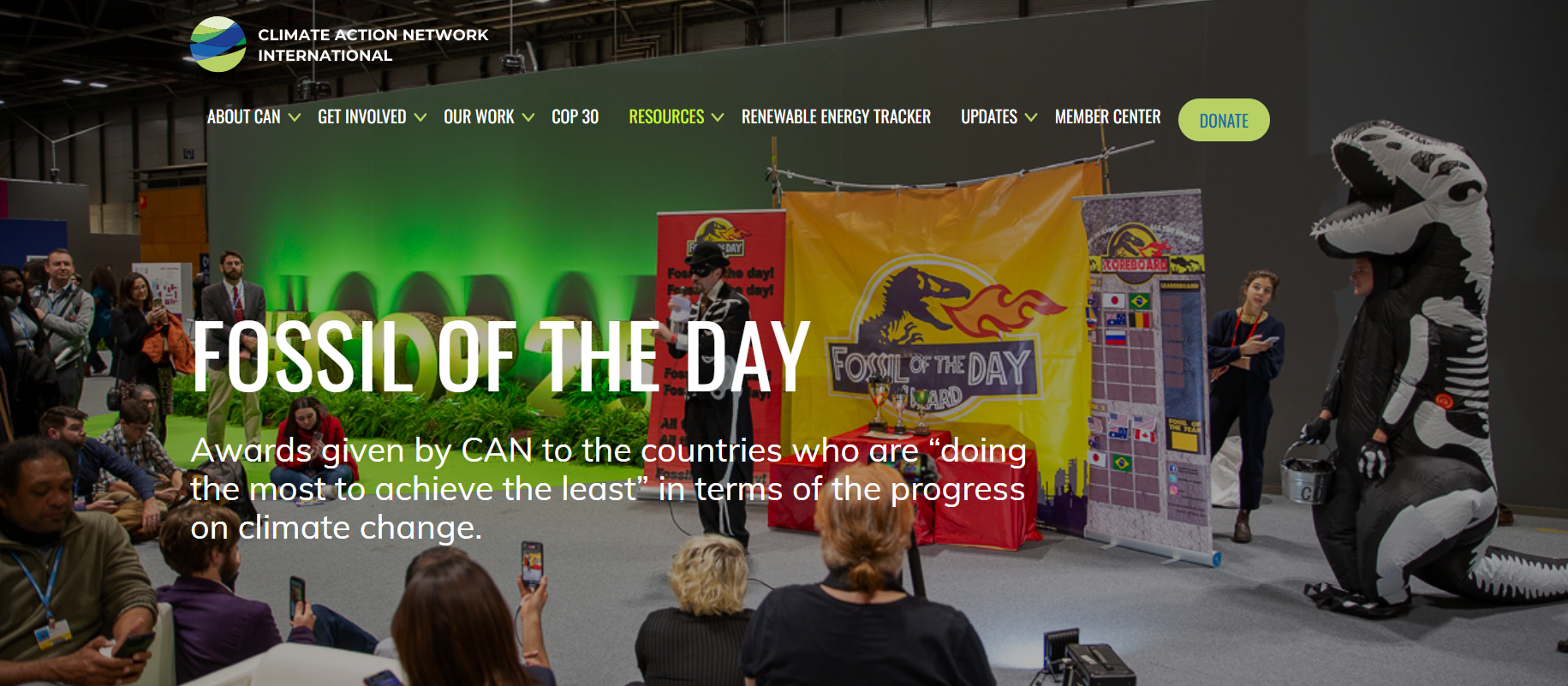

Post Comment