Sastra Kita: Sebuah Lelucon yang Sungguh Serius
Mungkin kita harus memulai dari sini: suatu pagi yang cerah, di tepi sungai Gangga, seorang brahmana tua batuk-batuk setelah menulis bait pertama sebuah kakawin. Atau barangkali di bawah pohon bodhi, seorang pengelana Jawa membolak-balik daun lontar, mengguratkan aksara dengan pisau kecil, berusaha menciptakan puisi untuk seorang putri raja yang tak pernah mencintainya. Siapa yang tahu pasti kapan dan di mana sastra Indonesia dimulai? Mungkin dimulai dari mereka yang ingin mencintai, atau sekadar ingin merasa lebih mulia, lebih pintar. Satu yang pasti: sastra Indonesia lahir dari kesepian yang ditulis, dari kalimat-kalimat yang mencoba mengisi ruang kosong dalam kepala dan hati yang berdebar.
Kemudian datanglah para pelaut dari Barat, dengan niat mencari rempah-rempah dan Tuhan, yang tak sabar menunggu tanah basah nusantara menyambut kaki mereka. Ketika mereka tiba, barangkali mereka heran menemukan bukan hanya lada dan cengkeh, tapi juga kisah-kisah yang berbelit seperti sulur merambat pada tembok. Di situlah sastra Indonesia bertemu dengan modernitas: ketika naskah-naskah lontar mulai terselip di antara kargo kapal-kapal dagang, ketika kisah-kisah dari negeri ini diterjemahkan dan diimpor kembali dengan rasa baru, lebih tajam, lebih eksotik. Maka lahirlah “hikayat” dan “babad,” memuat sejarah yang lebih banyak fiksinya ketimbang faktanya.
Namun, mungkin benar kata pepatah, bahwa semua perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil. Entah kenapa, langkah itu seringkali diiringi dengan pertanyaan, “Apakah ini benar-benar sastra?” Teks-teks berusia berabad-abad itu, yang diangkat dan digadang-gadang sebagai permulaan, hanyalah kata-kata yang tercampur aduk antara fakta dan mitos, antara sejarah dan fiksi. Dan itulah, barangkali, asal mula sastra Indonesia: perpaduan yang menawan antara keinginan untuk menulis dengan ketidakpastian apakah ada yang benar-benar peduli membaca. Sastra Indonesia adalah mimpi yang mulai ditulis bahkan sebelum ada pembaca untuk bermimpi bersama.
Antara Semangat dan Suramnya Takdir
Lalu, waktu pun berlalu, dan sastra Indonesia menemukan jalannya ke abad ke-20. Di masa itu, puisi berkembang dengan liar, seperti tanaman perdu yang tumbuh di celah-celah trotoar kota. Penyairnya ada di mana-mana: di kampus, di kantin, di warung kopi pinggir jalan. Mungkin ada yang menyangka ini adalah kebangkitan. Barangkali. Puisi Indonesia menjelma dari mantra-mantra menjadi sajak modern: penuh dengan luka yang dirayakan, mimpi yang dipuja-puja, dan kesedihan yang dibuat merdu. Penyairnya menyihir kata, menantang tirani, dan mengumpat lewat metafora. Mereka berteriak dengan pelan, membisik dengan lantang, dan entah bagaimana, mereka percaya dunia akan berubah dengan sebaris puisi. Sejauh itu, sastra Indonesia terlihat seperti seorang remaja yang penuh semangat, menulis di dinding sekolah, berharap guru sejarah tidak pernah membacanya.
Di samping puisi, cerita pendek atau cerpen mulai bermunculan seperti jamur setelah hujan. Para penulisnya menemukan keasyikan bermain-main dengan narasi singkat, menjelajahi ruang-ruang baru untuk bercerita tentang manusia, tanah air, cinta, bahkan tikus di balik lemari. Mereka menggali dari kehidupan sehari-hari, dari kemiskinan yang tak pernah usai, dari humor yang getir, dari absurditas yang tak tertandingi. Namun, tentu saja, ada batasan: cerpen harus singkat, ringkas, dan menggigit—seperti kue lebaran yang terlupakan di dalam kaleng. Mereka berkata bahwa cerpen harus dapat dibaca di dalam satu dudukan toilet umum; barangkali itu yang membuatnya begitu berkesan.
Novel, di sisi lain, menjadi medium yang lebih panjang untuk mengurai kompleksitas yang tak bisa diselesaikan dalam narasi pendek. Novel Indonesia, dengan segala keberaniannya, mulai menembus batas-batas tabu: menggugat sejarah, mengkritik pemerintah, bahkan mencoba merekonstruksi masa lalu yang tak pernah beres. Penulisnya ada yang melarikan diri ke luar negeri, ada yang berakhir di penjara, ada yang lenyap begitu saja di bawah tekanan rezim. Novel-novel ini mencoba melukiskan kebenaran yang tak pernah bisa diucapkan secara langsung, membawa pembacanya menyusuri lorong-lorong kelam kehidupan. Novel-novel ini sering kali tebal, rumit, penuh lapisan makna, mungkin karena mereka tahu, pembaca yang tersisa hanya segelintir. Maka, mengapa tidak menulis untuk mereka yang sedikit, namun setia?
Naskah teater pun tak mau ketinggalan, meski harus mencari tempatnya di ruang-ruang yang semakin sempit. Di masa-masa tertentu, teater menjadi lebih politis, menjadi sarana perlawanan yang lebih efektif daripada orasi. Panggungnya tidak lagi terbatas pada gedung megah dengan tirai merah, melainkan di pasar malam, di gang kumuh, atau di halaman kampus yang penuh debu. Teater Indonesia mencoba berbicara langsung kepada penonton yang mungkin lebih tertarik pada teriakan pedagang kaki lima. Mereka menampilkan ironi kehidupan dengan cara yang lebih harfiah: dialog-dialognya mencerminkan kebisingan kota, adegan-adegannya diiringi suara klakson dan jeritan. Naskah-naskah ini adalah monolog kehidupan yang ditulis dalam kondisi yang jauh dari nyaman, dan justru itu yang membuatnya begitu hidup.
Sebuah Drama Tanpa Penonton
Namun, setelah perjalanan panjang itu, kita tiba di era di mana sastra Indonesia menghadapi tantangan yang lebih pelik dan menggelikan. Para penulis kita kini tidak hanya dihadapkan pada masalah ide, inspirasi, atau kompetensi menulis, melainkan juga pada kenyataan pahit bahwa menulis sastra di negeri ini sering kali sama artinya dengan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa—secara harfiah. Media-media besar yang dulu menyediakan ruang bagi puisi, cerpen, dan esai, kini lebih tertarik pada berita selebriti, skandal politik, atau resep makanan viral. Mereka yang gigih menulis sastra sering kali tak dibayar; kata-kata mereka dianggap sebagai dekorasi belaka, bukan sebagai komoditas yang layak dihargai.
Lebih ironis lagi, banyak rubrik sastra yang mulai gulung tikar, baik di media cetak maupun digital. Sastrawan tak ubahnya tokoh utama dalam sebuah lakon komedi gelap; menulis dengan penuh semangat, hanya untuk mendapati panggung mereka lenyap di saat-saat terakhir. Rubrik sastra itu, yang dulu menjadi arena gladiator kata-kata, kini menjadi museum yang dikunjungi oleh segelintir orang dengan rasa kasihan. Ada yang berkata, “Ini zaman yang lebih realis, pragmatis,” seolah-olah menghibur diri. Sementara itu, redaktur sastra yang tersisa mungkin memutar-mutar bolpoinnya, berharap ada keajaiban yang akan membuat sastra kembali relevan di mata pengiklan.
Dan, masalahnya tak berhenti di situ. Kita bicara tentang pembaca, atau lebih tepatnya, ketiadaan mereka. Di era gawai dan gulir cepat ini, membaca sastra mungkin terasa seperti menonton film hitam putih di layar ponsel: lambat, membosankan, dan memerlukan perhatian lebih. Buku-buku sastra menumpuk di toko dengan label “diskon,” atau lebih sering lagi, berakhir menjadi hadiah doorprize pada acara-acara seminar yang peserta utamanya bahkan tak pernah menyentuh halaman pertama. Kita mendengar cerita tentang sastrawan yang memaksakan diri menjadi influencer, mencoba menyesuaikan diri dengan algoritma yang lebih menyukai gambar kucing ketimbang kata-kata mereka yang penuh renungan. Sastra Indonesia dihadapkan pada dilema eksistensial: apakah tetap setia pada dirinya sendiri atau bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih mudah dijual.
Di tengah semua ini, penulis muda yang berani bermimpi sering kali terpaksa menghadapi kenyataan bahwa karya mereka mungkin lebih sering dibaca oleh teman-teman dekat, yang terpaksa memberi “like” di media sosial. Komunitas sastra, yang dulunya menjadi pusat diskusi hangat dan kritis, kini lebih sering menjadi ajang pertemuan untuk saling menghibur. Ada yang tetap menulis dengan tekun, meyakini bahwa kata-kata mereka akan menemukan jalannya sendiri, meski entah kapan. Sementara yang lain memilih jalur pragmatis: bekerja di bidang yang lebih mapan, menulis di sela-sela waktu luang, berharap suatu hari kelak sastra akan kembali menemukan panggungnya yang layak.
Mungkin, pada akhirnya, sastra Indonesia adalah drama yang tak pernah selesai. Ia adalah kisah tentang mereka yang menulis di tengah kegelapan, percaya bahwa ada yang mendengar meski tak ada yang menjawab. Ia adalah monolog panjang yang diucapkan di depan panggung kosong, sambil berharap ada yang masuk dan mengambil tempat duduk, meski hanya untuk satu adegan. Barangkali, sastra kita memang sedang mencari bentuk baru, atau mungkin saja, ia sedang menunggu seseorang yang cukup gila untuk percaya bahwa menulis tetaplah penting, meski tak ada yang peduli.
Sastra Era 4.0
Dan di ujung segala keresahan ini, datanglah era yang disebut Sastra 4.0, ketika segalanya menjadi lebih digital, lebih cepat, dan, tentu saja, lebih kabur. Ada yang bermimpi bahwa sastra akan menemukan ruang baru di dunia blockchain, menjadi NFT yang tak terhapuskan, tak terbantahkan, dan abadi di atas rantai-rantai kode yang tak bisa diretas. Namun, kenyataannya, puisi yang dijual sebagai NFT hanya berakhir seperti lukisan Mona Lisa palsu di pasar gelap internet: dipuja oleh beberapa kolektor misterius, tetapi lebih sering diabaikan oleh para spekulan yang lebih tertarik pada gambar kucing yang beruntung. Sastra sebagai NFT tampak seperti lelucon kosmik, sebuah karya seni yang diciptakan tanpa penonton, hanya untuk dihargai oleh algoritma.
Di sisi lain, ada yang mencoba membawa sastra ke layar YouTube, mengubah naskah drama menjadi vlog, dan membaca cerpen dengan latar musik lo-fi. Hasilnya? Beberapa ratus penonton yang tersesat dari saluran mukbang atau tutorial make-up, lalu cepat-cepat mengklik tombol “kembali.” Sastra di dunia digital menjadi sesuatu yang memohon perhatian, seperti badut di pesta ulang tahun yang sunyi. Teks-teks yang dirancang untuk memprovokasi pemikiran panjang kini dihadapkan pada detik-detik singkat yang menuntut kepuasan instan. Barangkali ini semua hanya eksperimen, atau mungkin sekadar upaya terakhir untuk menegaskan eksistensi di tengah lautan konten yang tak bertepi.
Di media sosial, sastra tampak menemukan kehidupan baru—atau setidaknya demikianlah yang terlihat di permukaan. Kutipan-kutipan penuh gairah dan kegalauan tersebar luas di Instagram, Twitter, dan TikTok, dicampur dengan foto-foto kopi dan matahari terbenam. Para pembuat konten berlomba-lomba menciptakan “momen sastra” yang bisa diunggah dan dibagikan, meski sering kali hanya untuk mengumpulkan tanda suka. Di situ, sastra menjadi sebatas potongan kalimat yang kehilangan konteks, disederhanakan hingga tersisa inti paling ringan, siap untuk dijadikan status atau caption. Kata-kata besar menjadi kecil, dan mungkin, di situ kita melihat paradoks terbesarnya: sastra dirayakan tetapi tidak dibaca, dikutip tetapi tidak direnungkan.
Sastra 4.0 juga menghadirkan mimpi lain yang sama getirnya: menulis untuk algoritma. Para penulis kini harus mempertimbangkan tagar apa yang sedang tren, kapan waktu terbaik untuk memposting, dan bagaimana menyesuaikan gaya penulisan agar ramah mesin pencari. Sastra di era ini terancam menjadi serangkaian trik optimasi, di mana keindahan harus dikompromikan untuk mendapatkan tempat di halaman pertama Google. Penulis harus menjadi pemasar, editor harus menjadi manajer media sosial, dan pembaca berubah menjadi metrik yang harus dikejar. Ironisnya, semakin keras mereka mencoba menyesuaikan diri, semakin hilang jati diri sastra yang dulu penuh kebebasan dan keberanian.
Dan begitulah, di zaman serba digital ini, sastra menemukan dirinya di tepi jurang yang tak terbayangkan. Ia bisa menjadi segala sesuatu—tetapi juga bisa menjadi bukan apa-apa. Ada yang tetap percaya bahwa sastra adalah jalan sunyi yang harus ditempuh, ada pula yang merasa itu semua hanyalah peninggalan masa lalu yang sudah waktunya dibuang. Barangkali, satu-satunya kepastian yang kita miliki adalah bahwa sastra akan terus berubah, seperti aliran sungai yang mencari muaranya sendiri, tanpa pernah tahu apakah muara itu ada. Dan kita, para penulis, pembaca, dan penonton, hanya bisa mengikuti aliran itu, sambil tersenyum getir di tengah ironi zaman yang tak pernah kekurangan lelucon.
Sastra Zaman Now
Sastra bilang, “Aku ada di TikTok,
Berdansa dengan algoritma, joget sama trending sound.”
Tapi ya siapa mau nonton,
Kalau nggak ada drama percintaan atau prank nge-prank.
Puisi jadi quotes di Instagram Story,
Disandingkan sama latte art sama foto kaki di pantai.
Sajak-sajak berbalapan jadi caption estetik,
Biar kelihatan mendalam, tapi aduhai jijiiiik.
Cerpen? Cerpen itu apa sih?
Ada yang ingat? Kayaknya sudah hilang,
Terkubur di thread curhat Twitter,
Yang lebih seru dan dapat lebih banyak “like.”
Naskah teater? Coba, deh, tayang di YouTube,
Tapi views-nya kalah sama ASMR mie instan dimakan pelan-pelan.
Sastra berusaha viral, tapi apa daya,
Kalah pamor sama kucing lucu main tiktok di reels tetangga.
Maka mari kita berdoa, teman-teman,
Semoga suatu hari nanti, sastra trending—
Bukan karena drama skandal atau clickbait murahan,
Tapi karena kita lupa log out dan semua like-nya otomatis.
Singajaya, 4 September 2030
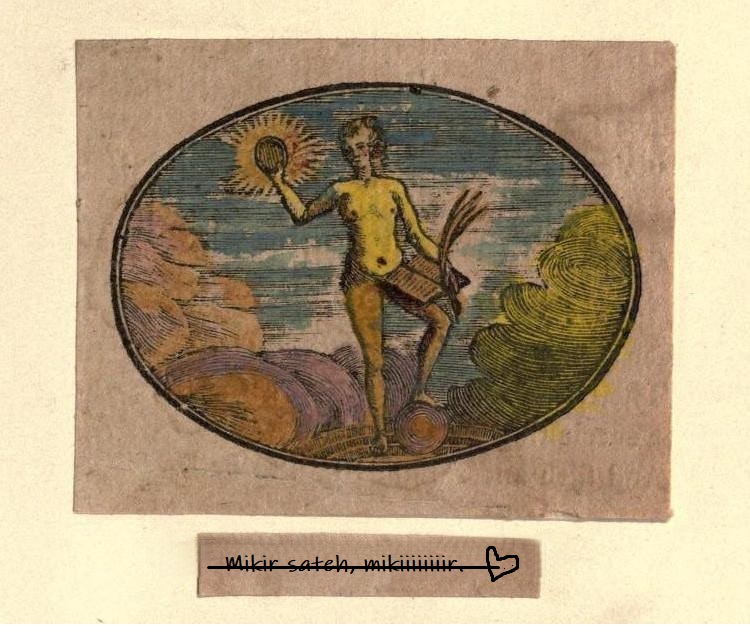



Post Comment