Pendidikan: Fucking Kapitalis!
Pendidikan, pada mulanya, adalah urusan waktu luang. Orang-orang kuno, yang bosan menatap ladang jagung tumbuh perlahan, menciptakan pendidikan sebagai cara agar hari terasa lebih pendek. Kalau pagi diisi dengan menanam dan sore untuk memanen, maka sisa waktu di antaranya dihabiskan untuk mengajari anak-anak membaca huruf-huruf yang bahkan burung pun tak peduli. Pendidikan adalah seni mengusir kejenuhan tanpa memecahkan tempayan air.
Guru, pada masa itu, adalah siapa saja yang merasa dirinya lebih tahu—seorang tetua, saudagar keliling, atau sekadar orang yang pernah pergi ke pasar besar di kota seberang. Mereka mengajarkan apa saja yang muncul di kepala: menghitung jumlah kerbau tetangga, membedakan daun yang layak dimakan, atau sekadar mengarang kisah tentang raksasa di hutan. Tidak ada yang meminta bayaran, karena siapa yang mau membayar untuk sesuatu yang tidak bisa dijual?
Anak-anak yang datang ke “kelas” adalah mereka yang kebetulan sedang tidak sibuk memanjat pohon atau mengejar layangan. Ruang belajarnya bisa di mana saja: di bawah pohon beringin, di gubuk pinggir sawah, atau di tepi sungai sambil menunggu ikan menggigit umpan. Kalau ada yang malas datang, tak ada konsekuensi. Pendidikan bukan kewajiban; ia hanya hiburan, setara dengan pertandingan gasing atau menyimak dongeng sebelum tidur.
Namun, di balik kesederhanaan itu, ada keikhlasan. Orang-orang belajar bukan untuk ijazah atau gelar, tetapi karena penasaran. Mereka membaca bukan untuk mengejar angka, melainkan untuk memahami apa yang tertulis di papan pasar atau surat dari kerabat jauh. Pendidikan tidak mengubah hidup seseorang; ia hanya memperkaya hari-hari yang sudah berjalan lambat. Hidup bermakna dengan kaya raya dengan pemahaman.
Demikian pendidikan sebelum era kapitalisme, era tanpa uang, tanpa perbankan. Pendidikan yang santai, ikhlas, tidak menjanjikan apa-apa selain penghayatan terhadap makna hidup. Tidak ada keuntungan, tidak ada angka, tidak ada pasar. Maka datanglah waktu ketika pendidikan mulai dibungkus dengan aturan, nilai, dan—tentu saja—harga.
Wajar—Wajib Belajar
Di suatu titik dalam sejarah, seseorang dengan gagasan besar—atau mungkin kantong kosong—mendeklarasikan bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa, tapi dengan sedikit penyesuaian: hak itu harus diwajibkan. Anak-anak yang tadinya bebas memilih antara belajar huruf atau berburu belalang kini harus duduk di bangku kayu keras, menatap papan tulis yang penuh coretan angka. “Belajar itu penting,” kata mereka, sambil mengeluarkan aturan bahwa setiap anak harus masuk sekolah, atau keluarganya akan dicap tidak beradab.
Maka dimulailah pergeseran besar. Pendidikan, yang dulunya cuma hiburan, kini menjadi pekerjaan penuh waktu. Para guru yang tadinya dibayar dengan sepotong ubi mulai menuntut sesuatu yang lebih konkret—beras, kain, atau akhirnya, uang. Untuk pertama kalinya, pendidikan mulai dihargai, meskipun dengan catatan kecil: harga itu ditentukan oleh mereka yang mengelola sekolah, bukan mereka yang belajar.
Kurikulum diperkenalkan sebagai bukti keseriusan. Anak-anak tidak lagi belajar sesuai kebutuhan hidup, melainkan sesuai kebutuhan kebijakan. Semua harus tahu kapan perang Diponegoro dimulai, meskipun yang mereka inginkan hanyalah cara menanam padi lebih cepat. Semua harus memahami rumus phytagoras, meskipun segitiga tidak pernah relevan di ladang jagung.
Dan dengan kewajiban itu datanglah biayanya. Sekolah yang dulunya gratis mendadak punya daftar pungutan: untuk seragam, buku, alat tulis, bahkan kursi untuk diduduki. “Pendidikan harus dihargai,” kata mereka, tapi yang dimaksud ternyata bukan nilai moral, melainkan nilai nominal. Orang tua yang dulu hanya sibuk menyiapkan bekal kini juga harus memikirkan bagaimana membayar uang pembangunan, uang ekstrakurikuler, dan—yang paling absurd—uang kebersihan, padahal anak-anak mereka yang menyapu kelas setiap pagi.
Semua ini, tentu saja, dikemas dengan narasi indah. “Pendidikan akan membuka pintu masa depan,” kata mereka, meskipun tidak menjelaskan bahwa pintu itu kadang mengarah ke jurang hutang. Anak-anak belajar, orang tua membayar, dan sistem mulai bekerja seperti mesin. Pendidikan, yang dulunya hak, kini menjadi investasi. Dan seperti semua investasi, ada yang untung besar, tapi ada juga yang bangkrut sebelum sempat melihat hasilnya.
Investasi Kecemasan
Ketika kewajiban sudah diterima sebagai norma, tahap berikutnya adalah penyempurnaan model bisnisnya. Pendidikan yang tadinya berbayar seperlunya kini menjadi komoditas premium. Sekolah-sekolah biasa mulai merasa rendah diri; mereka melirik sekolah-sekolah “unggulan” yang memasang harga setara sebuah sepeda motor dan berusaha menyaingi. Para pengelola bersepakat bahwa pendidikan harus memiliki nilai tambah: gedung bertingkat, seragam yang dijahit khusus, dan fasilitas seperti kolam renang yang lebih sering kosong daripada terisi.
“Investasi untuk masa depan,” itulah mantra baru yang dijual kepada orang tua. Dalam rapat sekolah, kepala sekolah berdiri di podium dan berbicara tentang pentingnya komputer di setiap meja, sementara para orang tua saling berpandangan, menghitung berapa kilo beras yang harus dijual untuk menutup biaya tambahan itu.
Dan bukan hanya sekolah; kampus-kampus pun ikut berlomba menaikkan standar harga. Biaya masuk melonjak, diiringi daftar panjang kebutuhan: laboratorium canggih, perpustakaan digital, hingga gedung olahraga yang lebih mirip pusat kebugaran bintang lima. Jurusan-jurusan tertentu seperti kedokteran atau teknik bahkan memasang angka yang bisa membuat petani tiga generasi gemetar hanya dengan mendengar totalnya.
Semua ini dibenarkan dengan alasan sederhana: kualitas ada harganya. Tidak ada yang bertanya apakah pendidikan yang mahal benar-benar berkualitas, atau hanya sekadar ilusi dari marmer mengkilap dan brosur warna-warni. Yang jelas, biaya yang tinggi tidak hanya menjadi simbol gengsi, tetapi juga alat seleksi. Pendidikan, yang katanya untuk semua, mulai menutup pintunya bagi mereka yang kantongnya terlalu tipis.
Akibatnya, pendidikan menjadi ajang kompetisi bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi orang tua. Mereka berlomba mencari uang untuk membayar sekolah terbaik, sementara anak-anak mereka dipaksa berlomba mendapatkan nilai terbaik. Di tengah semua itu, pertanyaan mendasar tentang apa yang sebenarnya dipelajari sering kali terlupakan. Yang penting adalah lulus, mendapatkan ijazah, dan entah bagaimana, membayar semua itu sebelum surat penagihan datang lagi bulan depan.
Di sini, pendidikan tidak lagi sekadar mahal; ia menjadi alat pemisah. Siapa yang mampu membayar melanjutkan, siapa yang tidak hanya bisa berharap. Tapi tunggu dulu—ini belum selesai.
Fucking Kapitalisme
Ketika pendidikan semakin mahal dan semakin wajib, sistem menemukan solusi baru yang brilian: utang. “Jangan khawatir soal biaya,” kata mereka dengan senyum yang seolah penuh empati. “Kita bisa bantu membiayai masa depan Anda. Pendidikan adalah investasi, dan investasi butuh modal.” Maka, lahirlah era baru di mana sekolah dan kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi perlahan-lahan berubah menjadi lembaga keuangan.
Pinjaman pendidikan mulai diperkenalkan sebagai tiket menuju mimpi. Mahasiswa yang keluarganya sudah kehabisan tabungan ditawari formulir dengan janji muluk: belajar dulu, bayar nanti. Kampus-kampus berlomba menawarkan skema cicilan, lengkap dengan bunga yang bersaing, seolah-olah mereka adalah bank. Bahkan, beberapa institusi memasang spanduk besar yang menampilkan siswa tersenyum di samping slogan, “Pinjam Sekarang, Sukses Kemudian.”
Awalnya, utang pendidikan tampak seperti penyelamat. Orang tua merasa lega; anak-anak mereka akhirnya bisa masuk sekolah favorit atau universitas ternama tanpa harus menjual tanah warisan. Mahasiswa pun merasa optimis, berpikir bahwa mereka akan melunasi semuanya begitu mendapatkan pekerjaan. Tapi tidak ada yang memberitahu mereka bahwa utang itu tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga bayangan yang akan mengikuti mereka ke mana pun mereka pergi.
Setelah lulus, realitas menampar lebih keras daripada ujian akhir. Banyak lulusan mendapati bahwa gaji pertama mereka, bahkan mungkin gaji tahun pertama mereka, tidak cukup untuk menutup cicilan. Mereka bekerja keras, tetapi utang pendidikan tetap menggunung, berlipat ganda oleh bunga yang terus berjalan tanpa jeda. Sementara itu, institusi pendidikan dengan senang hati melanjutkan praktik ini, menawarkan lebih banyak pinjaman kepada generasi berikutnya, memastikan siklus ini terus berjalan.
Dan di sinilah pendidikan mencapai puncak ironi: ia tidak lagi menjadi alat pembebasan, melainkan jebakan. Siswa yang bermimpi mengubah nasib mereka malah terjebak dalam lingkaran hutang yang tak ada habisnya. Orang tua yang berharap memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan surat penagihan yang tak kunjung selesai.
Kini, pendidikan tidak lagi bisa dihindari. Ia adalah kewajiban, ia adalah investasi, dan ia adalah utang. Anak-anak masuk sekolah dengan semangat, tapi keluar dengan beban yang mereka bawa seumur hidup. Dalam sebuah dunia di mana gelar lebih penting dari keterampilan, pendidikan tidak lagi menjanjikan kebebasan. Ia adalah bisnis, dan semua orang yang terlibat, tanpa sadar, telah menjadi pelanggannya.
Sistem tanpa Alternatif
Kita sering membayangkan ada jalan lain, sebuah alternatif dari pendidikan yang telah dikomersialkan: belajar secara otodidak, menemukan keterampilan tanpa perlu sekolah, atau menjadi pengusaha tanpa gelar. Namun, kenyataannya, pendidikan kapitalis telah merasuki setiap sudut kehidupan. Sistem ini begitu mendalam dan meluas sehingga bahkan mereka yang mencoba keluar darinya tetap dipaksa tunduk pada kerangka yang sama.
Lihatlah orang-orang yang dilabeli “sukses.” Kebanyakan dari mereka adalah lulusan sekolah atau universitas, dan itu bukan kebetulan. Sekolah bukan hanya tempat belajar; ia adalah alat legitimasi. Tanpa ijazah, seorang jenius tetaplah dianggap sekadar nekat, sementara seseorang yang hanya menguasai teori tetapi memiliki gelar akan disambut dengan tepuk tangan. Pendidikan kapitalis bukan hanya soal ilmu; ia soal pengakuan, dan dalam sistem ini, pengakuan hanya diberikan kepada mereka yang membayar harganya.
Bahkan bagi mereka yang mendobrak norma dan mencapai keberhasilan tanpa sekolah formal, label “tanpa pendidikan” tetap menjadi stigma. Para pendiri startup yang drop-out dari universitas ternama tidak dirayakan karena keberanian mereka meninggalkan kampus, tetapi karena sebelumnya mereka adalah bagian dari institusi bergengsi itu. Merekalah pengecualian yang justru memperkuat aturan: hanya yang sangat cerdas atau sangat beruntung yang bisa keluar dari jalur pendidikan kapitalis dan tetap menang.
Dan sistem ini bekerja seperti lingkaran yang tak terputus. Perusahaan besar, yang mendominasi dunia kerja, mensyaratkan gelar bahkan untuk posisi paling dasar. Orang tua, yang khawatir anak-anak mereka tak punya masa depan, merasa tak punya pilihan selain memaksakan pendidikan formal, tak peduli berapa pun biayanya. Generasi muda pun tumbuh dengan keyakinan bahwa tanpa ijazah, mereka bukan siapa-siapa, sementara sistem pendidikan terus menaikkan harga dengan alasan “kualitas.”
Pendidikan kapitalis telah berhasil menjadikan dirinya kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa mahal biayanya, seberapa besar utangnya, atau seberapa minim relevansi kurikulumnya, orang-orang tetap berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena sistem ini tidak memberi mereka pilihan lain.
Inilah ironi terbesar: pendidikan, yang seharusnya membebaskan, malah menjadi penjara tak kasat mata. Semua orang masuk ke dalamnya dengan harapan besar, hanya untuk mendapati bahwa mereka telah menjadi bagian dari mesin yang terus-menerus melestarikan dirinya sendiri. Pendidikan kapitalis telah menjadi keharusan, bukan karena ia terbaik, tetapi karena ia satu-satunya jalan yang tersisa.
God Father
Marilah kita tutup diskusi ini dengan mengingat film yang menjelaskan kehidupan elit di puncak-pucuk kapitalisme Amerika, ia adalah Mafia. Ia yang sadar bahwa selamanya ia tak bisa keluar dari sistem yang ia sadari memang biadab. Ia sebetulnya “orang baik”, bertahan hidup mulai merangkak dari kelas bawah. Begitu berada di lingkaran puncak, ia tak bisa dikalahkan. Kalah berarti tersingkir, kehilangan makna, atau mati. Maka, tokoh utamanya—atau bicara lewat pengacaranya—berulang-ulang mengatakan dengan santun dan normatif pada lawan bicaranya, atau pada penonton, atau pada kita semua: “Saya ingin menyampaikan tawaran yang tak bisa ditolak.”
Desember, 2024


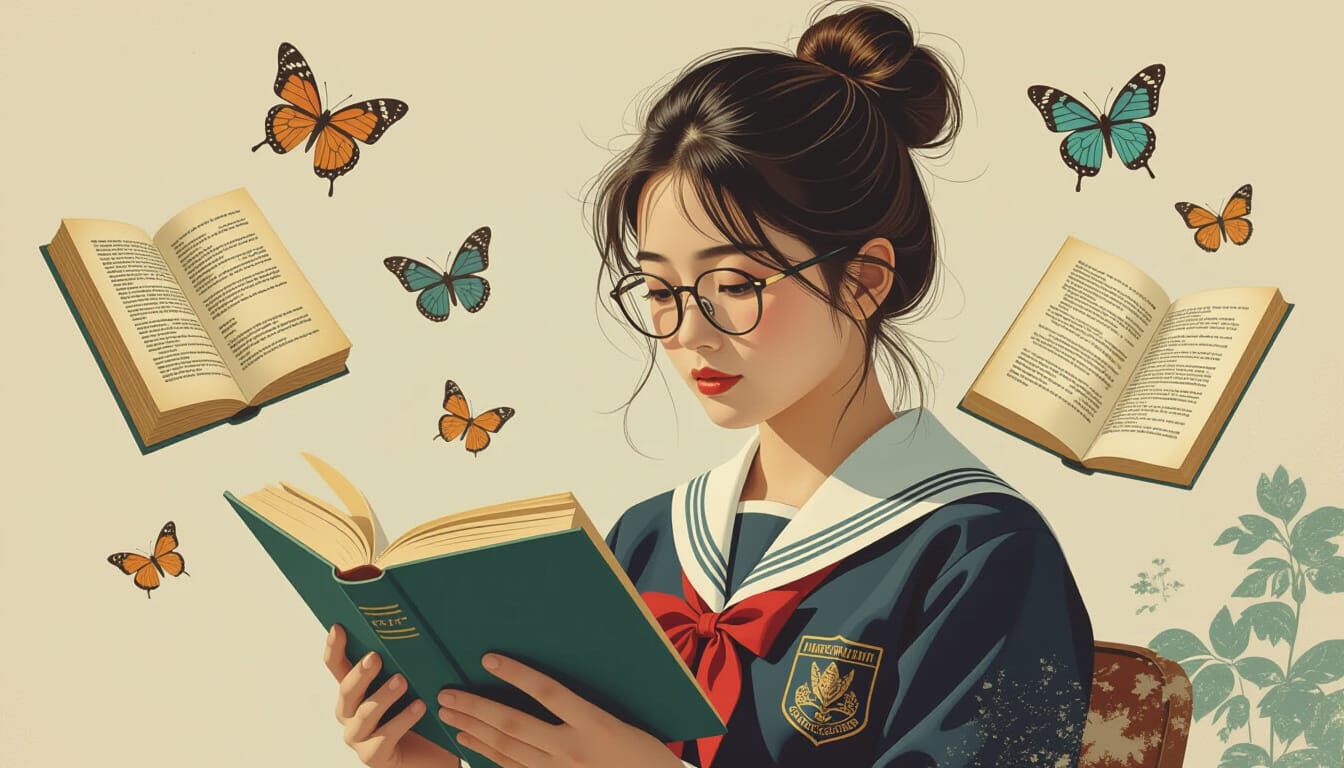

Post Comment