Buku Promblematik itu Bergenre Motivasi
Di dunia yang dipenuhi suara motivasi seperti iklan detergen, buku-buku motivasi tumbuh subur seperti rumput liar di pekarangan yang malas dipotong. Setiap halaman mereka menawarkan solusi instan, mirip bumbu mie instan yang menjanjikan rasa ayam bawang dalam dua menit. Pembaca pun tergoda, percaya bahwa buku-buku ini adalah tiket VIP menuju kesuksesan.
Tapi mari kita bicara jujur: apakah hidup benar-benar semudah membaca satu bab tentang “percaya pada diri sendiri”? Penelitian oleh Joanne V. Wood dan rekannya dalam artikel berjudul “Positive Self-Statements: Power for Some, Peril for Others” (Journal of Psychological Science, 2009) mengungkapkan bahwa afirmasi positif sering kali tidak efektif bagi orang dengan harga diri rendah. Bahkan, kata-kata seperti “saya bisa melakukannya” malah memicu stres dan kecemasan, karena individu merasa tidak mampu memenuhi harapan tersebut.
Isi buku motivasi biasanya bisa dirangkum dalam tiga langkah generik: bangun pagi, minum kopi, dan jangan malas. Penulisnya terdengar seperti orang tua galak yang cuma tahu marah tanpa benar-benar paham kompleksitas masalah hidup. Tapi entah kenapa, banyak orang rela membayar mahal untuk mendengar ceramah versi cetak ini.
Dalam dunia motivasi, kegagalan itu dianggap seperti remah-remah di atas meja makan: sesuatu yang harus segera dibereskan. Tidak ada ruang untuk menerima bahwa terkadang, kegagalan adalah tanda bahwa kita sedang mencoba hal yang salah. Sebaliknya, buku motivasi membuat kita merasa gagal karena “kurang usaha” atau “kurang percaya pada proses.” Penelitian Carol Dweck tentang mindset dalam bukunya “Mindset: The New Psychology of Success” (2006) menunjukkan bahwa cara seseorang memahami kegagalan jauh lebih kompleks. Dweck menekankan pentingnya konteks dan proses belajar daripada sekadar “usaha keras.”
Satu hal yang paling menarik adalah analogi yang digunakan dalam buku-buku ini. Hidup sering diibaratkan sebagai perjalanan mendaki gunung, padahal bagi sebagian besar orang, hidup lebih mirip jalan di tengah hujan deras sambil membawa payung bocor. Sayangnya, buku motivasi tidak pernah membahas apa yang harus dilakukan jika payungmu bocor. Sebuah artikel oleh Tomas Chamorro-Premuzic berjudul “The Talent Delusion” (Harvard Business Review, 2017) menyebutkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua dalam motivasi sering kali gagal karena mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis individu.
Buku-buku ini juga penuh dengan kisah sukses selebriti atau pengusaha yang “memulai dari nol.” Mereka lupa memberi tahu bahwa nol mereka biasanya adalah nol dengan latar belakang keluarga kaya dan akses pendidikan terbaik. Membaca buku motivasi kadang seperti menonton pameran lukisan tanpa menyadari bahwa semua karya di sana dibuat dengan cat mahal. Dalam laporan Pew Research Center bertajuk “Social Mobility in America” (2020), disebutkan bahwa akses terhadap pendidikan dan dukungan finansial adalah faktor utama kesuksesan, jauh lebih signifikan daripada motivasi internal semata.
Yang lucu adalah, buku motivasi sering kali tidak mengubah banyak dalam kehidupan pembacanya, kecuali membuat mereka jadi rajin mengunggah kata-kata bijak di media sosial. Timeline kita pun penuh dengan kutipan seperti “Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri,” padahal kehidupan unggahannya masih sama kusutnya seperti kemarin. Sebuah studi oleh Sheldon et al., “Media Use and Self-Objectification” (Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2011), menemukan bahwa perilaku semacam ini sering kali lebih berfungsi untuk pencitraan sosial daripada perubahan nyata dalam kehidupan pribadi.
Ironi terbesar dari buku motivasi adalah bahwa mereka dijual sebagai solusi, tetapi sering kali malah menciptakan masalah baru. Alih-alih membantu pembaca menerima kenyataan, mereka menanamkan ketakutan bahwa siapa pun yang tidak “berprogres” berarti gagal dalam hidup. Sebuah studi oleh Barbara Fredrickson berjudul “The Role of Positive Emotions in Positive Psychology” (American Psychologist, 2001), menunjukkan bahwa standar tidak realistis dapat membuat individu merasa lebih buruk dan mengurangi ketahanan mereka terhadap stres.
Jika buku-buku ini adalah makanan, maka mereka adalah junk food. Rasanya enak, tapi kandungan gizinya nol. Mereka mengenyangkan untuk sementara, namun meninggalkan rasa lapar yang lebih besar setelahnya. Para pembaca, seperti anak kecil di toko permen, terus kembali untuk mencari lebih banyak, tanpa menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan.
Akhirnya, kita harus bertanya: siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh buku-buku motivasi ini? Tentu saja, penulis dan penerbit yang menghitung uang dari penjualan setiap edisi ulang. Sementara itu, pembaca tetap terjebak di tempat yang sama, hanya dengan koleksi kutipan inspiratif di kepala mereka.
Jadi, mungkin sudah saatnya kita berhenti berharap pada mantra ajaib dari buku motivasi dan mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak bisa diringkas dalam tiga langkah sederhana. Sebab, dalam dunia yang kompleks ini, solusi instan hanyalah mitos manis yang dijual dengan harga mahal.
Deri Hudaya. Tulisan-tulisannya terdokumentasikan di HumaNiniNora.
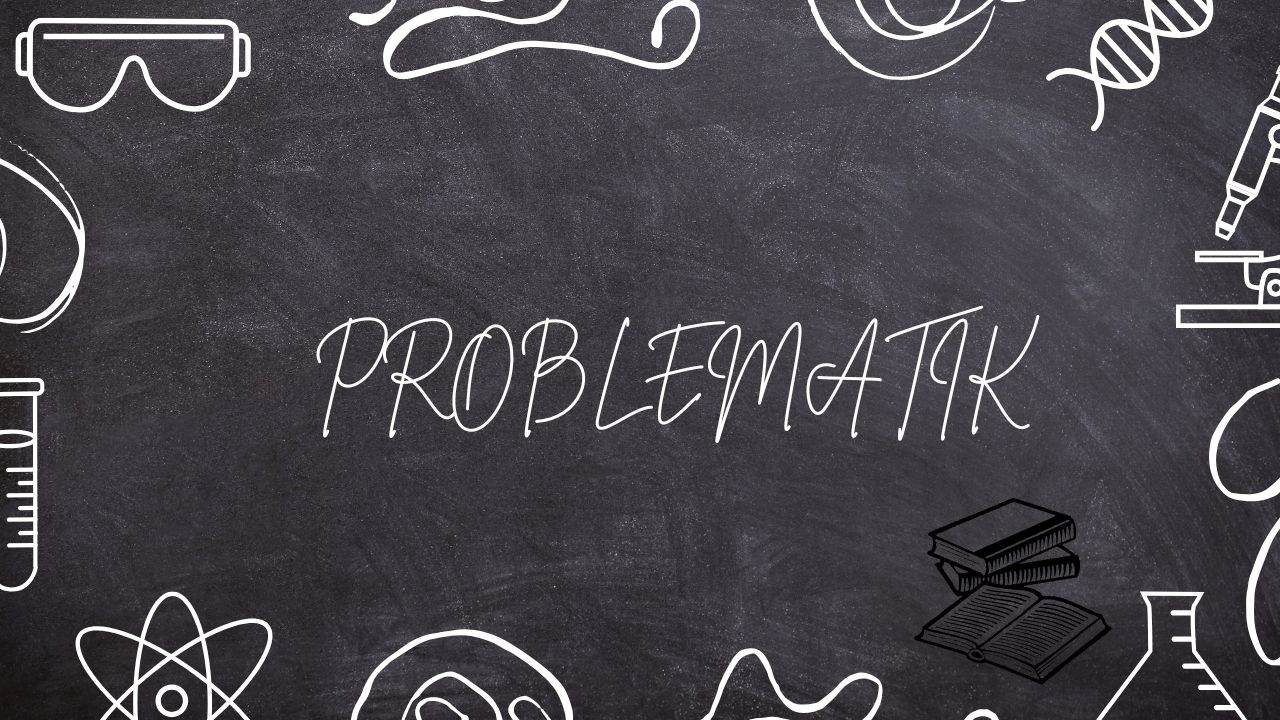


Post Comment