“Bapak Aing” dan Mitologi dari Tanah Konten
—sebuah pembacaan barthesian terhadap politisi yang memeluk kerbau sambil tersenyum ke kamera
Di negeri yang kehilangan bapak, siapa pun bisa jadi ayah. Terutama jika ia datang dengan logat lokal, senyum manis, dan tangan yang hangat untuk nenek-nenek renta yang telah lama diceraikan negara. Maka hadirlah Dedi Mulyadi, bukan sekadar gubernur, tetapi tokoh pewayangan modern dari jagat YouTube dan TikTok. Ia berjalan menyusuri pasar dan kandang kambing, membawa bukan program kerja, melainkan kasih sayang dalam format konten. Seolah kekuasaan bukan struktur, melainkan pelukan; seolah negara bisa ditebus dengan empati dan kamera yang fokus pada air mata.
Roland Barthes, andai lahir di Purwakarta dan main TikTok, pasti akan mengernyit dan berkata: ini mitos yang terlalu rapi. Sebab Dedi bukan sekadar manusia, ia adalah tanda. Sebagaimana dalam Mythologies, Barthes menjelaskan bahwa mitos adalah sistem komunikasi kedua yang bekerja diam-diam: menyamarkan ideologi sebagai kodrat, natural, alami, tidak perlu dipertanyakan. Ketika Dedi menggendong nenek dan berkata, “Saha nu nyeri hate?”, ia tidak hanya sedang berbicara—ia sedang menciptakan dunianya. Sebuah dunia di mana politisi adalah sahabat rakyat, budaya adalah konten, dan kasih sayang bisa direkam dalam format vertikal.
Dalam semiotika Barthes, tiap adegan Dedi adalah teks yang harus dibaca dua kali: pertama sebagai realitas (denotasi), lalu sebagai makna kultural (konotasi). Seekor kerbau dipegang dengan lembut, seorang pemulung diajak ngobrol, dan sepiring nasi dibagi—semuanya menandakan cinta. Tapi dalam lapisan kedua, kita melihat konstruksi: Dedi adalah simbol dari kekuasaan yang dibungkus sebagai kedekatan. Ia tidak memerintah, ia menemani. Tidak memaksa, tapi menyentuh. Tapi bukankah itu justru cara kekuasaan bekerja hari ini? Bukan dengan rotan, tapi dengan algoritma.
Yang lebih licin adalah bagaimana budaya lokal disulap menjadi panggung narasi. Dalam tangan Dedi, Sunda bukan sekadar warisan, tapi properti visual. Bahasa, pakaian, dan ritual menjadi aksesoris identitas yang dijual kepada audiens digital. Seperti Barthes membaca citra negro di milo box atau wrestlers Prancis dalam arena, kita bisa membaca Dedi sebagai tokoh adat yang dimodernkan—karuhun yang punya drone. Tradisi bukan lagi bentuk perlawanan terhadap modernitas, tapi justru bahan bakar bagi mesin kapitalisme representasi.
Dan dalam narasi ini, rakyat kecil bukan subjek. Mereka adalah properti moral. Nenek yang renta, anak yang kurus, atau pedagang yang lesu, semuanya menjadi penanda kesalehan Dedi. Mereka bukan lagi warga negara, tapi tokoh figuran dalam sinetron kekuasaan—panggung tempat Dedi membuktikan bahwa ia adalah Bapak Aing, ayah universal yang selalu hadir, bahkan saat negara tidur siang.
Di sinilah kerja mitos mencapai puncaknya. Dedi tidak sedang berpura-pura; justru karena itulah ia berfungsi. Mitos, kata Barthes, bukan kebohongan, tapi distorsi—sebuah operasi sunyi yang menjadikan konstruksi tampak alamiah. Dan dalam narasi “Bapak Aing”, kekuasaan tidak muncul sebagai instrumen dominasi, melainkan kasih yang hangat dan menghibur. Ia bukan aparat, tapi pelindung. Bukan struktur, tapi cerita. Ia adalah mimpi rakyat yang bosan dengan debat capres dan lapar akan figur yang bisa ngevlog sambil nyiram sawah.
Tentu kita bisa bertanya: apa salahnya? Bukankah lebih baik punya politisi yang menyapa, ketimbang yang korup? Tapi itu pertanyaan yang sudah dijebak mitos. Sebab di balik senyum Dedi ada mesin yang sangat efektif: mesin empati yang bekerja seperti iklan sabun—mengharukan, estetis, dan tanpa solusi struktural. Politik menjadi performa, dan performa menjadi pengganti kebijakan.
Maka Dedi Mulyadi bukan hanya seorang tokoh. Ia adalah refleksi dari zaman yang menggantikan kepercayaan dengan konten, dan mengubah rakyat menjadi penonton yang scroll tak henti, bukan karena harapan, tapi karena hiburan. Dalam dunia tanpa utusan Tuhan dan wakil rakyat yang bisa dipegang, mungkin kita memang butuh “Bapak Aing”—seorang semi-dewa lokal yang tahu bagaimana menyalurkan cinta dalam format tiga menit dan subtitle haru.
Barangkali kita tak sedang memilih pemimpin, tapi sedang mencari figur ayah digital. Seseorang yang bisa memeluk kita tanpa menyentuh, menyelamatkan kita tanpa janji, dan menyapa kita tiap sore lewat notifikasi. Sebab ketika dunia terlalu absurd untuk ditata, setidaknya kita bisa menontonnya. Dan dalam drama itu, Dedi adalah protagonis ideal: mitos yang hidup, konten yang berjalan, dan “Bapak Aing” yang kita ciptakan karena realitas terlalu dingin tanpa dongeng.
Deri Hudaya. Buku terakhirnya berjudul Dari Overthinking ke Overachieving: Meditasi, Logika, Tulisan.



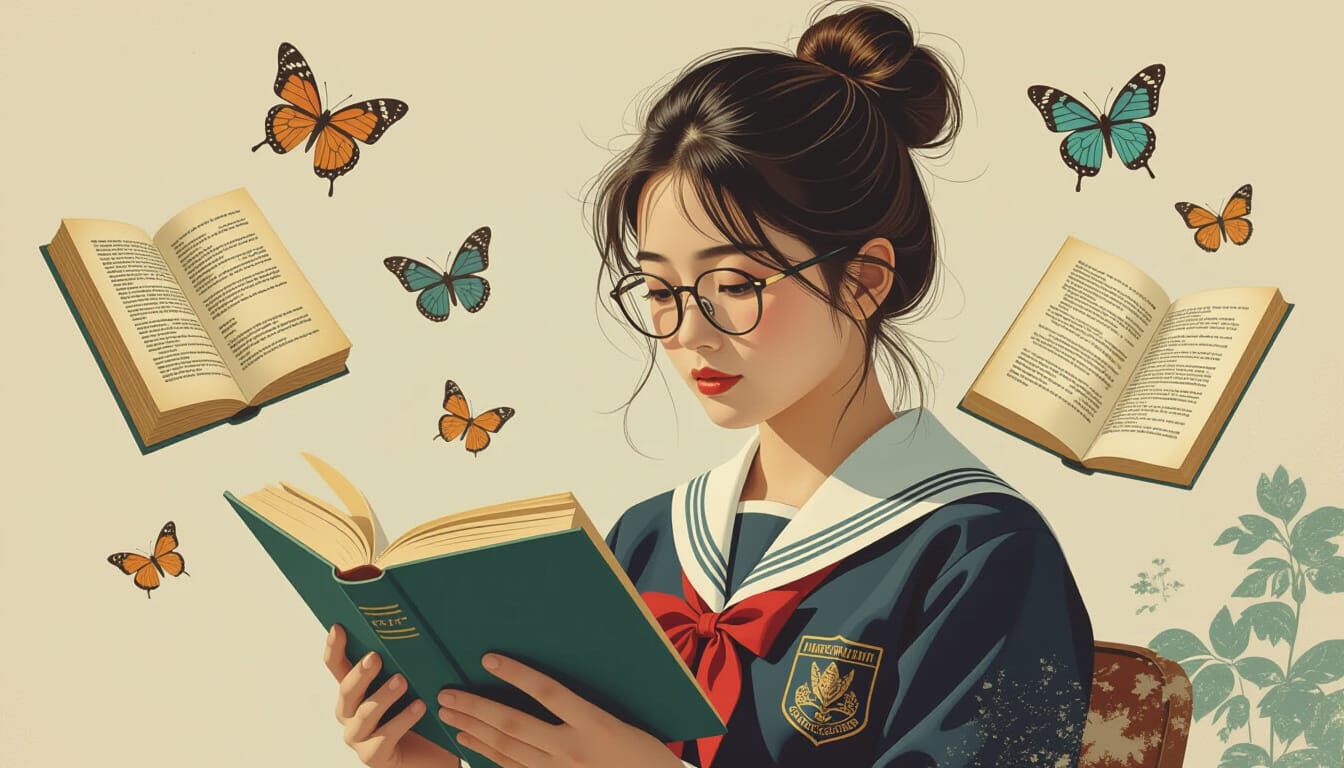
Post Comment