Dedi Mulyadi dalam Posthumanisme dan Cyborg Manifesto
Di tengah reruntuhan narasi modernisme yang pernah memuliakan manusia sebagai pusat segalanya—homo sapiens yang rasional, berkuasa, dan tentu saja laki-laki Jawa yang gemar memakai kopiah—hadirlah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sebagai semacam irisan aneh antara Ki Sunda dan C-3PO. Ia bukan manusia biasa. Ia bukan pula sekadar “Bapak Aing” yang senang turun ke lapangan, mengais-ngais sisa-sisa peradaban yang dilupakan negara. Ia, bila kita tarik lebih dalam, adalah cyborg. Bukan dalam artian berkabel atau bercangkang baja seperti dalam Ghost in the Shell, melainkan sebagai hibrida sosial-budaya yang mengacaukan batas-batas antara yang manusia, yang mesin, dan yang mitologis.
Dalam A Cyborg Manifesto (Donna Haraway, 1985), cyborg adalah makhluk perbatasan—tubuh-tubuh yang meleburkan dikotomi klasik: alam vs budaya, manusia vs mesin, laki-laki vs perempuan, elite vs rakyat. Dalam tubuh Dedi Mulyadi, kita melihat semuanya bercampur jadi satu, bagai sambal ulek yang pedasnya tidak bisa dibedakan apakah dari rawit atau dari kemarahan sejarah. Ia bicara seperti rakyat, berpakaian seperti rakyat (separuh waktu), namun memegang kekuasaan seperti elang yang melayang di atas ladang kering milik petani. Ia mencintai tradisi Sunda, tetapi merayakannya lewat medium video pendek, algoritma YouTube, dan estetika emoji.
Maka tak heran jika dalam dunia pascamodern yang cair, Dedi Mulyadi tampil bukan sebagai politisi, melainkan sebagai entitas posthuman—makhluk pasca-manusia yang tidak lagi bisa direduksi sebagai “pejabat”. Ia adalah content creator, pamong cyborg, influencer berdarah gubernur. Kekuasaan bukan lagi dijalankan lewat struktur hierarkis atau Perda, melainkan melalui “konten yang menyentuh” dan “video yang menginspirasi”. Ia tidak mengatur rakyat, tetapi menyentuh hati mereka, lalu melemparnya ke dalam kumpulan komentar: “Pa Dedi, yeuh… ka dieu atuh, di Cibatu loba jalan bolong!”
Dedi adalah figur yang menolak batas-batas lama. Dalam posthumanisme, sebagaimana dijabarkan oleh Rosi Braidotti dalam The Posthuman (2013), makhluk posthuman tidak sekadar makhluk yang menolak pusat manusia sebagai acuan utama, tapi juga makhluk yang hidup dalam jejaring relasi: dengan lingkungan, dengan hewan, dengan mesin, bahkan dengan likes dan views. Ia bukan lagi subjek yang otoriter, melainkan nodus dalam jaringan semiotik yang lebih luas. Dedi Mulyadi, dengan segala video “penyerahan bantuan sandal ke emak-emak”, adalah nodus itu. Ia tidak hadir sebagai pemimpin dalam pengertian klasik, tetapi sebagai makhluk yang membiarkan dirinya dikonsumsi oleh mata publik, oleh algoritma TikTok, oleh desir notif yang masuk ke HP emak-emak sambil masak sayur asem.
Ironisnya, dalam tubuh cyborg Dedi Mulyadi, kita juga bisa melihat bagaimana rakyat dimasukkan dalam logika posthuman, tapi bukan sebagai agen, melainkan sebagai properti moral. Mereka adalah latar belakang, kadang literal—warga miskin dengan rumah bolong dan anak tanpa seragam. Mereka hadir sebagai manusia yang “diselamatkan”, bukan sebagai subjek yang memutuskan. Seperti yang ditunjukkan Haraway, cyborg selalu mengandung potensi pembebasan sekaligus pengawasan. Posthumanisme, sebagaimana cyborg, adalah medan ambiguitas: antara emansipasi dan eksibisi.
Kita pun patut bertanya: apakah video Dedi Mulyadi yang menyantuni, menyapa, dan menyentuh, sungguh menyuarakan rakyat? Ataukah rakyat telah direduksi menjadi latar dramatis bagi narasi cyborg heroik yang ingin memperlihatkan betapa sistem bisa dikuasai oleh satu orang yang “berhati nurani”? Dalam imajinasi posthuman, tubuh biologis menjadi tidak penting. Yang penting adalah bagaimana tubuh itu bisa dipertunjukkan. Maka rakyat pun harus tampil. Mereka harus bersedih, mereka harus menangis, mereka harus bilang “hatur nuhun, Pa Dedi.” Mereka menjadi efek visual dari mesin kekuasaan yang baru: kekuasaan berbasis empati yang dikapitalisasi.
Dalam dunia posthuman, kekuasaan tidak lagi berada di ruang rapat atau meja kantor saja, tetapi dalam sorotan kamera HP. Dedi Mulyadi tidak butuh konstituen; ia butuh audien. Ia tidak perlu partai; cukup algoritma. Ia tidak menjanjikan perubahan struktural, tetapi perubahan persepsi. Politik bukan lagi urusan kebijakan, tetapi pengaruh. Maka slogan “Bapak Aing” bukan lagi tentang keterwakilan, tetapi tentang personalisasi. Rakyat bukan lagi massa kritis, tetapi followers setia. Demokrasi tak lagi bersuara dalam forum warga, tapi bergema dalam kolom komentar.
Dedi Mulyadi adalah cyborg Sunda paripurna: separuh tokoh, separuh tontonan. Ia menjahit mitos tradisional dan teknologi digital, mencampurkan nilai-nilai konservatif dengan gesture mainstream media. Ia tidak sekadar menjembatani masa lalu dan masa depan, tetapi menghapus batasnya. Ia bukan pejabat. Ia konten. Ia bukan manusia. Ia format MP4 dengan subtitle kesedihan.
Tapi haruskah kita marah? Tidak. Dalam dunia posthuman, kemarahan pun sudah tidak efektif. Yang tersisa hanyalah analisis. Atau mungkin… satire. Sebab, bukankah kita juga demikian?

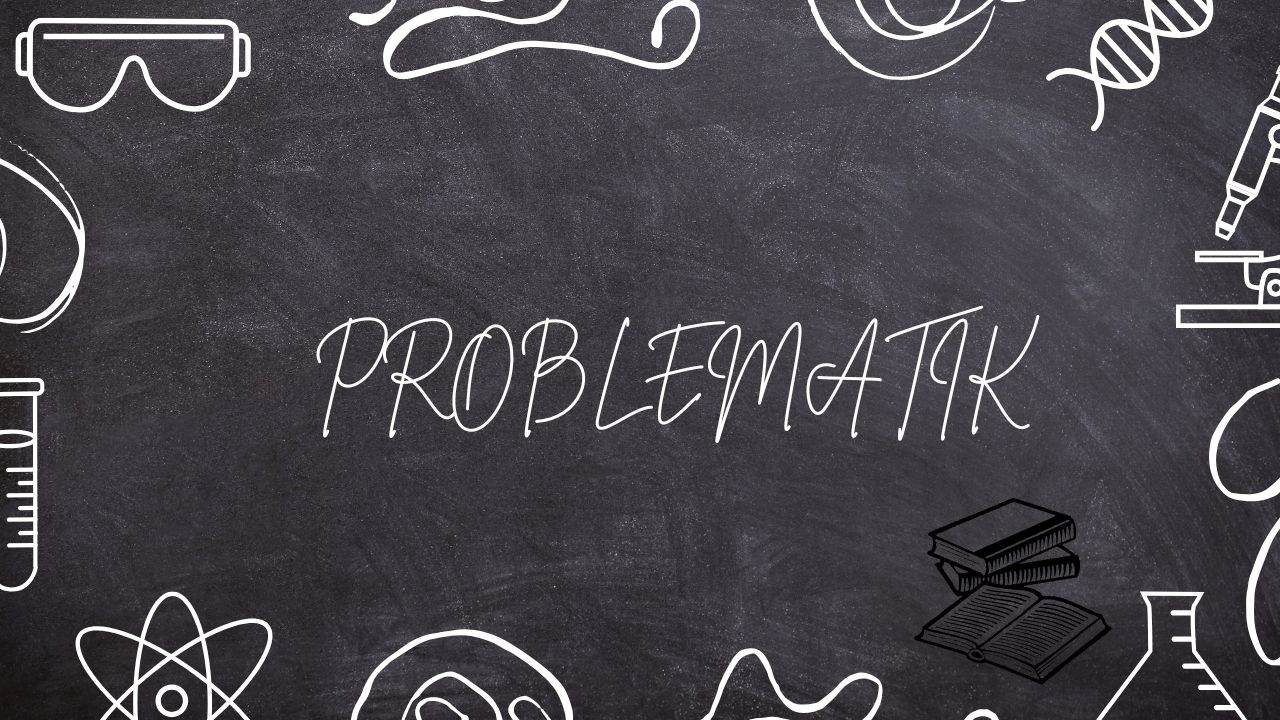

Post Comment