Membaca Bali dalam Puisi Pranita Dewi
Membaca Puisi Pranita Dewi1
Ketika seorang penyair memberi judul bukunya dengan mengambil satu sajak di dalamnya, kita boleh menduga bahwa puisi itu adalah poros utama. Begitu pula ketika membaca kumpulan puisi Nyawa, Tinggallah Sejenak Lebih Lama (2024) karya Pranita Dewi, penyair kelahiran Bali 1987.2 Puisi itu tidak sekadar lirih, tetapi juga menandai arah yang ia tempuh setelah Pelacur Para Dewa, kumpulan puisi pertamanya. Buku debutnya itu menawarkan satire atas banalitas di balik tradisi dan spiritualitas Bali. Kali ini, terutama pada puisi yang dijadikan judul, tendensinya bukan lagi soal sindiran, tapi tidak adanya harapan. Fatalistik.
Nyawa, Tinggallah
Sejenak Lebih Lama
Aku berjalan di kota yang berubah
lebih cepat daripada hati manusia.
Aku sering mencium lagu di tiap tikungan,
tersandung oleh kata-kata di trotoar,
dan bertabrakan dengan baris-baris yang
pernah dimimpikan oleh para petapa dan
pendeta ratusan tahun yang lalu.
Di kota ini, terompet kesunyian
mengalun sepanjang malam.
Aku berdiri memandang cakrawala merah
dan menduga-duga
tentang malam hari.
Aku menerima apa saja
yang diberikan matahari
kepadaku.
Bila wangi dupa mulai berpendar-pendar
dan patung-patung dewa yang anggun
bersila dan terpejam, di situlah hatiku mulai
mengajariku
untuk gentar.
Tapi aku hanya mendapati jejak-jejak
mimpi buruk pada wajah
orang-orang.
Hatilah yang mengajariku untuk gentar
bila keresahanku tumbuh menjadi
sajak di tiap jengkal aspal:
sajak yang menjadikan remaja lagi
semua yang telah patut
bertumpu pada tongkat kayu
dan menjadikanku pembunuh yang
bagaikan seorang raja,
tanpa pelayan dan mahkota,
masuk ke semua rumah sakit dan istana,
lalu, seperti seorang penyair sejati,
memuliakan semua yang hina.
Kini aku akan pergi seperti daun-daun yang lebat
berguguran pada jam-jam larut dan menghilang
tanpa pesan ke dalam kegelapan.
Masihkah aku akan sempat melambai bila nanti
aku telah sampai di garis batas terakhir antara
Tuhan dan bahasa?
O nyawa, tinggallah sejenak lebih lama
“Aku berjalan di kota yang berubah lebih cepat daripada hati manusia.” Bagian ini adalah pengakuan keterasingan. Bali modern, dengan hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan kafe yang tumbuh rakus, bergerak lebih cepat daripada hati manusia yang belum sempat menyesuaikan diri. Ironinya, manusialah yang tercecer di belakang ciptaannya sendiri. Kecepatan meninggalkan urusan permenungan, penghayatan, yang butuh jeda.
“Aku sering mencium lagu di tiap tikungan, tersandung oleh kata-kata di trotoar, dan bertabrakan dengan baris-baris yang pernah dimimpikan para petapa.” Di sini, penyair menghadirkan paradoks yang lebih. Kota modern memperlihatkan spiritualitas yang terserak di trotoar. Lagu, kata-kata, dan baris doa para petapa masa lalu kini hadir bukan dalam keheningan hutan atau di puncak gunung, melainkan di persimpangan jalan, di antara kendaraan dan papan reklame. Simbol-simbol rohani masih bertebaran di udara Bali, tetapi dalam bentuk serpihan yang membuat orang tersandung, bukan lagi menaikkan batin. Yang sakral telah bergeser ke ruang profan yang bisa saja banal; yang dulu ditulis para petapa kini berdesakan dengan iklan diskon.
“Terompet kesunyian mengalun sepanjang malam.” Sebuah paradoks kembali muncul. Di tengah pesta dan riuh turis, kesunyian justru semakin nyaring. Bali dihadirkan ramai, sibuk dan bising, tapi secara bersamaan menghasilkan kekosongan.
“Bila wangi dupa mulai berpendar-pendar dan patung-patung dewa yang anggun bersila dan terpejam, di situlah hatiku mulai mengajariku untuk gentar.” Simbol-simbol sakral tetap ada—dupa, patung, upacara—namun wajah manusia justru penuh keresahan. Ritual memang berlangsung, tapi ruhnya rapuh. Kenyataan sehari-hari pun memperlihatkan hal yang sama. Wisatawan kerap masuk pura tanpa tata cara, model bugil berfose di bawah pohon keramat, bahkan ada yang menantang pecalang saat diminta menghormati upacara. Dewa-dewa tetap bersila, tetapi keresahan manusia di sekelilingnya tidak berkurang.
Keresahan dalam puisi ini semakin terbaca ketika ia menulis tentang sajak yang tumbuh “di tiap jengkal aspal,” menjadikannya “pembunuh bagaikan seorang raja, tanpa pelayan dan mahkota.” Baris ini terdengar liar, penuh amarah. Puisi tidak lagi hadir sebagai hiasan, melainkan sebagai perlawanan—energi untuk menolak tunduk sepenuhnya pada dunia yang dikuasai aspal dan modal. Ia lebih tertarik untuk “memuliakan semua yang hina.”
Hingga akhirnya, penyair menutup dengan pengakuan fana: “aku akan pergi seperti daun-daun yang lebat berguguran pada jam-jam larut.” Sebuah akhir dibayangkan terjadi begitu saja, tanpa ada perhatian, tanpa ada yang memerhatikan. Lalu doa lirih itu mengalun: “O nyawa, tinggallah sejenak lebih lama.” Inilah ungkapan fatalistiknya: permohonan agar nyawa bertahan sejenak–bukan lama. Bukan hanya nyawa pribadi, mungkin, tetapi juga nyawa kolektif dari satu kebudayaan. Ia tahu, sesuatu sedang terancam lenyap—dan bukan hanya tubuh manusia yang fana, tetapi juga ruh sebuah pulau.
Kesadaran ini bukan sekadar metafora puitis. Bali memang menyimpan luka batin. Pada 2023, laporan Jakarta Globe mencatat Bali memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia, yakni 3,07 kasus per 100.000 penduduk. Periode sebelumnya, 2015-2018, laporan dari The Royal Lotus Initiatives menyebut sekitar 34 dari setiap 1.000 orang Bali mengalami gangguan mental—dua kali lipat dari rata-rata nasional. Angka-angka ini menyingkap paradoks getir: pulau yang disebut “pulau dewata” ternyata juga tanah dengan krisis batin paling dalam.
Membaca puisi ini tidak bisa mengabaikan kegelisahan sosial yang terjadi di Bali sebelum buku dan puisi ini diterbitkan. Pranita Dewi menulis dengan tubuh Bali, dengan luka Bali, dengan paradoks Bali: antara tradisi dan modernitas, doa dan perniagaan, hati dan aspal.
Mutasi Kebudayaan
Membaca puisi ini dengan kacamata evolusi terasa lebih ironis, tetapi justru di situlah relevansinya. Darwin pernah bicara tentang seleksi alam: yang bertahan adalah yang mampu beradaptasi. Namun Bali memperlihatkan hal yang lebih rumit: bukan sekadar adaptasi, melainkan mutasi. Mutasi sosial dan kultural terjadi ketika sesuatu tidak lagi sama dengan bentuk asalnya. Upacara yang dulunya doa kini bisa berfungsi sebagai atraksi. Bahasa tubuh yang dulu sakral kini bisa disulap menjadi pertunjukan untuk kamera. Bahkan pura—pusat kosmologi masyarakat Bali—kadang difungsikan pula sebagai latar foto prewedding.
Tentu saja mutasi ini bukan terjadi secara halus. Ia berlangsung brutal, seperti tubuh yang dipaksa berganti organ dalam semalam. Dan di titik itulah suara lirih Pranita Dewi menemukan maknanya. Doa agar “nyawa tinggal sejenak lebih lama” tidak lahir dari kecemasan pribadi seorang penyair. Itu adalah keputusasaan kolektif. Ia mencerminkan keresahan sebagian orang Bali yang melihat tanah mereka bertransformasi terlalu cepat, lebih cepat daripada hati, lebih cepat daripada doa.
Yang terancam lenyap bukan kura-kura atau nyawa biologis manusia, melainkan ruh kebudayaan. Sebuah nyawa komunal yang sudah ratusan tahun bertahan melalui ritus dan simbol, kini dipaksa menjalani mutasi yang belum tentu diinginkan atau lebih baik. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah manusia sanggup bertahan hidup, melainkan apakah peradaban yang kita kenal sebagai Bali masih sanggup mempertahankan jiwanya.
Bila Darwin menyebut “survival of the fittest,” maka di Bali kita kerap menyaksikan “survival of the most marketable.” Yang bisa bertahan bukanlah yang paling asli, melainkan yang paling bisa menjual keaslian.3 Ironinya, yang bertahan justru tiruan, bukan sumber. Bali bisa saja tetap hidup, tetapi dalam bentuk lain: pura sebagai ikon pariwisata, tarian sakral dipadatkan menjadi sepuluh menit pertunjukan, sesajen yang dulunya doa kini lebih sering jadi properti kapitalisme dan pariwisata.
Di titik inilah puisi Pranita Dewi bekerja bukan lagi sebagai peringatan.4 Nyawa bisa lenyap bukan hanya dari tubuh manusia, tetapi juga dari tubuh kebudayaan. Dan ketika kebudayaan kehilangan nyawanya, maka peradaban akan terasa seperti patung yang kosong di dalam: anggun bersila, tetapi orang-orang di sekitarnya dipenuhi “mimpi buruk”.
Pasca-Putus-Asa
Pertanyaan terakhir Pranita Dewi begitu getir dan manusiawi: “Masihkah aku akan sempat melambai bila nanti aku telah sampai di garis batas terakhir antara Tuhan dan bahasa?” Baris itu terdengar seperti ucapan seorang peziarah yang menyadari ia berdiri di ambang batas, bukan sekadar ambang kematian personal, tetapi ambang kebudayaan yang komunal. Namun Bali bukanlah satu-satunya tubuh yang sedang berdiri di batas itu.
Sebab di banyak tempat dan di berbagai bidang, mutasi itu terjadi dengan liar. Mata uang bermutasi dari koin menjadi kertas, dari kertas menjadi digital, dari digital menjadi kripto. Manusia bermutasi menjadi pascamanusia—posthuman—yang tubuhnya ditopang mesin, pikirannya disangga algoritma, emosinya diserahkan pada platform. Kecerdasan pun bermutasi: dulu lahir dari pengalaman dan penghayatan, kini dari jutaan parameter yang diproses kecerdasan artifisial. Yang fisik bisa digantikan yang virtual: pasar malam diganti marketplace. Tidak ada yang menjamin bahwa mutasi akan mengubah sesuatu menjadi lebih baik, memang. Tidak pasti.
Keresahan dalam puisi Pranita Dewi bisa relevan dengan keresahan banyak orang. Doa agar “nyawa tinggal sejenak lebih lama” bukan hanya permintaan seorang penyair di pulau dewata, tetapi juga dialog kepada umat manusia yang sedang kebingungan menghadapi mutasi besar-besaran, di mana-mana, dalam segala. Kita tidak tahu bagian mana dari manusia yang akan bertahan, dan mana yang akan punah. Apakah doa akan tetap ada, atau digantikan dengan bahasa algoritma? Apakah metafora akan bertahan, atau diganti emoji? Apakah cinta akan tetap diucapkan atau diperjuangkan?
Mutasi budaya, ekonomi, dan teknologi yang sedang terjadi tidak membuat nyaman. Evolusi kebudayaan yang terus terjadi secara perlahan dan tak selalu disadari, telah berubah jadi revolusi yang mengagetkan. Karena itu, membaca puisi Pranita Dewi hari ini seperti mengingat kegamangan kita sendiri yang mungkin sempat lupa. Kita mungkin tidak hidup di Bali, tidak menghirup dupa di pura, tidak menyaksikan turis mengacaukan ritual. Namun kita sama-sama berdiri di garis batas yang sama, antara Tuhan dan bahasa, antara manusia dan mesin, antara nyawa yang sakral dan kematian yang cuma urusan teknis.5
Dan mungkin, seperti Pranita Dewi, yang bisa dilakukan salah satunya adalah berdoa lirih, agar nyawa—dalam arti yang paling luas—tinggal sejenak lebih lama. Ini sangat manusiawi sekaligus romantis–dalam arti: fatalistik terhadap waktu-waktu yang akan datang dan mengidealkan masa silam. Tapi ironi besar bisa kita pertimbangkan kemudian. Dalam evolusi, tidak ada spesies yang “tinggal lebih lama.” Mereka hanya bisa bertahan dengan cara berubah. Bali seribu tahun lalu, bukan pulau dewata seperti yang kita kenal. Puisi adalah hasil tabrakan dari berbagai bahasa dan pengalaman. Homo Sapiens seperti Pranita Dewi memiliki sejarah evolusi yang tidak semuanya dapat dipahami.
Barangkali permintaan paling radikal bukanlah “tinggal sejenak lebih lama.” Dalam dunia yang bergerak lebih cepat daripada hati manusia, yang paling berani sepertinya bukan memohon waktu ditunda, melainkan yang rela melompat ke bentuk baru. Tantangan bagi puisi Pranita bukan sekadar menunda ritual kematian, tetapi berani menjadi spesies lain—menghasilkan bahasa yang tak lagi doa, tak lagi iklan, tak lagi grafiti atau puisi, tapi sesuatu yang bahkan Darwin pun, seandainya hidup kembali, tidak sanggup memberi nama.
Deri Hudaya, buku puisinya yang telah terbit berjudul Lawang Angin dan Puisi-Puisi Lainnya. Saat ini bekerja sebagai dosen Kajian Budaya di Universitas Garut.
- Esai ini disampaikan pada Sesi Diskusi Buku Puisi Penyair Muda, Hajatan Sastra Rumah Koclak 2025, 27-30 Agustus di Gedung Kesenian Ciamis.
↩︎ - Menyebut Pranita Dewi sebagai penyair muda sangat relevan ketika ia menerbitkan buku puisi debut yang judulnya propokatif: Pelacur Para Dewa. Pada buku keduanya ini apakah masih bisa disebut masih muda? Bukankah kaum muda saat ini lebih identik dengan Generasi Z? Pranita lahir 1987, dalam banyak ukuran termasuk Milenial–generasi antara Generasi Z dan Generasi Old–generasi yang telah mengalami banyak kegagalan dan pencapaian di masa muda, tapi benar-benar matang pun belum.
↩︎ - Bayangkan Dedi Mulyadi, misalnya.
↩︎ - Tema tabrakan antara tradisi dan modernitas, antara masa lalu dan masa depan, bukan sesuatu yang baru dalam jagat puisi atau lebih luas lagi sastra di Indonesia. Tema seperti ini sudah ditulis oleh penyair dan sastrawan lain. Kredo: “menolak tradisi, bertolak dari tradisi” bahkan identik dengan penyair Sunda, Godi Suwarna. Makna kredo itu dapat ditemukan pada banyak sekali karya sastrawan Indonesia.
↩︎ - Di Ciamis ada praktik budaya “Nyiar Lumar”, tepatnya di situs Astana Gede, Kawali, dengan artistik tanpa lampu atau penerangan dari teknologi modern. Penerangan semalam suntuk berasal dari bulan, kalau ada, dan dari jamur alami bernama “lumar”, yang berpendaran dari balik semak dan kayu-kayu lapuk. Setelah pandemi, praktik budaya itu terpapar cahaya-cahaya modern karena banyak sekali pengunjung melakukan live TikTok, atau membuat dokumentasi dengan ponsel pintar.
↩︎
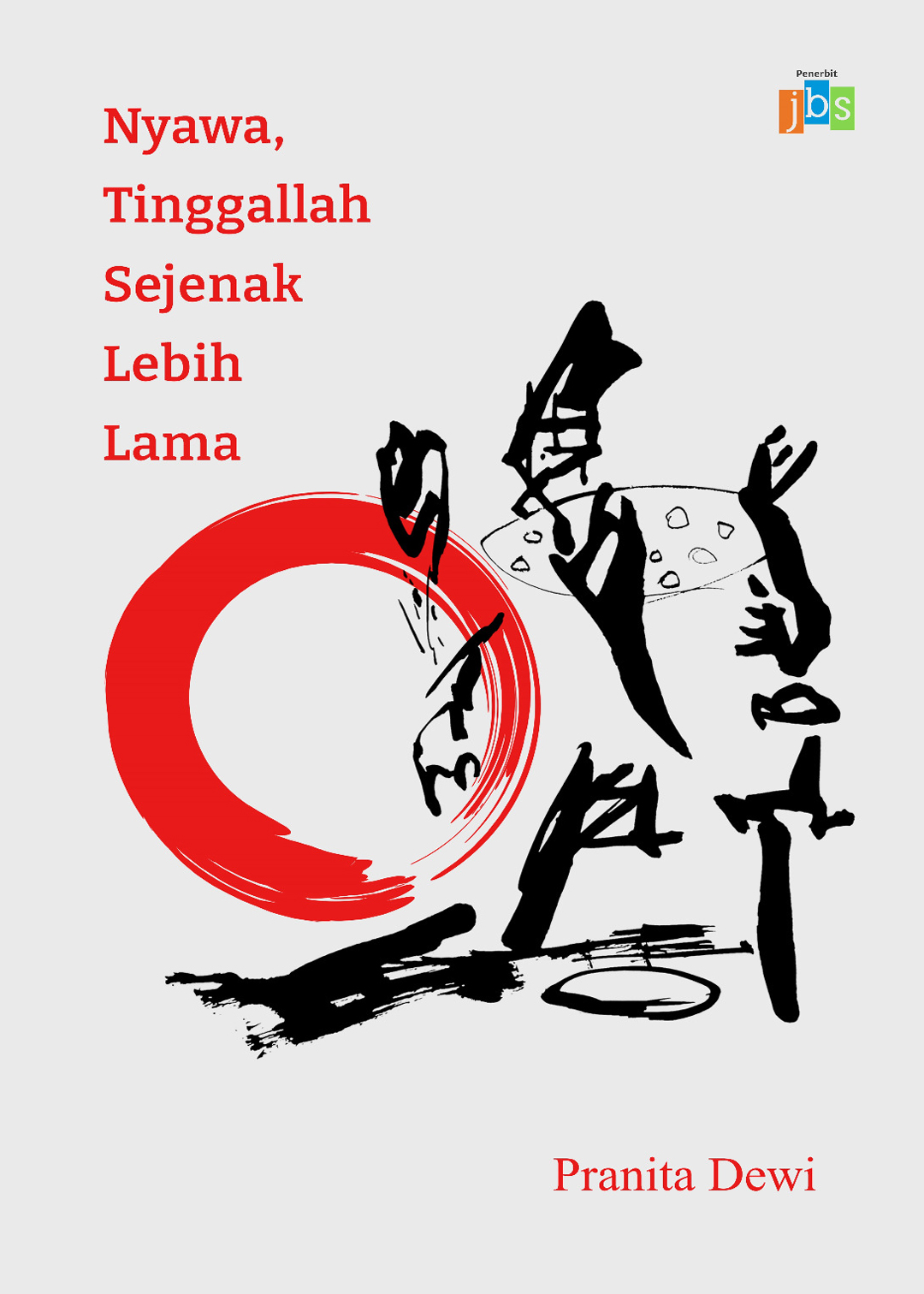



Post Comment