IQ 78
IQ 78
Ada kabar berseliweran bahwa rata-rata IQ orang Indonesia hanya 78. Angka yang, bagi sebagian bangsa, mungkin memalukan; bagi kita, malah jadi bahan becandaan nasional—seolah-olah kita sedang berlomba siapa yang paling santai menanggapi tragedi. Tentu saja orang akan membandingkannya dengan gorila atau simpanse. Dan ketika mereka bilang perbedaan kita dengan primata itu hanya beberapa digit, saya tidak tersinggung. Saya justru menatap angka itu lama-lama dan berpikir, “Hmm, ya masuk akal juga.”
Lagipula, siapa saya untuk protes? Saya pun sering kesulitan memahami konsep-konsep yang katanya “dasar”. Kalau ada orang menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak—entah ekonomi, kosmologi, atau teori apa pun yang lebih rumit daripada cara membuat mi instan tiga rasa—otak saya langsung mendadak kabur, seperti WiFi yang sinyalnya tinggal satu bar. Saya sejak kecil memang tidak berbakat memahami hal-hal yang mengawang; logika saya pendek, napas intelektual saya pendek, dan imajinasi saya kadang-kadang seperti bohlam kamar kos yang redupnya sudah pasrah.
Jadi ketika ada orang berkata bahwa IQ bangsa ini cuma 78, saya tidak refleks menolak. Saya tidak merasa “terhina”. Saya lebih merasa, “Ah, betul. Saya bagian dari itu.” Dan saya rasa banyak orang juga merasakan hal yang mirip. Kita tidak perlu pura-pura jenius hanya karena takut dianggap simpanse. Hidup ini sudah cukup berat tanpa perlu menambah beban akting jadi orang pintar.
Kalau dipikir-pikir, kondisi ini tidak muncul tiba-tiba. Kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak memberi ruang bagi kecerdasan untuk berbunga. Kita dibesarkan bukan dalam taman pengetahuan, tetapi dalam hutan rimba survival: sekolah untuk lulus, bukan belajar; baca buku untuk ujian, bukan memahami; menghafal untuk dapat nilai, bukan mengerti. Setelah itu, hidup berjalan lurus seperti rel kereta: cari nafkah, menikah, punya anak, ulangi pada generasi berikutnya. Kita dididik bukan untuk berpikir, melainkan untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup tidak butuh teori kritis—yang dibutuhkan adalah makan dan keturunan.
Ironisnya, dua kata itu—makan dan keturunan—secara mengejutkan sangat dekat dengan naluri primata. Simpanse pun melakukan hal yang sama: mencari makan, berebut pasangan, lalu meneruskan garis keturunan. Mereka hanya tidak membuat KTP dan tidak antre BPJS. Tapi struktur besar kehidupan? Mirip. Jadi sebenarnya perbandingan kita dengan simpanse bukanlah penghinaan, melainkan cermin evolusi yang setengah selesai.
Lagi pula, bagaimana mungkin kita berharap bangsa ini memiliki IQ tinggi kalau waktu untuk berpikir saja tidak ada? Ketika orang pulang kerja jam delapan malam, kaki gemetaran, punggung seperti habis dicincang, apakah mereka masih punya energi untuk membaca teori ekonomi politik atau sejarah pemikiran? Tentu tidak. Mereka akan memilih hal yang paling manusiawi: tidur, atau scrolling video 10 detik yang tidak menuntut apa pun selain kemampuan menggerakkan jempol. Dan kalau boleh jujur, kadang-kadang saya pun lebih memilih itu.
Di sisi lain, literasi kita seperti dekorasi ruang tamu: ada rak buku, ada kutipan motivasi, ada semangat palsu untuk “mencerdaskan diri”, tapi di dunia nyata jarang yang benar-benar membaca. Buku-buku yang dijual di toko sering kali tidak disentuh kecuali untuk difoto lalu diunggah dengan caption klise. Pendidikan hanya menjadi syarat administratif, bukan perjalanan intelektual.
Maka, kalau kecerdasan bangsa ini rata-rata rendah, itu bukan misteri. Itu adalah hasil dari sistem panjang yang membesarkan kita bukan sebagai pemikir, melainkan sebagai pekerja, konsumen, dan pewaris rutinitas. Bukan karena kita tidak mampu menjadi cerdas, tetapi karena kita tidak diberi waktu, ruang, dan dukungan untuk mencobanya.
Jadi ketika ada yang bertanya, “Salah siapa IQ kita rendah?” saya hanya bisa mengangkat bahu. Bukan salah gorila. Bukan salah simpanse. Mereka bahkan tidak pernah menuntut kita untuk meniru mereka sedekat ini. Mungkin salah sejarah. Mungkin salah kebijakan. Mungkin salah kemiskinan struktural, pendidikan yang tidak merata, budaya yang lebih menghargai kepatuhan daripada rasa ingin tahu.
Atau mungkin—dalam ironi yang paling jujur—semuanya salah kita. Kita semua. Karena kita terlalu sibuk bertahan hidup sampai lupa belajar hidup.
Dan mungkin itu sebabnya angka 78 terasa tidak jauh dari rumah.
#IQ #IQ78
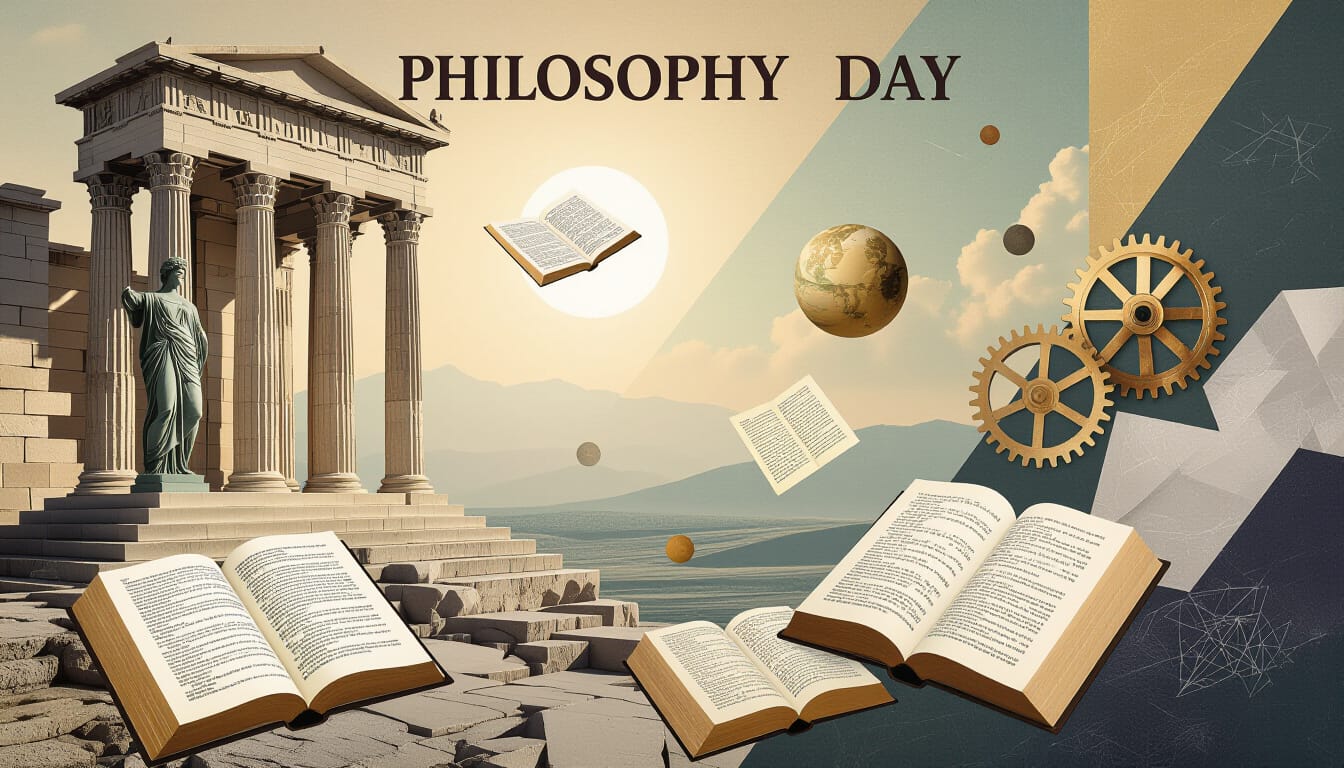
Post Comment