Membaca Messy Teks: Fakta dan Fiksi yang Berkelindan
Oleh: Ninuk Kleden-Probonegoro, Antropolog penggemar fiksi.
Saya belum menemukan istilah yang tepat untuk mengganti diksi messy[1]. Menurut kamus[2] ia adalah kondisi yang kacau (chaos), dan morat-marit, tidak teratur. Padahal saya tidak melihatnya demikian. Ia justru merupakan ruang di mana kekacauan bisa bersuara. Sehingga biarlah tetap messy, meskipun tidak ditulis text tetapi teks.
Messy teks sebenarnya sudah dikenal lama dalam karya sastra, tetapi tidak sebagai konsep dan kerangka pikir. Di sinilah saya beranikan diri menguarkan benang merah pengikat karya (semoga).
Ekspresi Messy Teks
Messy teks, cara penulisan baru dalam etnografi, mempunyai banyak wajah; berbagai perspektif, berbagai genre; cerita pribadi, cerita pendek, novel[3]. dan juga jurnalisme baru[4] yang faktanya dijadikan fiksi.
Esei ini hanya menyoroti messy teks dalam penggalan tiga genre; cerpen, novel, dan kolom baru tentang Obrolan Sukab.
Cerpen
Dalam cerpen ini messy teks hadir dekat dengan realitas sehari-hari. Ia tak berjarak dari penulisnya, bahkan dari pembacanya. Kalimat yang tampak sederhana kadang menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan; antara pengalaman dan tafsir, antara luka dan harapan. Di sanalah batas fakta dan fiksi menjadi kabur. Sebuah peristiwa nyata diberi nafas imajinasi, menjadi pengalaman batin dalam teks. Nada yang menyatu dengan irama, fakta dengan fiksi, menjadikan hidup tampak paling rawan; kadang jujur, kadang tulus, meskipun kadang ia bersembunyi di balik fiksi yang menenangkan dalam kemampuannya menggores warna abu-abu.
Cerpen Erni Cokek Teluk Naga memperlihatkan proses itu. Kehidupan cokek, yang biasa ngibing memeriahkan pesta hajatan. Awalnya hanya deskripsi-etnografi, berisi informasi tentang cokek. Kemudian diubah ke dalam bentuk cerpen. Teks itu jadi mempunyainafas kehidupan, menjadi narasi penuh rasa.
Erni Cokek Teluk Naga [5]
Malam makin padat, alunan Gambang Kromong makin keras, nada makin meninggi. Suara kendang tak putus-putus, bahkan makin terhentak-hentak, barisan ngibing juga makin merapat. Erni sudah memutar pinggul, kalau Johny mendekat, pinggul dia ayun. Indah dan erotis sekali.
***
Kini muncul Bin Seng di depan Erni. Ia segera ngibing dengan gaya panas, tanpa pemanasan. Sekali-kali kepalanya maju ke depan layaknya burung mematuk jewawut. Wajah Erni jewawutnya. Erni mulai gemetar dan ia tutup matanya. Ada yang mendarat di pipinya. Erni lihat Isah sekedipan, menangis digendongan neneknya, tapi Isah tidak ada.
Segera ia tarik handuk yang bertengger di bahu, menyeka wajahnya, meludah ke lantai, dan mendesis “huh.”
“Bau bir.” Katanya lirih.
***
Dini hari, rumah dengan banyak bilik itu dibuka seorang penjaga. Bilik-bilik berderet tanpa pintu, hanya ditutup selembar kain gorden yang berkibar menari sewaktu tersentuh angin. Mereka masuk satu persatu. Tidak lama senyap, rumah itu sepi. Semua tenggelam dalam nikmat mimpi. Tidur dalam damai yang hanya dipinjam sampai pagi.
***
Aula itu terlalu hening. Lantainya licin mengilat, kursi berjejer di sisi dindingnya. Dan tape recorder duduk kaku di sudut. Tidak ada bau bir, tidak ada asap rokok, tidak ada nada yang menggoda tubuh. Sepi.
Erni tidak muncul di pertemuan itu. Sambil menyendok ketupat sayur bersantan, mengunyahnya perlahan, pikirannya hadir bersama teman-temannya di pelatihan.
Ngapain ikut pelatihan? Kata hatinya. Erni ingat bagaimana ia ngibing. Rasakan nada dan masukkan dalam jiwa, maka nada akan menggoyang tubuh. Itu ngibing, pikir Erni.
“Latihan hari ini cukup, Kamis datang lagi ya,” suara bu Asni menutup acara pelatihan. “Kita harap, pelatihan ini membuat ibingan bisa lebih sopan, dan bermartabat,” lanjutnya dengan nada suara percaya diri.
Tidak ada tepuk tangan. Mereka tahu, uang martabat tidak bisa untuk bayar bilik bergorden, beli susu bocah, dan tidak cukup untuk beli sabun.
Tentang Erni Cokek Teluk Naga
Cerpen ini termasuk Etnografi Novelistik[6] yang memperlakukan novel sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Teks awal berupa deskripsi-etnografi yang diseminarkan di Prodi Studi Sastra Cina UI (14 Mei 2002). Teks seminar yang merekam kehidupan cokek Teluk Naga, Tangerang, kemudian terbit sebagai informasi tentang cokek,[7]” Teks ini lah yang kemudian diberi nafas kehidupan dalam bentuk fiksi.
Fakta ibingan panas disisipi sekedip imajinasi munculnya Isah, anak Erni. Ia bisa menimbulkan konflik batin Erni.
Erni mengelap mukanya dengan handuk kecil tanpa warna yang bertengger di bahunya, dan meludah ke lantai saat ngibing dengan pria bau bir itu. Suatu fakta, tindakan nyata itu, bisa menjadi pintu masuk ke dalam relung emosi yang hanya bisa diakses melalui fiksi. Peristiwa itu menimbulkan perlawanan diam dari Erni.
Seperti juga saat pemerintah ingin membuat ngibing berbudaya dan bermartabat. Erni menampiknya. Ia membayangkan ngibing. Rasakan nada dan masukkan dalam jiwa, maka ia akan menggoyang tubuh. Itu ngibing, bukan bermartabat yang tidak bisa untuk bayar bilik bergorden, beli susu bocah, dan tidak cukup untuk beli sabun.
Dengan cara itu, deskripsi-etnografi masuk ke dalam relung batin dan emosi, menyelam dan menangkap persoalan sebenarnya yang ada di sana, yaitu “tidak bisa membeli susu bocah.”
Novel
Messy teks terasa nyata saat dihadapkan pada karya sastra yang lahir dari pengalaman lapangan. Etnografi tidak lagi sekadar mencatat dan merekam fakta, melainkan juga menafsir. Imajinasi bekerja di dalam data, emosi menyusup di antara fakta. Messy teks merangkai serpihan hidup menjadi perjalanan suatu pengalaman. Fakta melebur dalam tafsir. Novel dengan setting Pulau Mentawai berhiaskan adat-kebiasaan kebudayaannya, membuat kita bertanya mana teks etnografi dan mana fiksi?
Burung Kayu[8]
Muturuk (1)
SIKEREI muda itu menari bersama roh para leluhur yang telah diundang-dipikat tujuh sikerei tua dengan semahan telinga kiri seekor babi.
Ia menari dan menari, kakinya mengentak-entak lantai, tangannya merentang tegang. Pukulan-pukulan pada gajeumak, yang bagian kulitnya mesti dipanaskan berkali-kali di dekat api, meningkahi setiap gerak-lakunya merentak. Tato di sekujur tubuhnya berkilap kilap diterpa cahaya lampu minyak. (1)
Silumang
Ketiganya tengah berlayar menuju barasi, menuju dusun bikinan pemerintah, menuju rumah-rumah kayu yang kelewat mungil dibanding uma yang mereka tinggalkan.
“Mau makan apa kalian di barasi?” tanya sikebbukat uma. “Pemerintah melarang memelihara babi.”
“Pohon sagu kalian di sini, durian dan langsat ada di sini. Ladang gette ada di sini. Kelapa ada di sini. Babi dan ayam ada di sini.” (7)
Tapi tekad Taksilitoni, yang telah ditularkan dengan caranya sendiri kepada Saengrekerei – memengaruhi beberapa saudara lelaki se-umanya. Beberapa bajak mendukung rencana pepindahan mereka ke barasi. Bahkan beberapa taluba dan eira berencana menyusul.
”Asal jangan terlalu ke hilir, jangan terlalu ke pesisir,” salah seorang bajak mengajukan syarat.(7)
***
Umat Simagere
Aman Legemanai masih mengukir seekor burung enggang di kayu terakhir. Burung kayu yang dulu, dulu sekali, sebagaimana dikisahkan tereunya pada malam-malam riang, pernah ditenggerkan rimata di puncak sebuah pohon paling tinggi yang dahan dan daunnya telah dipangkas, digunduli. Pohon katuka bagi seekor burung kayu bergaris-garis hitam yang menjadi simbol “kemenangan” pako yang menjeda atau menunda perkelahian, pertikaian, pengayauan dalam uma yang tengah bermusuhan (13)
Tentang Burung Kayu
Novel ini patut disebut etnografi novelistik yang sebenarnya. Aroma etnografinya sangat kental; bahkan mengaumkan konsep “simbol” dan “keluarga batih,” setting pulau, dan kebudayaan Mentawai. Membaca novel ini menuntut kesabaran, karena ia meniadakan daftar isi dan glosari, membuat pembaca menyusuri teks seperti masuk hutan Mentawai tanpa pemandu.Sebenarnya pembaca sedang mengalami apa yang dialami subyek etnografi, kebingungan. Bab dan sub babnyapun bagaikan kata tanpa penanda. Membuat pembaca mencari makna melalui pengalaman dan bukan struktur.
Ia bukan buku etnografi. Adat-kebiasaan Mentawai dianyam sebagai narasi. Suatu keluarga yang meninggalkan umanya, untuk menghindari perseteruan, menuju barasi, tempat kediaman baru buatan pemerintah. Padahal barasi mempunyai berbagai masalah baru.
Fakta dan fiksi tidak tampak sebagai suatu hal yang terpisah, seluruh novel adalah fiksi. Bahan dasar fakta etnografi yang direka menjadi satu buku cerita. Di sini fakta dan fiksi menari bersama diberi nafas emosi. Pernikahan Taksilitoni dengan adik mendiang suaminya, adalah fakta di dalam fiksi. Pernikahan mempunyai maksud terselubung, dan itu menjadi fiksi di dalam fiksi.
Adegan manis, dengan nada dan dialog yang biasanya digunakan untuk menunjukkan otentisitas, tidak dikenal. Otentisitasnya tampak dari penggunaan diksi Mentawai dengan tidak mengimbuhkan glosari.
Kolom Baru
Di sini messy teks tampil tanpa jubah sastra, tapi gema fakta, fiksi dan refleksi tetap ada dienyut di dalamnya. Ia berbicara soal realitas yang muncul dalam obrolan. Realitas seperti ini tidak bisa diobservasi. Kekhasan kolom ini adalah kekuatan kreatifitas permainan bahasa yang menjadikan fakta tidak bisa diobservasi, dan fiksi tersembunyi dibaliknya. Fakta dan fiksi ada dalam obrolan, dan selalu meninggalkan bayang yang membuat kita bertanya.
Obrolan Sukab[9]:
“Répolusik! Èh, Répormasik! Èh, …” 30 Agustus 2025
Ntu siang panas-panas warung anabèl rada sepi. Tapinyah kaum anabèl nyang mingsi nganggur, kayak Dul Komprènf mantan kernèt mikrolet, amé Bahlul mantan tukang obat, adé di sono omongin nasèb masing-masing.
“Namènyé jugak jaman berubé Lul,” katé si Dul bari nyomot témpé bacem, “dulu adé mikrolèt, karang kagak adé, kernètnya ikut ngilang, alias jadi pengangguran dèh …”
“Ah, maèn basé dèh énté Lul, ané kan nganggur-nganggur kagak ngerongrong pajak rakyat, ini témpé ….,” doi dorong sisa témpényah masup mulut, “a*#~e ba@rrr p^+_&èk ngo”:ek ja%% !@^+~cepèk.”
“Ah, maèn basé dèh énté Lul, ané kan nganggur-nganggur kagak ngerongrong pajak rakyat, ini témpé ….,” doi dorong sisa témpényah masup mulut, “a*#~e ba@rrr p^+_&èk ngo”:ek ja%% !@^+~cepèk.”
***
“Haiyah mangkin ngacok,” katé Bahlul, “telen dululah Dul!”
Tapinyah ntu témpé bacem ukuran rajak atawa king size separok, kayak nyangkut di tenggorokan. Maté Dul Komprèng mendelik nggak bisé napas, doi punya tangan nunjuk-nunjuk nggak jelaz.
Yati rada panik.
***
Gitu abis langsoen nyambung.
“Ané bayar ini témpé paké ngobyèk jadi mister cepèk! Nggak nyabet duit orang kecil kayak Mentri Perduitan Nyang Maha Srintil.”
Ujug-ujug masup Sukab nyang ngeboncèng Jali, bari kibasin kupluknyé nyang ketimpé helm. Di bagian blakang motor Jali, bendèrè WanPis bekiber.
“Uwah nyang abis démo!” ujar Bahlul, “ntu di tipi mingsi ramé kok udé ke sinih?”
***
Sukab langsoen ngocol.
“Orang nyang démo teréak soal tunjangan Dé-Pé-Èr, èh si Sukab teréaknyé laèn lagéh!”
“Teréak apé?”
“Répolusik! Répolusik! Gétu katényé …”
“Ah, mangsud ané mah Répormasik.”
“Répormasik Jilid Duwa mangsudnyah?”
“Mau Jilid Duwa kèk, mau prékuwèl kèk, pokoknya jangan cumak sepotong-sepotong.”
***
Trus ujan deres.
“Pantes sedari tadé gerah,” katé para anabèlis.
Tentang Obrolan Sukab
Disebut kolom “baru” karena sebelumnya tidak dikenal kolom seperti ini. Istilah kolom baru digunakan layaknya New Journalism (Clair 2003). Kolom baru dalam IHIK3 sepertinya mempunyai kesinambungan dengan Obrolan Sukab (2019). Obrolan sebelumnya seperti cerita, ada penjelasan dengan menyebut teori, sementara obrolan yang sekarang, sempurna ngobrol. SGA terlihat seperti menulis tanpa berpikir, ngobrol melalui jarinya. Padahal ia menyembunyikan kerja pikir yang panjang di balik spontanitas bahasa yang direka sana-sini.
Kolom baru terbit seminggu sekali, pada hari Sabtu. Obrolan pelanggan warung Anabel yang fiktif, dijadikan teks yang bermain di batas fakta dan fiksi. Topiknya sekitar kemiskinan mereka (tukang gali, penganggur, tukang ojek), politik, perilaku pejabat, dan isu hangat seperti makan gratis, pajak, ijazah palsu dan sebagainya.
Fakta dari luar warung yang merupakan kenyataan sehari-hari, dijadikan teks satire, sindiran, dan imajinasi melalui kemampuan permainan bahasa yang piawai. Bukan hanya penggunaan dialek urban Jakarta, tetapi juga bahasa gaul kawula muda, ejaan bahasa Belanda tanpa konteks; dioejoeng, langsoeng, setenge batoek (16/8). Kreatifitas tinggi dengan penciptaan idiom baru, mewarnai kolom ini; zaman ngèhè’, Dé-Pé-Èr méhong, pahanas, maknyédikipé! (18/10). Judul teks kadang tidak menandai isi. “Bendera Item Gambar Tengkorak,” (23/8) adalah penanda selesainya narasi, bukan isi.
Kolom baru juga memaparkan bunyi yang bukan kata, bukan bahasa, tidak bermakna, tapi dia ada di sana.
“Di Warung Anabel. Siang. Pengangguran ngumpul ngomongin nasib. Telan tempe “a*#~e ba@rrr p^+_&èk ngo”:ek ja%% !@^+~cepèk.
” Ngomong apaan tuh makin ngaco?”
“Aagrsfkmnvgrtermigf@35!” (9/8). di sini bahkan “bunyi tanpa arti,” bunyi pun mungkin bukan, karena sulit saya bunyikan tumpukan huruf mati itu. Bagaimana pun ia bisa menjadi bagian dari realitas sosial yang diolah jadi “bahasa.” Tampaknya berfungsi sebagai strategi mengaburkan fakta dengan kelakar.
Dari ke tiga teks tersebut di atas, tampaknya Obrolan Sukab menjadi bentuk teks yang paling messy, dibandingkan dua messy teks yang lain. Di sini fakta dan fiksi menyatu sepenuhnya.
Merekam Realitas dengan Messy Teks
Realitas dalam penelitian sosial-budaya direkam dengan teknik observasi, partisipasi, dan diperjelas dalam wawancara, tetapi yang tertangkap hanya yang kasat mata, dan bukan yang bisa dirasa.Tujuan riset untuk menjelaskan fenomena yang bisa diobservasi itu.
Para penulis sastra banyak juga yang melakukan riset, untuk membangun dunia fiksi, mencari realitas yang bisa dirasa yang diolah dari yang nyata. Batasan antara ilmu sosial-budaya dan sastra menjadi kabur, seperti yang dinyatakan oleh C.Geertz sebagai blurred genre[10]. Di sinilah messy teks menemukan maknanya: kelindan antara fakta dan fiksi, antara pengetahuan dan pengalaman hidup.
Sebenarnya lah realitas bukan hanya fakta yang kelihatan saja. Ia bisa bersembunyi dibalik relung batin; empati, emosi, benci, dendam, marah, adalah realitas batin. Pada titik ini kamera riset empiris tidak bisa tembus menyorotinya, meskipun fakta bisa dijadikan kendaraan untuk masuk ke dalam batin.
Erni harus ngibing dengan pria bau bir, ia meludah ke lantai. Ini adalah fakta, dan pada saat itu teks sebenarnya melakukan perlawanan diam. Realitas konflik batin dapat direkam oleh messy teks dengan melukiskan bagaimana Erni meludah dan menghapus wajahnya dengan handuk. Jadi, riset tentang messy teks bertujuan untuk menghadirkan realitas yang dirasa, yang ada dalam batin. Baik cerpen maupn novel dalam esei ini, membiarkan fakta tetap berjejak. Cerpen tidak menghilangkan pengalaman hidup cokek, dan novel tidak meninggalkan adat kebiasaan Mentawai.
Dalam Obrolan Sukab, fakta adalah isi obrolan pelanggan warung Anabel, yang tidak bisa diobservasi. SGA tidak menggunakan fakta untuk masuk ke relung batin. Faktanya ada dalam tataran yang berbeda dengan kedua genre terdahulu. Ia memperlihatkan bahwa tawa pun bisa merekam realitas batin, bukan rasa pedih seperti Erni, melainkan bentuk resonansidari masyarakat terhadap kekuasaan. Fakta ciptaan SGA memantulkan sinisme terhadap pejabat ahli keuangan yang juga merasa pintar berbahasa (23/8). Rakyat kecil dalam obrolanitu justru menguasai wacana dengan tawa dan plesetan. Fakta dijungkirbalikkan menjadi satire dan sindiran melalui permainan bahasa, yang direkam oleh tawa.
Adakah Kebenaran Dalam Messy Teks?
Bila realitas adalah sesuatu yang dirasa, maka kebenaran menyertainya.
Dalam cerpen, saat Erni ngibing dengan pria bau alkohol, ia meludah dan berdesis “huh”. Kebenaran di sini lahir dari suara messy teks; kelindan antara fakta dan fiksi. Dalam momen ngibing, kebenaran bersembunyi di balik desisan “huh,” menyusup ke dalam batin Erni. Fakta Erni ngibing dengan pria bau alkohol, berhenti dan menjadi data, yang kemudian berubah menjadi pengalaman rasa. “Huh” menjadi “gema batin,” bahasa tak terucap bagi kebenaran, tidak tampak, tapi ia ada. Pembaca bisa menjadi jengah dan marah. Dengan demikian, kebenaran batin tidak berhenti di tokoh cerpen, tapi beresonansi ke luar menjadi pengalaman bersama.
Kebenaran Burung Kayu ada dalam irama adat-kebiasaan yang dijalani. Cara menyapa nenek moyang, memanggil roh leluhur, menyapa hutan, membuat sajian dengan telinga kiri babi, itulah bahasa kebenaran orang Mentawai. Fiksi menjadikan adat sebagai ruang dengar, tempat suara masa lalu bisa didengar saat ini. Saat adat ditulis sebagai novel, ia memang kehilangan sedikit rohnya, tetapi justru menemukan nada kebenaran yang baru, yang hidup karena diceritakan. Ia melewati imajinasi; bukan fakta etnografi, tapi adanya kebersamaan, antara alam, manusia, dan yang gaib, yang tetap ada dan hidup karena diceritakan.
Dalam satire SGA, kebenaran tidak muncul dari jeritan batin Erni, atau adat-kebiasaan seperti dalam Burung Kayu. Akan tetapi ia hadir dari tawa, dari kata yang digeser agar terdengar lucu, dan mengandung getir. Tawa di warung Anabel bukan canda kosong; ia adalah cara rakyat menegakkan kebenaran tanpa harus berteriak. Kebenaran di sini adalah kejelian menertawakan yang berkuasa tanpa kehilangan harga diri. Dalam messy teks, tawa menjadi alat dengar batin, menyampaikan apa yang tidak bisa diucapkan langsung.
Kebenaran dalam messy teks tidak menuntut bukti. Realitas itu ada dalam batin, sehingga hanya suaranya yang bisa terdengar. Ia bukan hasil perhitungan statistik, tetapi bisa dirasa karena ia ada di sana. Lahir ketika fakta menyentuh rasa, ketika tafsir dan pengalaman saling mendengarkan. Mungkin messy teks hanya mengatakan bahwa kebenaran pun bisa ada dalam ruang batin, bila tidak dipaksa menjadi tunggal. Ia tumbuh dan menampung makna kesaksian dan juga pengalaman orang lain. Kadang benar, bukan berarti tepat (truth yang terbedakan dari untruth), melainkan tulus dan jujur.
Erni Cokek Teluk Naga, Burung Kayu, dan Obrolan Sukab telah saling menyapa. Mereka ada bersama di ruang tafsir yang terbuka, di relung batin suatu messy teks. Kebenaran ada di sana bersama mereka, bersama pembaca yang menjadi bagian dari teks, meneruskan yang belum selesai, serta menafsir yang tak terkatakan.
Dari ruang batin semacam inilah, manusia belajar mendengar suara yang sering luput dari aturan, hukum, dan kekuasaan. Negara memang tak bisa diatur dengan batin, tetapi tanpa batin, negara akan kehilangan arahnya, kehilangan nurani.
Bintaro, 28 Oktober 2025
[1] Denzin, Norman K. 1997. Interpretative Ethnography; Ethnographic Practices for the 21st Century. Sage Publication. London. New Delhi
[2] Echols, John M dan Shadily,Hassan. 2003 Kamus Inggris; An Indonesian – Engish Dictionary. Penerbit PT. Gramedia Jakarta: 379
[3] Clair, Robin Patric 2003. Expressions of Ethnography; Novel Approaches to Qualitative Methods. State University of New York Press
[4] Denzin, Norman K. 1997. Interpretative Ethnography; Ethnographic Practices for the 21st Century. Sage Publication. London. New Delhi
[5] Kleden-Probonegoro, Ninuk. Cerpen “Erni Cokek Teluk Naga”, (https://borobudurwriters.id/kolom/erni-cek/teluk-naga)
[6] . Clair, Robin Patric 2003. Expressions of Ethnography; Novel Approaches to Qualitative Methods. State University of New York Press.
[7] Kleden-Probonegoro, Ninuk. Tanpa tahun. “Cokek Sebagai Kasus Diverensiasi Multikultural”. MITRA; Jurnal Budaya & Filsafat. Edisi no. 10: 15-24
[8] . Erlang, Niduparas. 2023. Burung Kayu. Taroka Press.
[9] Seno Gumira Ajidarma 2025. Obrolan Sukab @ IHIK3
[10] Geertz, Clifford. 1987. “Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought.” Local Knowledge. BasicBooks.A Divission ofHarperCollins
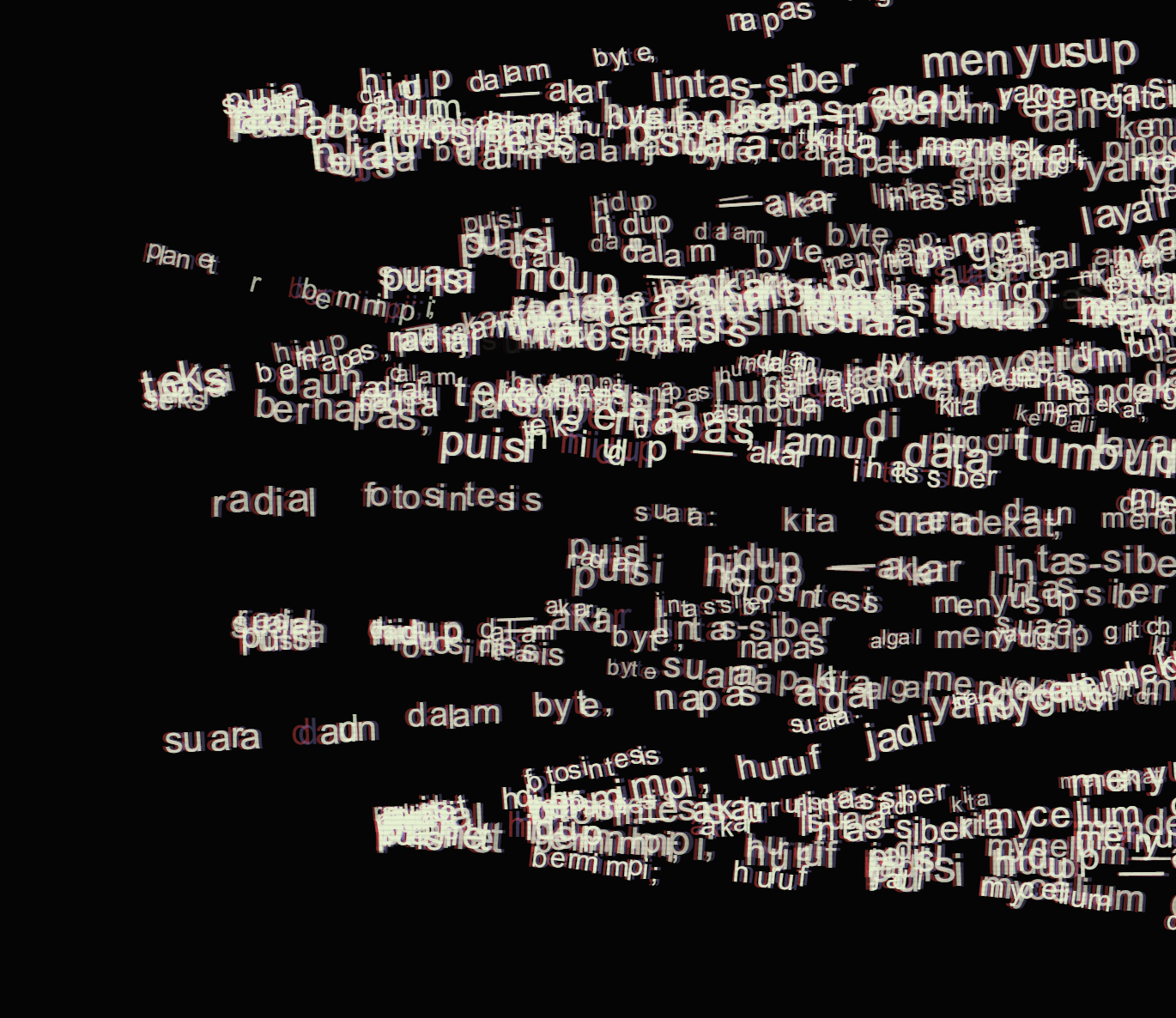
Post Comment