Pembatalan pada Novel Ajengan Anjing
Pembatalan pada Novel Ajengan Anjing
Novel ini berkisah tentang pesantren Bahrul Ulum di Citamiang, sebuah tempat di Garut Selatan yang terletak di antara Pantai Pameungpeuk dan hutan keramat Sancang. Sebuah pesantren yang lahir dari tangan dingin—atau mungkin lebih tepatnya, tangan sakti—Mama Aleh, pendirinya yang dihormati karena reputasi yang, kalau dipikir-pikir, seperti berasal dari komik silat.
Mama Aleh adalah generasi pertama, tokoh yang kehebatannya tidak hanya terkenal, tapi juga dilestarikan dalam bentuk anekdot yang membuat kita bertanya-tanya: ini riil atau karangan masa senggang? Salah satunya, ia konon pernah dicegat dan dipukuli oleh gerombolan DI TII. Ternyata, setelah puas memukul, gerombolan itu baru sadar bahwa objek kemarahan mereka bukan Mama Aleh, melainkan sebatang pohon. Versi lain menyebutkan, ada gerombolan lain yang mencoba menyerangnya, tapi mereka malah menumpahkan energi pada seekor babi hutan. Sebuah peringatan diam-diam: hati-hati, jangan-jangan musuh Anda adalah hasil editan realitas.
Rahasia kehebatan Mama Aleh? Salawat, katanya. Sesederhana itu. Tidak perlu amalan rumit atau jimat-jimat mistis. Hanya dengan rajin melafalkan salawat, ia menguasai seni hidup di dunia yang, jika digambarkan, seperti perpaduan antara folklore lokal dan cerita superhero versi tradisional. Kata-kata bagi Mama Aleh bukan sekadar ujaran; ia adalah mantra yang bisa membengkokkan kenyataan, mengubah pohon menjadi perisai, dan babi hutan menjadi tameng.
Namun, kehebatan Mama Aleh bukan hanya soal selamat dari serangan musuh, tapi juga bagaimana ia menanamkan filsafat yang selevel puisi epik. “Kita ini tak lebih baik daripada terong,” katanya. Dan, ya, ada sesuatu yang menyentuh di sana, meski mungkin terong di pasar tidak akan merasa tersanjung. Ia mengajarkan keselarasan dengan alam, membingkainya dalam ajaran yang lebih cocok untuk TED Talk ketimbang pidato Jumat biasa: bahwa manusia adalah saudara dari daun mangga, sepupu jauh pohon belimbing, dan, tentu saja, masih dalam satu kartu keluarga kosmis dengan kayu jati.
“Jaga akhlak kepada pohon, batang singkong, ikan-ikan, kepiting, ular sawah, keong, pohon cengkih, …. Sebab kita tak lebih baik daripada terong. Kita ini saudaranya daun mangga, sepupunya pohon belimbing, dan kerabat jauh kayu jati. Jaga akhlak, sebab Islam adalah akhlak.” Hal 61
Sekalipun Mama Aleh mampu menaklukkan dua dukun sakti dari hutan Sancang, ia tidak menjadi tiran yang arogan. Sebaliknya, ia menyerap kearifan lokal tempat itu. Hutan Sancang tetap lestari, jauh dari tangan-tangan yang tergoda untuk menebang atau menjarah. Barangkali, karena Mama Aleh paham, melawan dua dukun adalah soal kehormatan, tetapi melawan alam adalah bunuh diri yang sia-sia. Ia menerima kebijaksanaan itu, meresapinya, lalu menyebarkannya pada para pengikutnya dengan penuh rasa hormat, seperti menyampaikan resep rahasia yang diwariskan turun-temurun.
Setelah Mama Aleh, tampuk kepemimpinan jatuh kepada Ajengan Oyong, generasi kedua. Ajengan Oyong ini, untungnya, tidak mengalami sindrom “penerus yang gagal paham.” Ia melanjutkan pemikiran pendahulunya, menjaga harmoni yang diwariskan Mama Aleh. Bahkan, di bawah kepemimpinannya, Citamiang menjadi surga bagi anjing, yang—secara ironis—mewakili keseimbangan alam di sana. Begitu banyak anjing berkeliaran dengan damai sehingga kampung itu akhirnya disebut “Kampung Anjing.” Sebuah nama yang, meski tidak cocok untuk brosur wisata, memiliki daya tarik tersendiri.
Anjing-anjing itu ternyata membawa manfaat sosial yang tidak main-main. Tidak ada maling yang berani coba-coba menguji keberanian mereka di Kampung Anjing. Penduduk pun beradaptasi; anjing menjadi teman kerja, bukan sekadar penghias halaman. Mereka ikut diajak ke sawah, ke hutan, bahkan ke kebun, menggantikan peran kucing yang—sejujurnya—lebih cocok untuk rebahan di dapur daripada berkontribusi dalam perekonomian lokal. Di Citamiang, anjing adalah partner produktif, bukan sekadar pelengkap hidup.
Kehidupan berlangsung indah di Citamiang. Orang-orang dan anjing hidup akur di bawah kepemimpinan Ajengan Oyong. Pesantrean Bahrul Ulum menjadi cahaya bagi kampung, dan anjing-anjinglah yang menjaga cahaya itu tetap menyala. Orang-orang berbahagia. Anjing-anjing berbahagia. Hal 208.
Namun, seperti dongeng-dongeng yang sering kali berakhir pahit, harmoni itu runtuh ketika Ajengan Oyong wafat. Kepemimpinan berpindah ke generasi ketiga: Ceng Aom, yang, entah kenapa, seperti kehilangan semua pelajaran dari generasi sebelumnya. Bagi Ceng Aom, anjing bukan lagi simbol keselarasan alam, melainkan ancaman moral yang harus disingkirkan. Ia melarang santri-santrinya berbagi makanan sisa dengan anjing. Bahkan, ia mendesak seluruh warga untuk mengusir anjing-anjing yang selama ini hidup berdampingan dengan mereka. Bukan sekadar perintah, ini seperti deklarasi perang terhadap sejarah dua generasi yang penuh damai.
Jika manusia bukanlah makhluk suci, dan anjing pun bukanlah makhluk suci, mengapa Ceng Aom tidak bisa berdamai dengan najis anjing sedangkan di saat yang sama dirinya bisa berdamai dengan dosanya sendiri. Hal 269.
Keputusan Ceng Aom ini menimbulkan ironi yang menggigit. Jika anjing dianggap terlalu najis untuk hidup di kampung itu, bagaimana dengan manusia-manusianya? Apakah mereka lebih suci daripada makhluk yang selama ini menjaga mereka dari maling dan memberi mereka arti tentang harmoni? Atau mungkin, keputusan ini hanyalah refleksi lain dari kebiasaan manusia: melupakan kearifan masa lalu demi kebodohan yang dibungkus dengan selimut moralitas baru.
Kritik semacam itu sesungguhnya berkecamuk dalam pikiran banyak warga. Mereka diam-diam membandingkan Ceng Aom dengan pendahulunya, membatin tentang kejanggalan keputusannya. Namun, suara-suara itu hanya sebatas desah angin di tengah malam, terlalu lemah untuk menembus tembok keangkuhan sang pemimpin. Ceng Aom, dengan caranya yang khas, menutup rapat-rapat ruang diskusi. Semakin ia dipertanyakan, semakin keras suaranya menindas. Ia tidak ingin pendapatnya diuji; ia ingin perintahnya dipatuhi. Bagi Ceng Aom, menjadi seperti Bapak dan Kakeknya berarti memiliki otoritas yang tak tergoyahkan, di mana kata-kata tidak diukur dengan logika, melainkan dengan kepatuhan.Pertanyaan adalah pembangkangan, pembelotan umat.
Dan warga, meski hatinya memberontak, hanya bisa mengangguk pasrah. Bagaimanapun, Ceng Aom adalah ulama, dan ulama—apalagi yang punya garis keturunan ulama—tidak sekadar dianggap berilmu, tetapi juga pemegang otoritas absolut. Hukumannya atas kritik tidak tertulis, tetapi semua orang tahu risikonya: menjadi orang yang terbuang di kampungnya sendiri. Dalam tradisi itu, aturan dari seorang ulama seperti garis lurus tanpa kelokan—saklek dan mutlak.
Tragedi akhirnya tiba tanpa puisi penghibur. Satu-satunya anjing yang masih tersisa, seekor makhluk setia yang entah bagaimana luput dari eksodus massal, ditemukan mati mengenaskan. Diracun. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia ada. Sebuah akhir yang lebih cocok untuk kisah distopia daripada kampung yang dulu bernama Kampung Anjing. Kini, yang tersisa hanyalah kesunyian yang dipaksakan, tanpa gonggongan, tanpa jejak harmoni yang pernah membuat Citamiang begitu hidup.
Membaca novel ini untuk pertama kalinya membuat saya menyadari mengapa di kampung-kampung hari ini warganya tampak lebih malas pergi ke kebun. Jawabannya sederhana: tidak ada lagi anjing. Kenapa kebun-kebun dibiarkan terbengkalai dan ditumbuhi ilalang? Lagi-lagi karena tidak ada anjing. Kehadiran anjing dalam rutinitas sehari-hari ternyata bukan sekadar pelengkap. Ia memengaruhi ritme hidup, membentuk kebiasaan, dan pada akhirnya menentukan produktivitas.
Namun, tanpa anjing, warga kini lebih senang memelihara kucing. Ya, kucing—makhluk rumahan yang pemalas, manja, dan, terus terang, terlalu narsistik untuk peduli pada dunia di luar dirinya sendiri. Kucing tidak akan menjaga palawija, apalagi melindungi tuannya dari bahaya di kebun. Ia tidak akan menggonggong memperingatkan pencuri, tetapi mungkin dengan anggun akan menjilat kaki mereka. Ketika anjing dihapus dari kehidupan, aktivitas pertanian pun seperti ikut menghilang—atau, lebih tepatnya, dibatalkan.

Pembatalan adalah kata kunci yang melingkupi tema novel ini. Dalam filsafat dekonstruktif, pembatalan mengurai kontradiksi yang tak bisa lagi dibiarkan berdampingan. Novel ini membatalkan keintiman harmonis antara manusia dan alam, antara warga kampung dan anjing, dengan menghadirkan superioritas salah satu pihak dan marginalisasi pihak lain. Apa yang dibatalkan adalah narasi kebersamaan, kehadiran makhluk yang menjadi penjaga, sahabat, dan mitra kerja. Ironisnya, semakin anjing-anjing itu dihapus, semakin jelas jejak mereka. Novel ini tidak hanya memberi ruang bagi anjing untuk “berbicara,” tetapi juga menjadikan mereka elemen sentral dan provokatif—terutama dalam judulnya: Ajengan Anjing.
Pembatalan berikutnya yang dijelajahi novel ini adalah tradisi intelektual dalam dunia Islam. Secara khusus, novel ini menyoroti tradisi yang menghubungkan intelektualitas dengan garis darah—sebuah tradisi feodal yang terlalu sering dianggap sakral. Dalam kultur semacam ini, jika seseorang adalah ulama, maka anak dan cucunya otomatis berhak atas gelar yang sama, sementara yang lain tidak punya hak sama sekali. Novel ini menunjukkan bagaimana tradisi semacam itu gagal bertahan. Pemikiran visioner Mama Aleh memang berhasil diteruskan oleh Ajengan Oyong, tetapi begitu sampai pada generasi ketiga, Ceng Aom, semuanya batal total. Keangkuhan garis darah justru menjadi penyebab gagalnya kepercayaan terhadap garis darah itu sendiri.
Di sini, novel ini pun menyentil salah satu prinsip Islam yang fundamental: rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Prinsip ini, sebagaimana diungkapkan, tidak hanya berlaku bagi manusia tetapi juga bagi makhluk lain, termasuk anjing—makhluk yang dalam tradisi dianggap najis. Tetapi kasih sayang ini, ketika diserahkan kepada tokoh yang gagal memahaminya, justru batal dengan sendirinya. Islam yang seharusnya menjadi ajaran keselamatan bagi semua justru berubah menjadi ajaran pengucilan bagi yang dianggap tidak sesuai dengan standar suci versinya, tafisrnya.
Dan pembatalan berikutnya hadir dalam struktur alur cerita novel itu sendiri. Jika pada umumnya sebuah novel membangun konflik utama dengan menyisipkan konflik-konflik kecil yang perlahan memuncak hingga meledakkan pikiran pembaca, hal semacam itu tidak terjadi di sini. Novel ini bermain dengan harapan dan, tentu saja, membatalkannya.
Sejak awal, pembaca disuguhi narasi yang cukup koheren: siapa pendiri Bahrul Ulum, lalu siapa penerusnya di generasi kedua, hingga akhirnya siapa yang mengambil tongkat estafet di generasi ketiga. Koherensi ini memberikan struktur yang terasa solid, nyaris tak tergoyahkan, sampai—secara tiba-tiba—sebuah fragmen berjudul “Madsahdi” muncul seperti tamu tak diundang dalam pesta yang terencana.
Fragmen ini memperkenalkan Madsahdi, seorang manusia sebatang kara yang keluarganya dibantai, diperkosa, dan dirampas hartanya karena dituduh sebagai PKI. Ceritanya berdiri sendiri, menghantam emosi dengan keras dan tanpa kompromi. Masalahnya, fragmen ini terasa seperti cerita yang berbeda, hampir tidak relevan dengan alur tentang Bahrul Ulum, Mama Aleh, atau Ceng Aom. Kehadirannya menjadi semacam pembatalan struktur narasi yang sudah dibangun sejak awal. Dan akibatnya, momen emosional ketika Ceng Aom memusuhi anjing dan membatalkan ajaran generasi pertama malah terasa kurang menghunjam. Fragmen Madsahdi terlalu kuat, terlalu mencuri perhatian, hingga konflik utama seolah tertelan oleh cerita yang berdiri di luar alur.
Namun, bagi penikmat dekonstruksi, bagian ini justru menarik. Pembatalan semacam ini bukan hanya sesuatu yang bisa diterima, tetapi bahkan diharapkan. Bukankah kehidupan itu sendiri seringkali berjalan seperti itu? Sebuah perjalanan yang sudah dirancang rapi mendadak belok tanpa aba-aba, berhenti di tengah jalan tanpa peringatan, atau tiba-tiba diinterupsi oleh sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Dalam dunia nyata, koherensi jarang menjadi raja; yang ada justru kekacauan, gangguan, dan belokan tajam. Fragmen Madsahdi menjadi pengingat bahwa dalam setiap narasi—baik di buku maupun kehidupan—tidak ada kepastian yang benar-benar pasti.
Akhirul kalam, novel yang ditulis Ridwan Malik ini, anjing banget! Isinya, bukan tentang bagong yang susah belok.
Singajaya, Akhir 2024
Deri Hudaya, pengelola HumaNiniNora
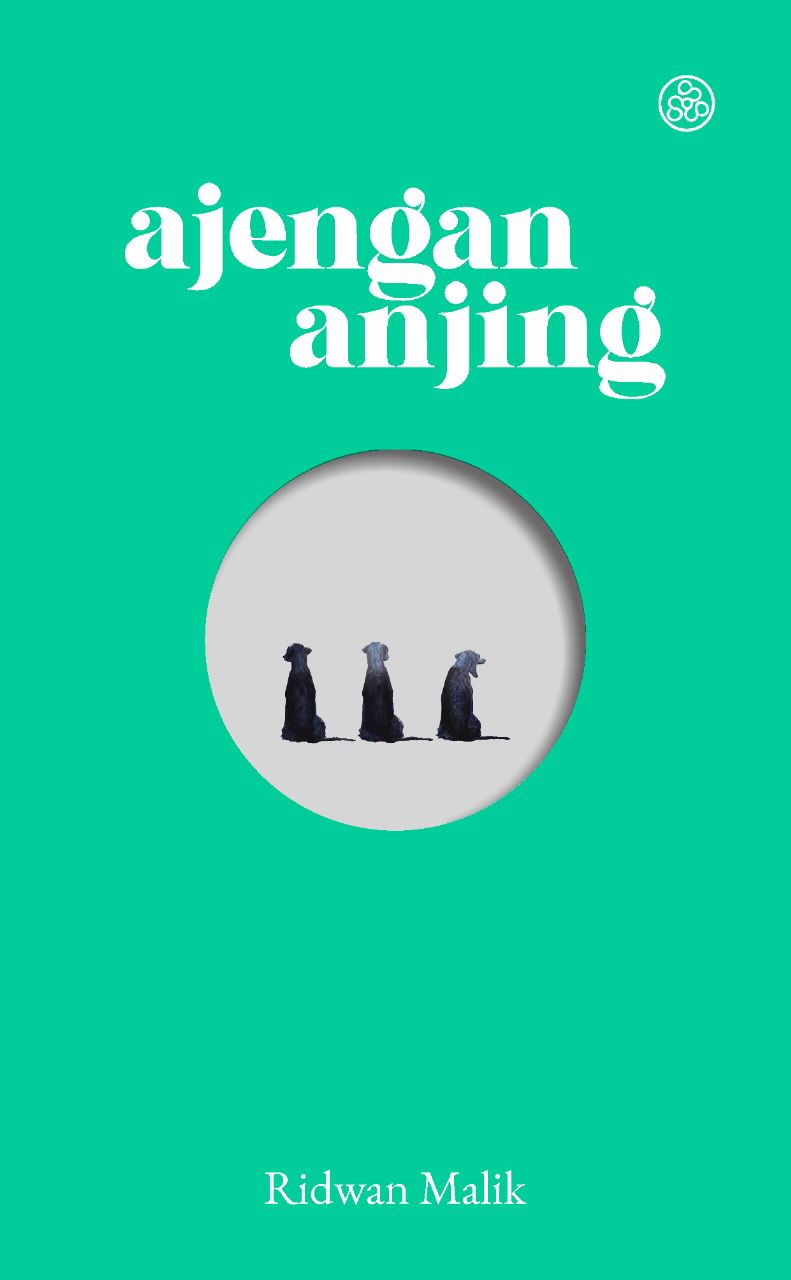
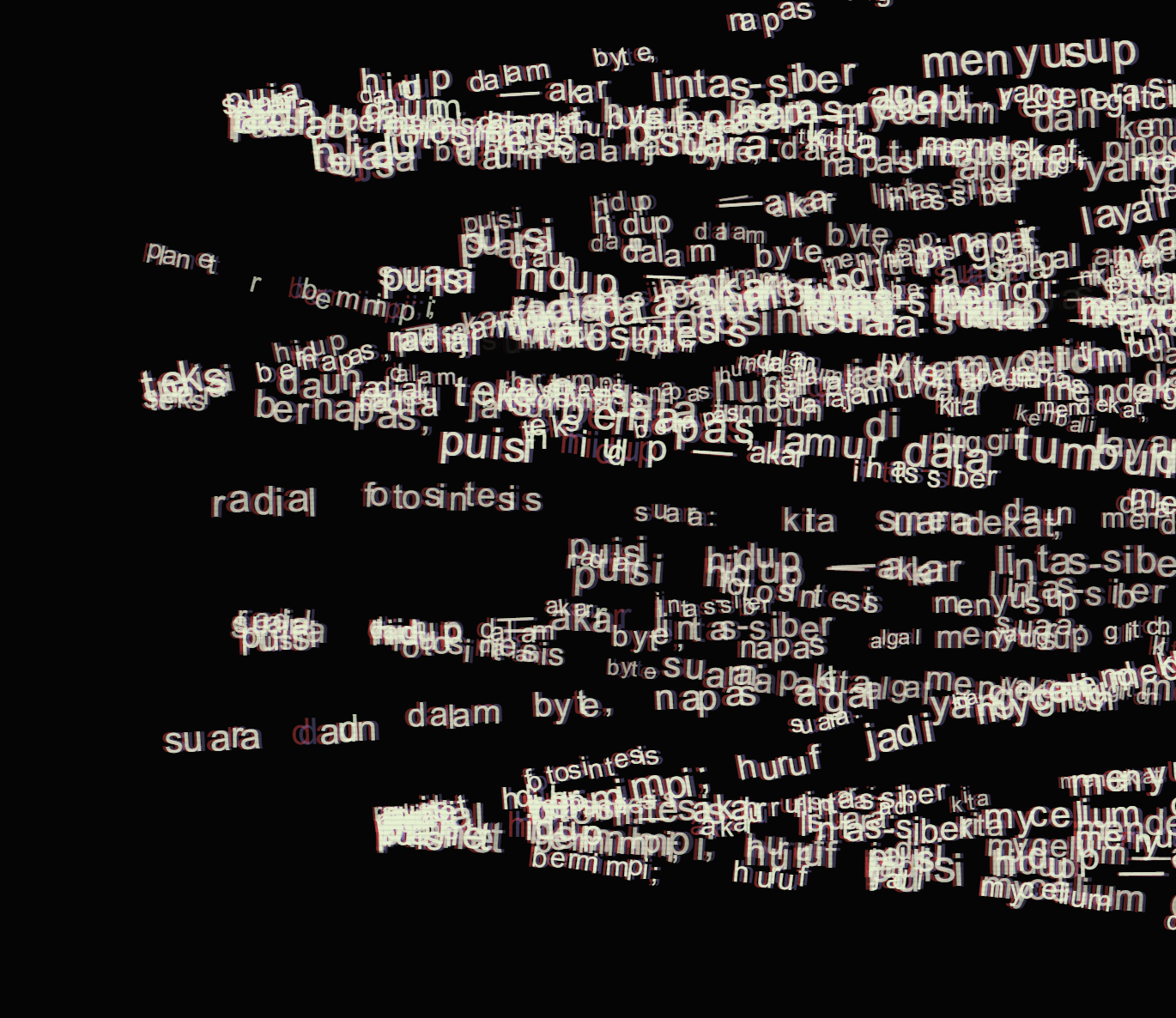
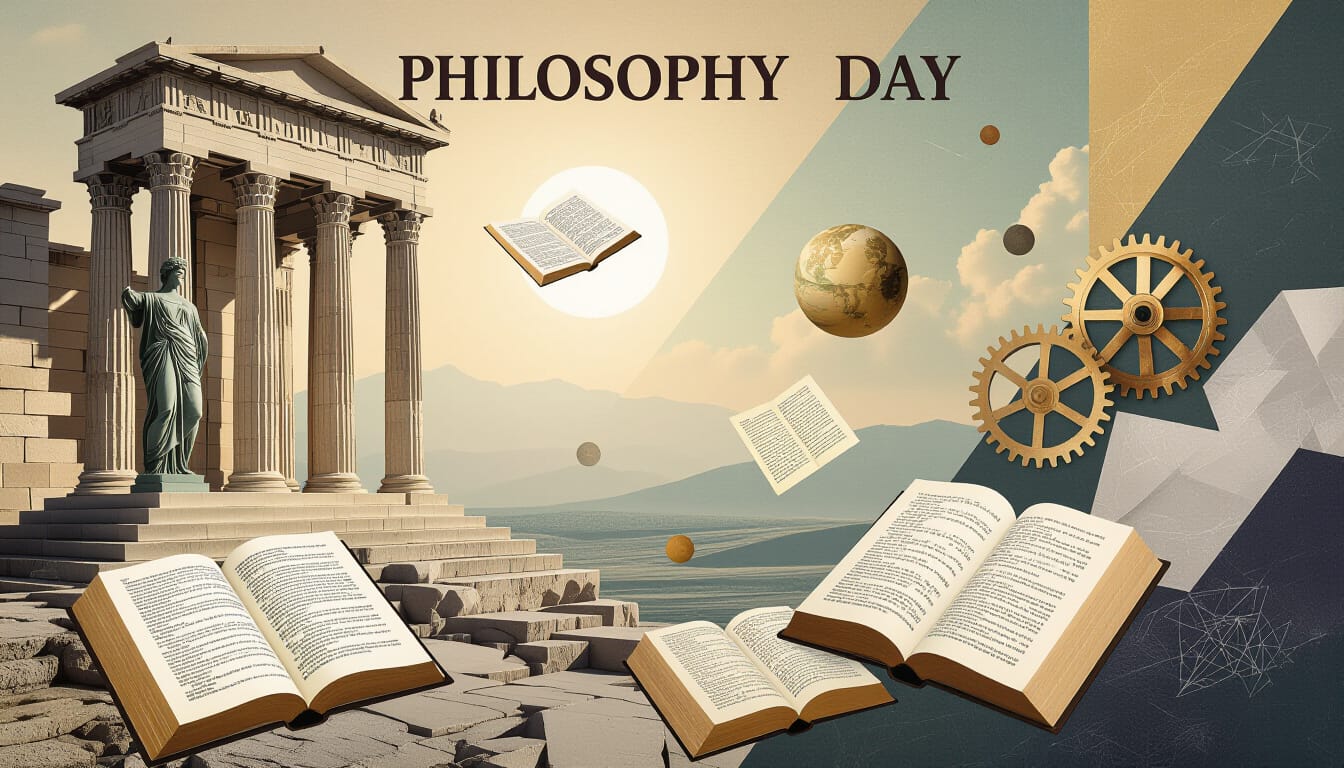
2 comments