AI dan Masa Depan yang Tak Pernah Kita Minta
“We have to continually be jumping
off cliffs and developing our wings
on the way down.”
Kita terus-menerus harus melompat
dari tebing dan mengembangkan
sayap kita saat jatuh.
–Kurt Vonnegurt
Di kawasan Blok M, seorang pria yang sering dijuluki “Taylor Swift-nya teknologi” duduk di antara aroma satai dan bising klakson bajaj. Jensen Huang, CEO NVIDIA dan salah satu arsitek utama revolusi kecerdasan buatan (AI), tampak santai berbincang dengan Najwa Shihab– juga Vikram Sinha, CEO Indosat. Pertemuan ini seakan menjadi panggung ironis, di mana pembicaraan tentang kecerdasan buatan senilai triliunan dolar berlangsung di atas meja plastik yang hampir goyah karena beban satai.
Baca juga: Hari AI Indonesia dan Riset Total Dunia
Kehadiran Jensen di Indonesia bukan sekadar kunjungan biasa. Ia datang dengan ambisi besar: membangun Indonesia sebagai negara AI dan meresmikan “Hari AI Nasional.” Namun, seperti kata Kurt Vonnegut, dalam usaha melompat dari tebing teknologi, apakah kita benar-benar sudah siap mengembangkan sayap, atau justru sedang jatuh bebas tanpa tujuan?
Momen itu, dialog di antara tiga tokoh tersebut membuka diskusi menarik tentang potensi, tantangan, dan absurditas AI dalam kehidupan modern, terutama ketika teknologi canggih bertemu realitas negara berkembang. Bagaimana AI, yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan besar dunia, diterapkan di negara di mana kabel internet sering kali bersaing ruang dengan jemuran pakaian? Di sinilah satire menemukan ruangnya untuk berbicara.
AI, Jansen Huang, dan Kita
Dalam perbincangan tersebut, Jensen Huang menekankan bahwa AI memiliki potensi untuk mendemokratisasi pengetahuan. Dengan teknologi ini, siapa pun bisa mengakses informasi yang sebelumnya terbatas pada kalangan tertentu. Ia menggambarkan AI sebagai tutor pribadi, mampu memberikan jawaban langsung dan menjadi mitra dalam menyelesaikan masalah. Namun, optimisme ini menghadapi kenyataan bahwa akses terhadap teknologi di Indonesia masih jauh dari merata. Bagaimana AI bisa mendemokratisasi sesuatu yang bahkan fondasinya, seperti akses internet stabil, masih menjadi barang mewah di banyak daerah?
Huang juga menyebutkan bahwa bisnis kecil tidak perlu membangun AI sendiri. Negara atau perusahaan besar bisa menyediakan layanan tersebut untuk membantu pedagang kaki lima hingga pengusaha mikro. Gagasan ini terdengar mulia, tetapi mari kita lihat realitanya: berapa banyak pedagang angkringan yang akan menggunakan AI untuk menghitung margin keuntungan ketimbang memanfaatkan cara tradisional? Di sisi lain, gagasan ini malah memperbesar ketergantungan pada korporasi besar, menciptakan semacam kolonialisme digital di mana yang kecil terus-menerus bergantung pada yang besar.
Selain itu, percakapan itu menyentuh soal bagaimana AI dapat membantu mempercepat penemuan ilmiah, mulai dari perubahan iklim hingga pengembangan obat-obatan. Namun, ironi besar terletak pada kenyataan bahwa masalah seperti perubahan iklim sebenarnya dipicu oleh sistem yang sama yang kini menjual AI sebagai solusi. Apakah AI benar-benar dapat memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kapitalisme industri, atau hanya menjadi alat baru untuk melanggengkan sistem yang sama?
Pendidikan juga menjadi sorotan dalam diskusi ini. Huang menyatakan bahwa di masa depan, keterampilan coding mungkin tidak lagi penting bagi kebanyakan orang. Sebaliknya, pendidikan harus fokus pada kompetensi seperti logika, filsafat, dan cara mengajukan pertanyaan yang efektif kepada AI. Ini adalah visi yang menarik, tetapi apakah kita telah siap bertransisi ke era di mana pendidikan berbasis dialog dengan mesin menggantikan interaksi manusia yang penuh nuansa? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah maraknya kecenderungan teknologi untuk menggantikan pekerjaan manusia.
Namun, diskusi ini juga mencerminkan sisi lain dari narasi AI: ketakutan dan kesalahpahaman yang sering kali dipupuk oleh media dan film. Banyak orang mengkhawatirkan skenario dystopia di mana AI mengambil alih dunia, padahal kenyataannya, ancaman terbesar AI mungkin bukan pada teknologinya, tetapi pada bagaimana manusia menggunakannya. Sebagaimana Huang mengingatkan, membangun AI secara bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan teknologi ini digunakan secara positif.
Optimisme Huang memang memikat, tetapi tidak boleh melupakan kenyataan bahwa teknologi hanyalah alat. Tanpa regulasi yang jelas dan pendekatan yang etis, AI dapat dengan mudah menjadi alat eksploitasi baru. Dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan teknologi dan pendidikan masih menjadi tantangan besar, AI mungkin lebih berpotensi memperbesar ketimpangan daripada menjembataninya.
Percakapan antara Najwa Shihab dan Jensen Huang adalah potret dari dilema teknologi modern: di satu sisi, ada janji kemajuan yang hampir utopis; di sisi lain, ada risiko bahwa janji tersebut hanya menjadi narasi kosong yang mengaburkan masalah yang lebih mendasar. Vonnegut mungkin akan tersenyum pahit mendengar optimisme ini, sambil mengingatkan kita bahwa teknologi, sebagus apa pun, tidak akan pernah bisa menggantikan kemanusiaan itu sendiri.
Antara Solusi dan Ilusi
Percakapan antara Jensen Huang dan Najwa Shihab memang menyajikan visi besar tentang masa depan yang ditenagai oleh AI, tetapi juga meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Optimisme Huang tentang bagaimana AI dapat mendemokratisasi pengetahuan dan mempercepat kemajuan manusia adalah sebuah mimpi yang menggoda. Namun, seperti halnya semua mimpi besar, realitasnya penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan akses terhadap teknologi dan pendidikan masih menjadi momok, AI dapat menjadi pedang bermata dua: membuka peluang bagi yang mampu mengaksesnya, tetapi sekaligus memperdalam ketidakadilan bagi mereka yang masih tertinggal.
Vonnegut pernah mengingatkan bahwa kemajuan teknologi sering kali tidak lebih dari alat untuk menutupi ketidakadilan yang lebih besar. AI mungkin adalah puncak dari ironi tersebut. Ia dirancang untuk memberikan solusi, tetapi kerap menjadi katalis bagi masalah yang lebih dalam. Ketika Huang berbicara tentang potensi AI untuk mempercepat penemuan ilmiah atau mendukung bisnis kecil, pertanyaan yang harus kita tanyakan bukanlah seberapa hebat teknologi ini, tetapi untuk siapa teknologi ini sebenarnya bekerja?
Penutup dari diskusi ini tidak seharusnya menjadi tepuk tangan semata, melainkan juga ajakan untuk berpikir dan sedikit mempertanyakannya. AI bukanlah penyelamat dan Huang bukanlah nabi, dan kita harus menahan godaan untuk memperlakukannya sebagai jawaban atas segala persoalan. Teknologi ini, seperti pisau bedah, hanya seefektif tangan yang menggunakannya. Tanpa kebijakan yang inklusif dan etis, AI akan menjadi alat bagi segelintir orang untuk mengontrol lebih banyak, sementara yang lainnya hanya menjadi penonton dalam revolusi yang seharusnya menjadi milik semua orang.
Di akhir percakapan, kita diingatkan akan peran manusia, bukan AI, dalam membentuk masa depan. Jika kita gagal memahami bahwa teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya, maka optimisme Huang hanya akan menjadi dongeng modern yang berakhir tanpa klimaks. Dan mungkin, jika Vonnegut masih hidup, ia akan menulis cerita satire tentang bagaimana manusia sekali lagi terpikat oleh mainan baru yang menjanjikan segalanya, tetapi melupakan apa yang benar-benar penting: keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan itu sendiri.
“Science is magic that works,” tulis Vonnegut dalam Cat’s Cradle, menyindir betapa manusia sering terlalu terpesona pada teknologi tanpa peduli akibatnya. Pesannya jelas: berhentilah memuja teknologi, kecuali kalau ingin hidupmu berubah menjadi eksperimen gagal.
Deri Hudaya, tulisan-tulisannya terdokumentasikan di HumaNiniNora. Saat ini tengah menyiapkan buku berjudul Dari Overthinking ke Overachieving: Meditasi, Logika, Tulisan.



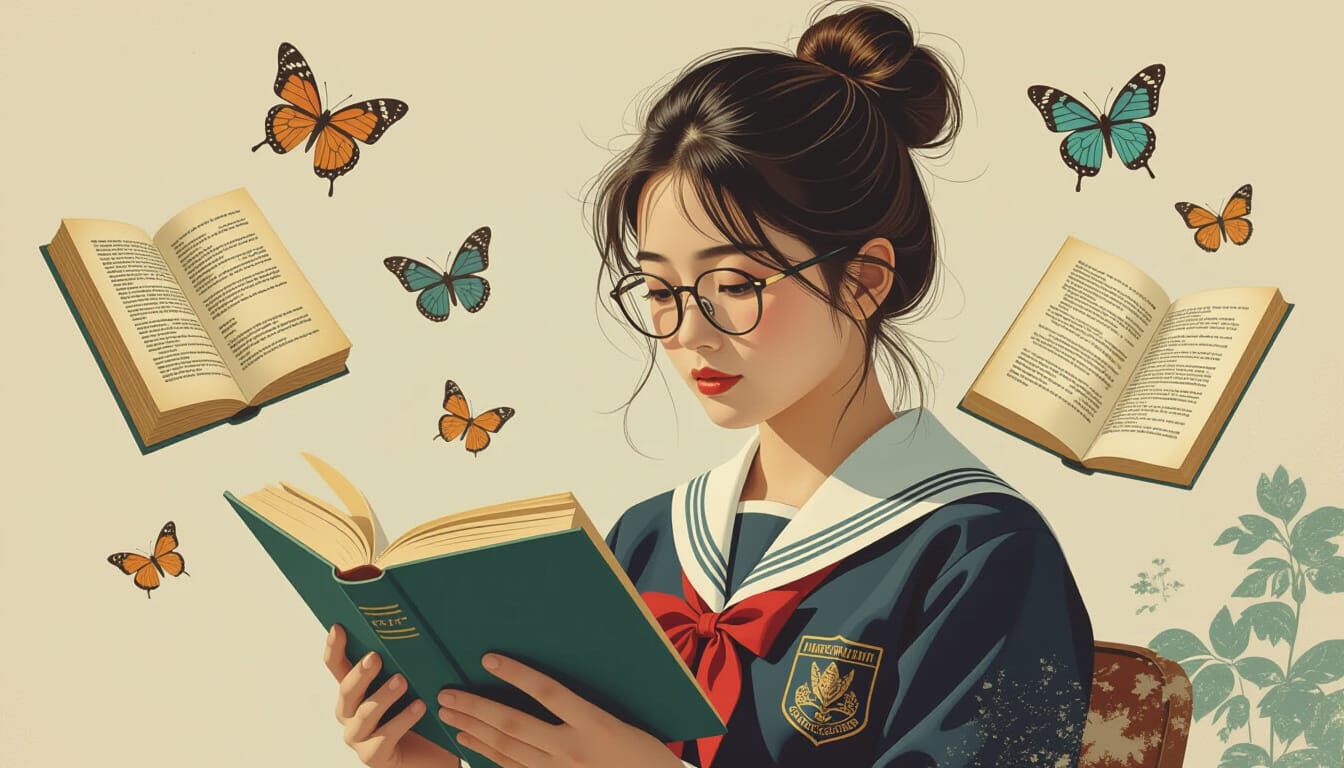
Post Comment