Industrialisasi Makanan Sehat
Tadinya, makanan sehat adalah soal bumi, hujan, dan sedikit keberuntungan. Sebatang wortel ditarik dari tanah, dibilas sungai, lalu dimakan di bawah matahari yang terik. Tidak ada label organic-certified, tidak ada diskusi soal superfood, tidak ada kursus plant-based lifestyle berharga jutaan. Hanya manusia, tanah, dan rasa lapar.
Namun dunia berubah. Kita berpindah dari sawah ke swalayan, dari pasar becek ke pop-up market berpendingin ruangan. Dalam perubahan itu, sesuatu yang dulu bersifat alami kini menjadi barang dagangan. Kita menyaksikan — tanpa cukup marah — bagaimana “makanan sehat” dijadikan industri, dikomodifikasi, diberi merek, dan tentu saja, dijual lebih mahal. Dalam saku korporasi besar, sebutan sehat tidak lagi tentang nutrisi, tetapi tentang margin laba.
Lihatlah rak-rak berwarna pastel di toko swalayan mewah. Ada granola artisanal dalam toples kaca mungil, dihargai lebih tinggi dari upah harian buruh tani. Ada jus hijau yang, kata labelnya, mengandung “detoksifikasi alamiah”, meskipun tubuh manusia sudah dilengkapi ginjal untuk itu sejak ribuan tahun lalu. Ada pula meat-free nuggets, berlabel plant-based, yang setelah ditelisik, ternyata penuh aditif dan melalui lebih banyak pabrik daripada potongan ayam di warung Padang.
Industri telah menemukan tambang emas baru: kecemasan manusia modern. Kecemasan tentang tubuh, tentang usia, tentang penyakit yang samar-samar mengintai di balik hidangan cepat saji. Maka muncullah produk-produk yang menjanjikan clean eating, whole food diet, atau alkaline body balance, lengkap dengan selebriti yang memamerkan kulit bersinar dan perut rata. Sehat, kini, adalah status simbol — bukan lagi kebutuhan dasar.
Michael Pollan, dalam In Defense of Food (2008), menyindir fenomena ini dengan cerdas: “Eat food. Not too much. Mostly plants.” Tapi industri tidak suka nasihat sederhana. Mereka membutuhkan ketidakpastian, membutuhkan kata-kata baru yang rumit — probiotic-enriched, gut-friendly, immune-boosting superfoods — supaya konsumen merasa perlu membeli sesuatu yang seharusnya sudah ada di dapur mereka: sayuran biasa.
Lebih parah lagi, industrialisasi makanan sehat menciptakan jurang baru antara si kaya dan si miskin. Di kota-kota besar, seorang eksekutif muda bisa menghabiskan setengah juta rupiah untuk salad quinoa dan smoothie bowl berwarna ungu cerah. Sementara di gang-gang sempit, pilihan tetap jatuh pada mie instan dan nasi putih, bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena harga dan ketersediaan. Ironi ini merayap diam-diam, seperti tikus malam di belakang dapur, dan kita — para pengkhotbah gaya hidup sehat — sering kali menjadi bagian dari masalah.
Di satu sisi, kita tak bisa menyalahkan semua orang. Manusia ingin hidup lebih lama, lebih bugar, lebih cantik. Keinginan itu dijual kembali kepada kita dalam bentuk bubuk protein, suplemen vitamin C liposomal, dan makanan ringan gluten-free yang anehnya justru lebih manis dari kue ulang tahun. Inilah capitalism in a nutshell: mengidentifikasi rasa takut, lalu mengubahnya menjadi produk.
Yang ironis, makanan sehat sungguhan — yang sesungguhnya — masih ada. Ia tersembunyi di pasar-pasar tradisional, di kebun kecil nenek, di ikan asin dan lalapan, di tahu-tempe tanpa kemasan. Tapi karena tidak mengkilap, tidak berbahasa Inggris, tidak diendors selebgram, makanan ini luput dari perhatian. Bahkan mungkin dipandang rendah.
Di zaman ini, menjadi sehat tidak cukup. Kita juga harus terlihat sehat — di Instagram, di TikTok, di rapat-rapat daring. Tubuh bukan lagi rumah yang perlu dirawat, tetapi etalase yang harus dipamerkan. Dan di sinilah industrialisasi makanan sehat menemukan puncaknya: ketika makan tidak lagi soal hidup, tetapi soal citra.
Jika kita masih peduli, barangkali saatnya merebut kembali definisi makanan sehat dari tangan mereka yang menjualnya dalam botol plastik. Kita kembali ke sayuran seadanya, beras dari ladang lokal, lauk pauk sederhana tanpa daftar bahan baku sepanjang novel. Kita makan bukan untuk gaya hidup, tetapi untuk hidup itu sendiri.
Atau, jika kita gagal, bersiaplah: kelak, bahkan mengunyah akan dikenakan pajak, sepanjang disertai label low-carb, keto-certified, dan non-GMO.
Referensi:
- Pollan, Michael. In Defense of Food: An Eater’s Manifesto. Penguin Press, 2008.
- Nestle, Marion. Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health. University of California Press, 2002.


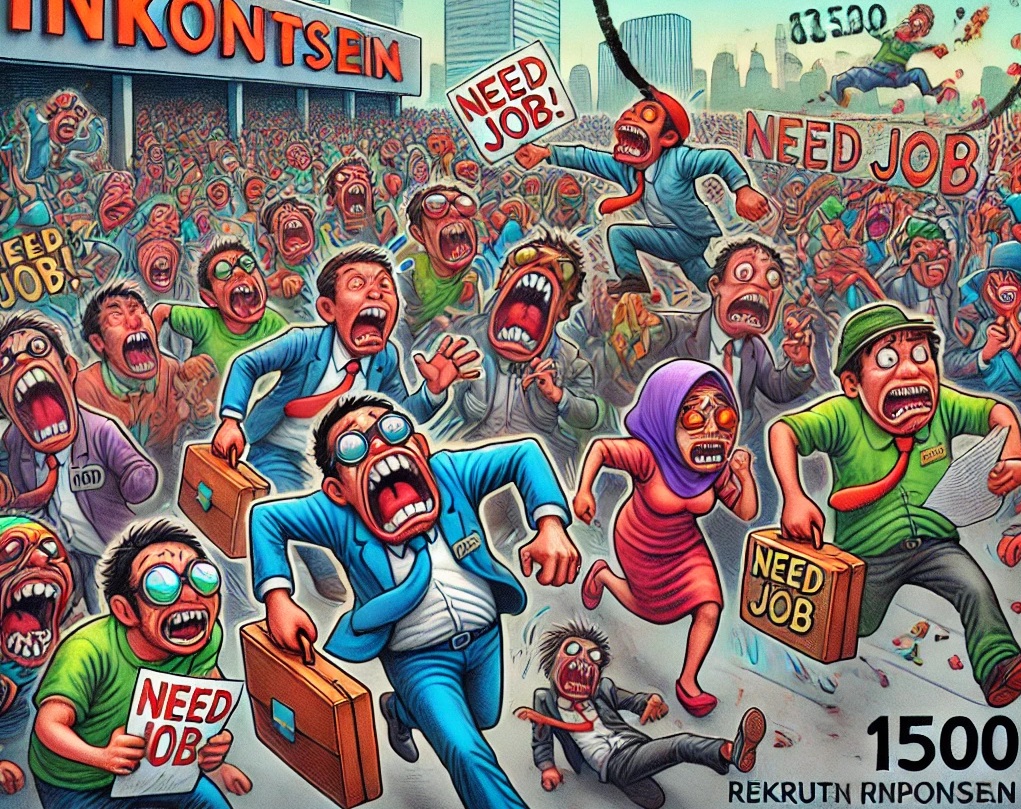
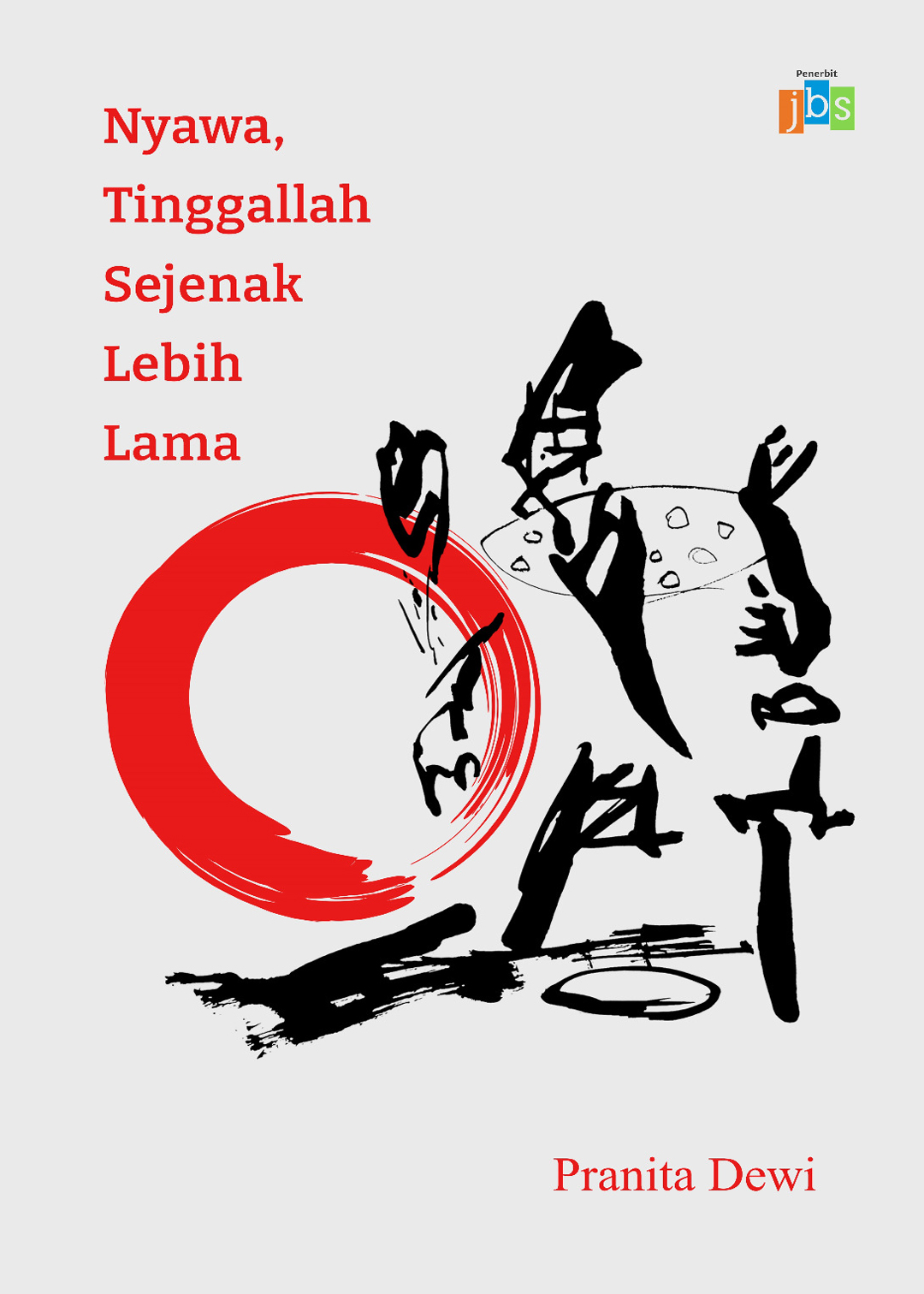
Post Comment